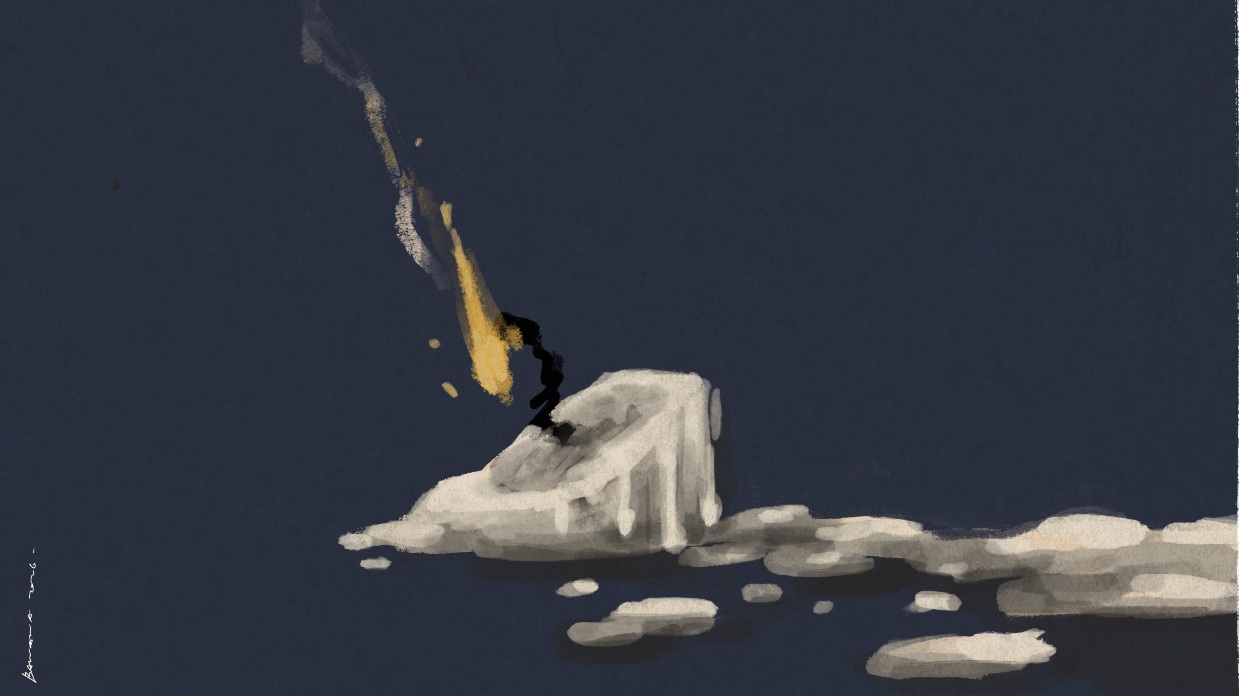MAHASISWA BERSUARA: Ketika Aksi Demonstrasi Tak Lagi Cukup: Membaca Negara, Merumuskan Perlawanan Hari Ini
Jika demokrasi ingin dipertahankan, medan perlawanannya harus diperluas: dari jalanan menuju keseharian, dari reaksi menuju pengorganisiran.

Cindy Veronica Rohanauli
Mahasiswa S1 Hubungan Internasional Unpad, Ketua Umum LPPMD Unpad 2024, bergiat di Aksi Kamisan Jatinangor.
7 Februari 2026
BandungBergerak – Selain tahun baru, awal 2026 juga menandai sebuah babak baru penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Per 2 Januari, secara resmi berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Mengok perjalanannya yang panjang, berliku, dan bahkan berbatu, sulit rasanya bagi kita untuk merayakannya.
Sepanjang tahun 2025, jalan-jalan di berbagai kota di Indonesia telah menjadi saksi gelombang protes. Aksi demonstrasi silih berganti hadir, membawa tuntutan yang tidak terbatas pada penolakan Revisi KUHAP, tetapi juga seruan untuk mencabut dan menolak banyak regulasi serta kebijakan lain yang disusun melalui proses yang tidak demokratis dan merugikan kepentingan masyarakat luas—terutama mereka yang berada pada posisi rentan. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba, RUU TNI, dan kenaikan tunjangan DPR adalah sebagian dari daftar kebijakan yang dipersoalkan. Di saat yang sama, tuntutan untuk segera mengesahkan regulasi yang dianggap krusial untuk menjamin akuntabilitas negara dan perlindungan sosial—seperti RUU Perampasan Aset, RUU Ketenagakerjaan, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Adat—juga terus disuarakan. Namun, rangkaian aksi-aksi tersebut cenderung membawa kita pada ujung yang sama: kebijakan yang dipersoalkan tetap disahkan, sementara peraturan yang didesakkan justru mandek tanpa tindak lanjut yang serius.
Di tengah hujan penolakan, negara—melalui aparat—merespons suara-suara kritis masyarakat dengan berbagai bentuk represi. Tahun 2025 tidak hanya diisi oleh spanduk, poster, dan seruan di jalanan, tetapi juga oleh daftar panjang nama-nama mereka yang ditangkap, ditahan, dan ditersangkakan. Bentrokan fisik, intimidasi, serta teror menjadi pengalaman yang secara kolektif menimpa mereka yang kritis. Kehadiran aparat pun tidak lagi terbatas pada titik-titik demonstrasi, tetapi juga merembes ke ruang-ruang yang sebelumnya terasa relatif privat, seperti kampus, forum diskusi, dan kehidupan sehari-hari.
Jika kemenangan dalam demokrasi hari ini dimaknai sebagai kemampuan masyarakat untuk menghentikan lahirnya kebijakan yang merugikan kepentingan publik, terutama kelompok rentan, maka harus diakui bahwa kita telah berkali-kali kalah. Bagi banyak orang yang terlibat langsung dan mempertaruhkan tubuh dalam kerja pengorganisiran aksi dan turun ke jalan, rangkaian kekalahan ini meninggalkan lelah, luka, dan—dalam banyak kasus—demoralisasi.
Pada titik inilah—ketika aksi demonstrasi berulang kali berujung pada kekalahan sementara represi kian meluas, sejumlah pertanyaan mendasar perlu didiskusikan. Mengapa kita terus kalah? Apakah persoalannya semata terletak pada kurangnya massa atau lemahnya koordinasi teknis selama aksi, atau justru pada cara kita memahami siapa—atau apa—lawan yang sesungguhnya kita hadapi? Lebih jauh lagi, apa yang keliru dari cara kita merumuskan dan mengorganisir perlawanan itu sendiri? Tulisan ini berangkat dari kegelisahan tersebut, sebagai upaya untuk membaca ulang negara dan wataknya hari ini, sekaligus membuka kemungkinan untuk merumuskan ulang strategi perlawanan yang selama ini kerap dianggap cukup.
Siapa (atau Apa) Lawan yang Kita Hadapi
Pertanyaan tentang siapa atau apa lawan yang kita hadapi tidak dapat dijawab dengan menunjuk satu aktor atau entitas tunggal—entah itu presiden, menteri, aparat di lapangan, atau suatu produk hukum tertentu. Ketidakberpihakan regulasi, inkompetensi pejabat, serta represi oleh aparat yang terus berulang bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan terjadi secara sistematis dan konsisten.
Indonesia sebagai negara tidak pernah berdiri sebagai entitas yang netral. Ia diselenggarakan oleh aktor-aktor yang membawa kepentingan ekonomi-politik tertentu. Komposisi elite dalam Kabinet Merah Putih, misalnya, memperlihatkan dominasi individu dengan latar belakang pengusaha besar, pemilik modal, serta mereka yang terhubung dengan dinasti bisnis dan penguasaan sumber daya alam. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan konsentrasi kekayaan mereka pada aset finansial, properti, dan kepemilikan perusahaan. Fakta ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara hari ini berada di bawah pengaruh kuat kelas yang memiliki kendali atas sumber daya ekonomi.
Di sisi lain, Indonesia juga tidak bekerja dalam ruang yang hampa. Ia terintegrasi dalam tatanan ekonomi-politik global yang bercorak neoliberal, di mana efisiensi pasar melalui deregulasi, pengurangan hambatan bagi investasi swasta, dan kompetisi global menjadi orientasi utama dari kebijakan hari ini. Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, terus diimplementasikan untuk meningkatkan daya tarik investasi, meski menempatkan pekerja pada posisi yang semakin rentan. Kebijakan hilirisasi nikel pun, meski dibungkus retorika kedaulatan, dalam praktiknya tetap bergantung pada modal besar dan investasi asing demi memenangkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Bahkan sektor-sektor publik seperti pendidikan semakin terdorong ke arah privatisasi.
Ketika negara diselenggarakan oleh elite dengan kepentingan ekonomi besar dan bergerak dalam kerangka neoliberal semacam ini, fungsinya mengalami pergeseran. Negara tidak lagi berperan sebagai penjamin hak-hak masyarakat, melainkan sebagai fasilitator bagi kelancaran akumulasi kapital. Kebijakan tidak lagi berangkat dari upaya untuk memenuhi kebutuhan publik, tetapi dari tuntutan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya tidak menjanjikan distribusi yang adil. Pergeseran ini adalah sesuatu yang umum hari ini, sebuah watak khas negara modern dalam kapitalisme kontemporer.
Dengan demikian, aparat negara—baik kepolisian maupun militer—harus dipahami sebagai instrumen yang bekerja di dalam dan untuk logika akumulasi kapital. Peran mereka bukan semata menegakkan hukum secara adil, melainkan memastikan keberlanjutan tatanan yang ada, termasuk mengamankan proses akumulasi dan meredam potensi gangguan terhadapnya. Suara kritis masyarakat dan aksi-aksi demonstrasi, karenanya, kerap diperlakukan sebagai ancaman terhadap ketertiban versi negara. Dalam konteks ini, kekerasan, penangkapan, dan kriminalisasi tidak lagi tampil sebagai respons insidental, tetapi sebagai mekanisme yang dilembagakan dan dijalankan secara sistematis.
Agar mekanisme ini dapat berjalan tanpa hambatan, hukum berfungsi sebagai perangkat yang melegitimasinya. Alih-alih menjamin distribusi kekuasaan yang adil dan melindungi masyarakat, hukum justru semakin terang digunakan untuk mengamankan konsentrasi kekuasaan di tangan elite. Kita tahu, praktik represif aparat telah lama terjadi, bahkan sebelum diberlakukannya KUHP Nasional dan KUHAP yang baru: sepanjang 2014–2023, 827 pejuang lingkungan dikriminalisasi; pasca-aksi demonstrasi Agustus–September 2025, sedikitnya 3.337 massa aksi ditangkap dan 1.042 orang dilarikan ke rumah sakit akibat dugaan kekerasan aparat, belum termasuk korban jiwa. Namun, dalam versi terbarunya, praktik-praktik represif tersebut kini dilembagakan—melalui pengaturan ketat terhadap pawai dan unjuk rasa (Pasal 256 KUHP baru), ancaman kriminalisasi penghinaan terhadap penguasa (Pasal 218 dan 240 KUHP baru), serta dibukanya ruang bagi hakim untuk memutus perkara berdasarkan pengamatannya yang bersifat subjektif (Pasal 235 KUHAP baru).
Menjadi sangat jelas bahwa di bawah negara yang bekerja dengan logika akumulasi kapital, mustahil membayangkan aparat mengayomi masyarakat—karena mereka memang tidak didesain untuk bertindak demikian, dan hukum tidak dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat secara luas, terlebih mereka yang berada dalam posisi rentan. Logika tersebut membentuk watak unit-unit di dalamnya, termasuk aparat, pengadilan, dan lembaga legislatif, sehingga setiap regulasi, praktik penegakan hukum, dan kebijakan publik secara konsisten memperkuat konsentrasi kekuasaan dan akumulasi kapital oleh elite. Dengan demikian, musuh yang kita hadapi bukanlah sekadar individu atau kebijakan tunggal, melainkan sebuah sistem—sebuah konfigurasi kekuasaan yang bekerja secara terpadu untuk mempertahankan status quo dengan cara membungkam setiap potensi perlawanan terhadapnya.
Memperluas Medan Perlawanan
Setelah memahami bahwa musuh yang kita hadapi bukanlah entitas tunggal—melainkan sebuah konfigurasi kekuasaan yang bekerja secara struktural, maka aksi-aksi demonstrasi hanya dapat dipahami sebagai suatu fragmen kecil dari perlawanan terhadapnya. Namun, harus digarisbawahi bahwa bukannya salah untuk melakukan aksi demonstrasi, ia hanya tidak memadai jika diposisikan sebagai satu-satunya bentuk perlawanan. Sayangnya, dalam praktik politik kita hari ini, perlawanan kerap berhenti tepat di sana. “Garis terdepan adalah barikade massa demonstran,” katanya—seolah-olah kemenangan telah diraih ketika sebuah regulasi berhasil digagalkan. Padahal, bagi sebagian besar dari kita, kondisi material dan relasi kuasa yang menindas tetap tidak berubah.
Dalam situasi tersebut, sistem yang sama terus bekerja. Ia tidak hanya memproduksi kekerasan dalam bentuk kebijakan dan regulasi, tetapi juga dalam bentuk-bentuk yang lebih halus, terstruktur, dan dinormalisasi dalam keseharian. Kekerasan ini tidak selalu hadir dalam rupa pentungan atau gas air mata, tetapi menjelma sebagai ketidakpastian hidup, relasi yang timpang, dan pengalaman-pengalaman yang terus menggerus martabat. Ironisnya, justru dimensi kekerasan inilah yang kerap luput dibicarakan dari diskusi-diskusi kita—seakan yang “politis” hanyalah apa yang terjadi di jalanan dan berupa konfrontasi langsung yang spektakuler.
Pengalaman Alfarizi yang menjalani hari-hari menyakitkan di dalam penjara, atau Laras—di tempat yang sama—yang diberi obat kadaluwarsa dan diperlakukan tidak manusiawi oleh aparat, menunjukkan bahwa kekerasan negara merembes masuk sampai pada ruang-ruang keseharian. Namun demikian, imajinasi perlawanan kita masih kerap terjebak pada mekanisme konfrontasi langsung—terutama dalam bentuk demonstrasi—sebagai respons terhadap regulasi yang dianggap merugikan. Kita sering kali gagal membaca bahwa regulasi-regulasi tersebut bukanlah akar persoalannya, melainkan produk dari relasi kuasa yang timpang dalam struktur masyarakat.
Malangnya, bahkan keterbatasan imajinasi kita ini—untuk membayangkan bentuk perlawanan alternatif—sesungguhnya juga dikondisikan oleh sistem semacam itu. Negara, melalui berbagai perpanjangan tangannya seperti pendidikan tinggi, mereproduksi pengetahuan yang selaras dengan logika neoliberal. Mahasiswa didorong untuk terus produktif, kompetitif, dan patuh, sementara waktu dan ruang untuk berpikir, berorganisasi, dan membangun solidaritas perlahan dirampas. Karenanya, tidak mengherankan jika perlawanan kerap hadir sebagai reaksi sesaat, bukan sebagai proyek politik jangka panjang.
Jika yang kita hadapi adalah sebuah sistem, perlawanan tidak mungkin hanya berupa respons sesaat terhadap produk-produknya. Ketika perlawanan berhenti pada demonstrasi sebagai reaksi atas regulasi, kita masih bergerak di dalam logika yang sama dengan kekuasaan yang kita kritik. Fokus kita tertuju pada kebijakan, bukan pada struktur relasi kuasa yang melahirkannya. Ia tidak sungguh-sungguh dapat menantang kekuasaan. Bahkan, tanpa disadari, kita berisiko justru membantu menormalkan siklus yang sama: regulasi lahir, ditolak, direpresi, lalu perlahan dilupakan—sementara elite terus mengonsolidasikan kekuasaan dan sumber daya.
Kita membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar demonstrasi agar negara benar-benar dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat. Pertanyaan tentang “bagaimana caranya” tentu tidak bisa dijawab secara instan. Namun, di tengah situasi hukum yang semakin represif dengan diberlakukannya KUHP dan KUHAP yang baru hari ini, mengandalkan aksi jalanan semata justru berisiko menghancurkan basis perlawanan itu sendiri. Barangkali, fase hari ini menuntut kesadaran lain, seperti mengenali kekerasan yang bekerja dalam keseharian, memupuk keberanian untuk menolaknya, dan mulai mengorganisir perlawanan dari ruang-ruang yang paling dekat dengan kehidupan kita: kampus, ruang kerja, komunitas, dan kehidupan sehari-hari.
Jalanan tetap penting, tetapi ia tidak lagi cukup. Jika demokrasi ingin dipertahankan, medan perlawanannya harus diperluas: dari jalanan menuju keseharian, dari reaksi menuju pengorganisiran, dan dari tuntutan sesaat menuju pembongkaran relasi kuasa yang menopang ketidakadilan itu sendiri.
***
*Esai ini ditetapkan sebagai pemenang pertama Sayembara Esai Mahasiswa Bersuara 2025
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB