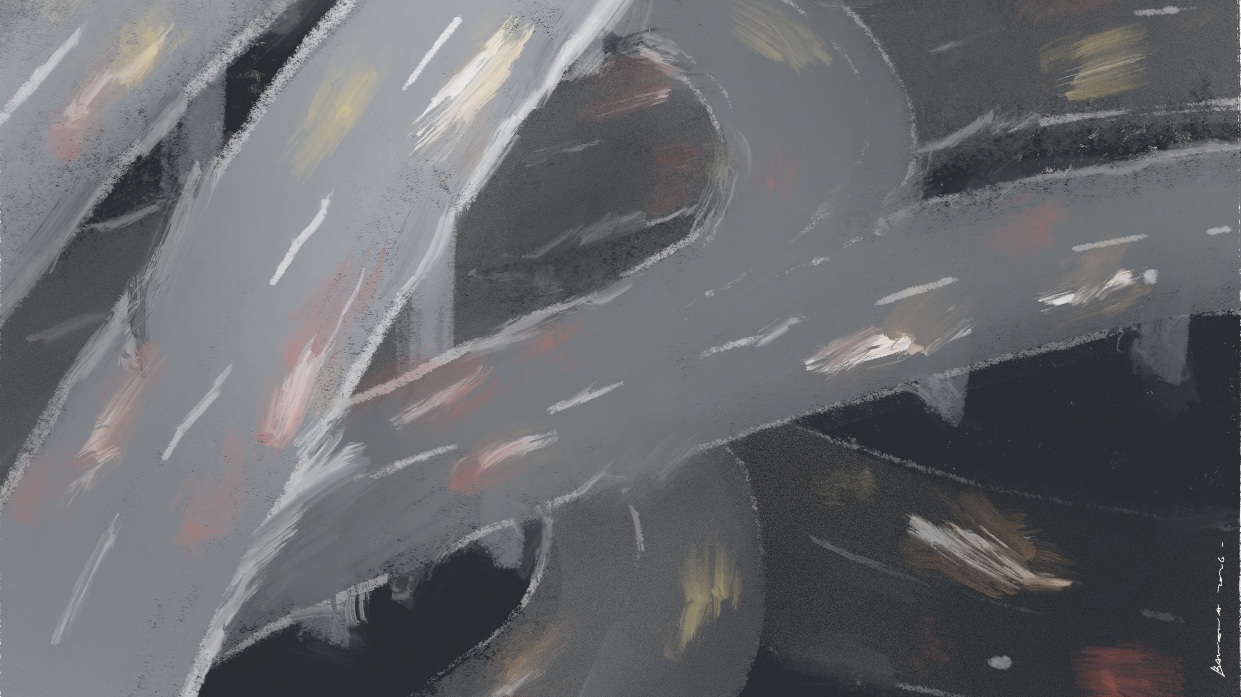MAHASISWA BERSUARA: Manusia Budak Kota
Selama kota terus dibangun untuk melayani kekuasaan dan modal, manusia akan terus diproduksi untuk sibuk dan patuh.

Nur Yusril Muhammad Isnain
Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
9 Februari 2026
BandungBergerak – Hidup di kota hari ini bukan sekadar melelahkan. Ia secara sistematis dirancang untuk menyita waktu, menguras tenaga, dan menghabiskan perhatian manusia, lalu mengajarkan bahwa semua itu adalah sesuatu yang normal. Macet berjam-jam, banjir tiap tahun, lingkungan yang tidak aman, dianggap risiko hidup dalam perkotaan. Hari-hari dipenuhi pekerjaan, perjalanan, dan kewajiban hingga hampir tidak ada ruang tersisa untuk berpikir lebih jauh dari sekadar bertahan hidup.
Kesibukan ini bukan kebetulan. Ia adalah mekanisme. Masyarakat yang terlalu sibuk tidak punya cukup waktu untuk belajar, membaca, atau memahami struktur yang mengatur hidupnya. Orang yang pulang ke rumah dalam keadaan lelah tidak membutuhkan sensor atau represi untuk dibungkam; ia sudah dibungkam oleh ritme hidupnya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, diam bukan pilihan moral, melainkan akibat dari kelelahan yang diproduksi secara sistematis.
Di titik inilah manusia kota perlahan dipersiapkan untuk patuh. Bukan melalui kekerasan terbuka, melainkan melalui pengaturan ruang dan waktu yang membuat hidup berjalan cepat tanpa jeda. Ketika seluruh energi dihabiskan untuk bekerja, berpindah tempat, dan bertahan dari hari ke hari, kesempatan untuk menyuarakan ketidakadilan nyaris tidak ada. Kesibukan menjadi bentuk kontrol yang paling efektif.
Lewis Mumford, dalam The Culture of Cities dan The City in History, sejak lama memperingatkan bahwa kota seharusnya menjadi wadah kehidupan manusia sebagai ruang tempat relasi sosial, kebudayaan, dan makna hidup bertumbuh. Meski demikian, ia juga menunjukkan bagaimana kota dapat berubah menjadi megamachine: sebuah sistem raksasa yang menuntut efisiensi, keteraturan, dan produktivitas, dengan menjadikan manusia sebagai komponen yang dapat dikorbankan. Dalam kota seperti ini, manusia tidak lagi menjadi tujuan pembangunan, melainkan bahan bakar agar sistem terus berjalan.
Apa yang kita alami hari ini persis seperti yang diperingatkan Mumford. Kota dibangun bukan untuk membantu manusia hidup dengan layak, melainkan untuk memastikan roda ekonomi, investasi, dan administrasi berputar tanpa gangguan. Dalam keadaan tersebut, kota sudah kehilangan fungsinya untuk melayani manusia; ia menjadikan manusia sebagai mesin yang melayani kotanya. Dan ketika manusia kelelahan, jawabannya bukan pada evaluasi kembali sistem yang sudah ada, tetapi tuntutan agar manusia menyesuaikan diri dengan sistem. Kota tidak pernah bertanya apakah warganya sanggup; ia hanya menuntut agar mereka tetap berfungsi.
Ruang sebagai Alat Kontrol
Henri Lefebvre dalam The Production of Space (1991) menegaskan bahwa ruang bukanlah sesuatu yang netral. Ruang adalah produk sosial dan politik, dibentuk oleh relasi kuasa antara negara, modal, dan institusi. Karena itu, siapa yang menguasai ruang, pada dasarnya menguasai cara hidup manusia. Ketika ruang diproduksi dari atas (oleh negara dan pasar), sementara warga hanya diposisikan sebagai mesin, kehidupan sehari-hari warga dipaksa untuk tunduk sepenuhnya pada kepentingan kekuasaan.
Logika ini terlihat nyata dalam praktik pembangunan di Indonesia hari ini. Penggusuran kampung atas nama penataan dan investasi menunjukkan bagaimana negara memproduksi ruang dengan mengorbankan warga yang telah lama hidup di dalamnya. Hak atas tempat tinggal, keberlanjutan hidup, dan ruang sosial dikalahkan oleh kepentingan proyek. Alih-alih melindungi, aparat justru hadir sebagai penjaga agar rencana pembangunan berjalan mulus.
Kekerasan ruang tidak selalu hadir dalam bentuk penggusuran terbuka. Ia juga bekerja secara halus melalui desain dan pengaturan ruang sehari-hari. Konsep hostile architecture dalam buku City of Quartz (1990) yang ditulis oleh Mike Davis menjelaskan bagaimana ruang sengaja dirancang untuk mengontrol dan menyingkirkan manusia. Bangku yang tidak memungkinkan orang duduk lama, pembatas di kolong jembatan, penghilangan ruang berkumpul, hingga desain yang secara halus mengusir kelompok miskin dan marginal. Semua itu bukan kesalahan teknis, melainkan strategi. Ruang publik diperlakukan sebagai alat kontrol sosial.
Ruang semacam ini mengirim pesan yang jelas, bahwa kota hari ini tidak ditujukan untuk semua orang. Kota hanya ramah bagi mereka yang sesuai dengan logika produktivitas dan konsumsi. Mereka yang dianggap tidak produktif disingkirkan secara perlahan, tanpa perlu kekerasan terang-terangan. Hak atas kota direduksi menjadi hak untuk membeli dan mengakses, bukan hak untuk hidup layak dan berelasi.
David Harvey dalam Social Justice and the City (1973) menyebut kondisi ini sebagai ketidakadilan ruang. Dalam logika kapitalisme perkotaan, kota berubah menjadi mesin akumulasi modal. Nilai ruang ditentukan oleh nilai tukarnya, bukan oleh nilai gunanya bagi kehidupan manusia. Akibatnya, ruang yang aman, sehat, dan bermakna menjadi kemewahan bagi segelintir orang, sementara kelompok rentan dipaksa menerima ruang hidup yang sempit, jauh, dan tidak layak.
Cara negara memperlakukan ruang dan warganya diperkuat oleh apa yang dijelaskan James C. Scott dalam Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed (1998). Negara cenderung menyederhanakan kehidupan yang kompleks agar mudah dikendalikan melalui skema, zonasi, dan standar. Kampung, permukiman adat, dan pola hidup lokal yang tidak rapi di atas peta dianggap sebagai masalah. Yang tidak sesuai skema diperlakukan sebagai gangguan yang harus disingkirkan, meskipun ruang-ruang tersebut justru menopang kehidupan sosial warganya.
Michel Foucault dalam Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1975) menunjukkan bahwa kekuasaan modern jarang bekerja melalui kekerasan langsung. Ia bekerja melalui disiplin dan pengaturan keseharian. Ruang digunakan untuk mengatur tubuh, waktu, dan kebiasaan manusia. Ritme hidup dipercepat, jarak diperpanjang, dan pola hidup dibentuk hingga manusia mendisiplinkan dirinya sendiri. Kepatuhan tidak dipaksakan, tetapi dibiasakan.
Logika ini terlihat jelas dalam perumahan modern yang diseragamkan. Rumah diproduksi massal dengan bentuk, ukuran, dan orientasi yang sama. Manusia dipadatkan secara fisik, tetapi dipisahkan secara sosial. Tetangga hidup berdempetan tanpa saling menyapa. Lingkungan tampak rapi, tetapi miskin kehidupan. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan yang lebih peduli pada efisiensi dan keuntungan dibanding pada kualitas hidup. Perumahan modern dibangun dengan mengedepankan individualisme, batas tegas, dan privasi yang berlebihan. Rumah diperlakukan sebagai benteng pribadi, bukan bagian dari jaringan sosial. Interaksi antarwarga diminimalkan, digantikan oleh pagar, portal, dan sistem keamanan buatan.
Lebih buruknya lagi, di saat privasi dipertebal, ruang terbuka untuk berkumpul justru diperkecil, bahkan dihilangkan. Ruang hijau dan ruang publik diperlakukan sebagai sisa lahan, bukan kebutuhan hidup. Akibatnya, manusia hidup berdampingan secara fisik, tetapi terputus secara sosial.
Hal ini jelas berbeda dengan arsitektur dan penataan tradisional. Arsitektur tradisional dan kampung adat di berbagai wilayah Indonesia justru tumbuh dari kebutuhan hidup masyarakatnya. Pola permukiman dibentuk oleh iklim, kebiasaan, relasi sosial, dan nilai-nilai lokal. Ruang tidak dipisah secara kaku, tetapi saling terhubung. Rumah, halaman, jalan kampung, dan ruang komunal menjadi satu kesatuan hidup. Kampung adat mengajarkan manusia untuk berelasi, menyapa di jalan, bercengkrama di halaman, saling melihat dan saling menjaga. Privasi tidak dihapus, tetapi ditempatkan dalam keseimbangan dengan kehidupan bersama. Keamanan lahir dari kehadiran sosial, bukan dari isolasi.
Sayangnya, ruang-ruang yang paling kontekstual dengan kehidupan manusia ini justru dicap kumuh, tidak modern, dan dianggap menghambat pembangunan. Kampung adat dan permukiman tradisional digusur atas nama penataan, investasi, dan proyek strategis. Yang dihancurkan bukan hanya bangunan fisik, tetapi sistem kehidupan yang selama ini terbukti menopang manusia.
Normalisasi kondisi ini adalah bentuk kekerasan paling efektif. Ketika kelelahan dianggap biasa, keterasingan dianggap wajar, dan kesibukan dianggap keniscayaan, manusia berhenti mempertanyakan sistem yang merugikannya. Masyarakat tidak kehilangan suara karena tidak peduli, tetapi karena tidak memiliki cukup waktu dan tenaga untuk bersuara.
Merampas Kemerdekaan
Hak atas ruang hidup adalah bagian dari hak asasi manusia. Ia mencakup hak untuk tinggal, merasa aman, berelasi, dan menentukan ritme hidup secara manusiawi. Ketika ruang justru memaksa manusia hidup terburu-buru dan terisolasi, yang dirampas bukan hanya kenyamanan, melainkan kemerdekaan manusia itu sendiri.
Negara yang mengklaim diri demokratis seharusnya menjamin hak-hak tersebut. Namun ketika negara lebih setia pada kepentingan pembangunan dan keuntungan segelintir pihak dibanding pada warganya, demokrasi kehilangan makna di tingkat paling dasar, yaitu hidup layak dalam sehari-harinya. Kota berubah menjadi alat kekuasaan, bukan ruang bersama.
Selama kota terus dibangun untuk melayani kekuasaan dan modal, manusia akan terus diproduksi untuk sibuk dan patuh. Bukan melalui larangan atau kekerasan terang terangan, melainkan melalui ritme hidup yang menyita seluruh energi manusia.
Ketika masyarakat terlalu sibuk untuk belajar, berpikir, dan menyuarakan ketidakadilan, yang tercipta bukan warga negara yang merdeka, melainkan mesin yang siap dipakai. Di titik ini, persoalannya bukan lagi apakah kota adil atau tidak. Persoalannya adalah sejauh apa manusia telah dipersiapkan untuk hidup tanpa waktu, tanpa ruang, dan tanpa suara. Dan ketika semua manusia sudah kehilangan akal sehatnya, selamat! Kalian bukan sekadar tinggal di kota, tetapi telah menjadi budak kota.
***
*Esai ini termasuk dalam 28 esai terpilih Sayembara Menulis Esai Kritis Mahasiswa Bersuara 2025
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB