OBITUARI AFFAN KURNIAWAN: Berdiri Ditindas, Rubuh Dilindas
Inilah wajah militerisasi ruang sipil, konsekuensi dari cara pandang bahwa demonstrasi, hak dasar warga negara, diposisikan sebagai ancaman.
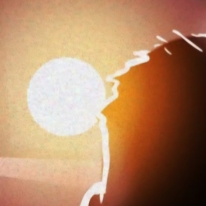
Sami Saujana
Peneliti lepas, tinggal di Majalengka
29 Agustus 2025
“Dan kata batu jatuh
di dadaku yang masih hidup.”
—Anna Akhmatova, Requiem
BandungBergerak - Affan Kurniawan baru 21 tahun. Anak muda yang seharusnya masih mencari arah hidup, sesekali menonton konser, nongkrong di kafe, tertawa terlalu keras di malam yang masih panjang. Tapi yang kita lihat darinya bukan citra generasi Z yang gemerlap di layar iklan. Yang kita temukan hanyalah tubuh muda yang habis ditindas kewajiban: kontrakan 3x11 meter, adik SMP yang harus dibayarkan sekolahnya, ibu sepuh yang perlu ditopang. Masa mudanya tidak penuh pilihan, melainkan disusutkan jadi soal ongkos bensin dan ongkos hidup.
Hari itu, Affan tidak ikut demo. Ia tidak berteriak, tidak mengangkat spanduk, tidak melawan. Ia hanya lewat, membawa pesanan yang harus sampai, dengan aplikasi yang menyalakan suara order. Pejompongan seharusnya hanya lintasan nafkah. Tapi justru di sana ia dilindas oleh kendaraan taktis Brimob. Tubuhnya remuk, tulang muda patah, darah bercampur debu jalan. Dan seketika, kalimat Akhmatova itu menjelma konkret: sebuah kata batu jatuh ke dada yang masih hidup.
Inilah wajah militerisasi ruang sipil, konsekuensi dari cara pandang bahwa demonstrasi, hak dasar warga negara, diposisikan sebagai ancaman. Sejak awal, aparat memperlakukan aksi massa bukan sebagai ekspresi politik yang sah, melainkan sebagai musuh yang harus dilumpuhkan. Itulah sebabnya dari siang gas air mata sudah ditembakkan ke kerumunan, dari siang para pelajar yang bahkan baru turun dari stasiun sudah diangkut ke markas polisi. Bukan tindakan ad-hoc, tapi pola yang lahir dari paradigma: protes adalah perang, demonstran adalah musuh negara.
Dalam logika itu, ruang kota berubah fungsi. Jalan bukan lagi jalur lalu lintas warga, melainkan zona operasi. Siapapun yang ada di situ, baik mahasiswa, pekerja, pelajar, atau bahkan seorang pengemudi ojol yang hanya ingin mengantar pesanan, dipaksa masuk ke logika pertempuran. Warga sipil jadi kolateral, karena aparat tidak lagi melihat manusia, hanya rintangan. Affan, yang seharusnya hanya melintasi kota untuk mencari nafkah, akhirnya digilas bukan semata oleh ban baja, tapi oleh paradigma yang menolak hak protes warganya sendiri.
Ketika demonstrasi dianggap permusuhan, maka demokrasi tinggal cangkang kosong. Ia berhenti menjadi ruang bagi warga untuk bersuara, dan berubah menjadi arena represi yang dilegalkan. Negara memang masih menggelar pemilu, masih menampilkan prosedur, tapi substansinya runtuh. Hak dasar untuk berkumpul, untuk marah, untuk mengingatkan penguasa, justru dipukul habis. Demokrasi yang menolak demonstrasi pada akhirnya bukan lagi demokrasi. Ia hanyalah rezim ketakutan yang menyamar dengan jargon partisipasi, sambil memperlakukan warganya sebagai musuh internal.
Affan Kurniawan adalah contoh paling telanjang dari apa yang disebut Giorgio Agamben sebagai homo sacer: manusia yang boleh dibunuh tapi tidak boleh dikorbankan. Ia boleh dibunuh, ban baja melindas tubuhnya, dan aparat bisa menyebutnya situasi kacau lalu melanjutkan hidup. Tapi ia tidak boleh dikorbankan, kematiannya tidak diakui sebagai pengorbanan, tidak dimaknai, tidak diberi tempat dalam bahasa resmi negara. Ia hanya hilang, ditinggalkan sebagai angka, padahal usianya baru 21 tahun.
Dalam ironi pahit itu, kita melihat betapa rapuhnya hidup rakyat jelata: tidak dihitung saat mereka berjuang, tidak dimuliakan saat mereka mati, hanya “bare life” yang sewaktu-waktu bisa dihapus dari jalan.
Shakespeare menulis dalam Henry V: “And all the wounded and the mangled dead / Heaped on the next day’s dawn in bloody field…”—mayat-mayat tercacah yang ditumpuk di fajar hari berikutnya di medan berdarah. Bagi Shakespeare, perang adalah mesin dehumanisasi total: manusia tak lagi utuh, tubuh bernyawa direduksi menjadi puing daging.
Affan mengalami nasib serupa, meski ia bukan prajurit di medan perang. Ia hanya pengemudi ojol berusia 21 tahun, melintas untuk mengantar pesanan. Tubuh bernyawanya dilindas mesin baja bukan sebagai manusia, tapi diperlakukan layaknya botol plastik bekas, diremukkan di atas aspal, hingga tak lagi dilihat sebagai manusia. Inilah dehumanisasi total itu.
Dari situlah alegori itu lahir: Affan adalah “the mangled man in the asphalt”, bukan di padang berdarah abad pertengahan, tapi di jalan kota yang telah dimiliterisasi, tempat warga sipil diperlakukan sebagai bangkai di medan perang yang seharusnya tak ada.
Di atas kertas, Affan bisa saja tidak masuk kategori miskin karena BPS bisa mengubah ukuran miskin kapan saja. Tapi Loïc Wacquant sudah lama mengingatkan bahwa negara modern lebih suka menertibkan ketimbang menyelesaikan akar kemiskinan. Ia menulis: “Sistem pemenjaraanl telah menjadi cara mengelola kemiskinan dan marginalitas, bukan dengan mengatasi penyebabnya, melainkan dengan menahan konsekuensinya.”
Dalam terang kalimat itu, nasib Affan terlihat telanjang: ia bekerja keras dalam kemiskinan yang tak pernah diakui, dan ketika tubuh mudanya hancur di jalan, ia justru jadi konsekuensi dari mesin penertiban itu sendiri.
Ada ironi yang dingin sekaligus menghantam: upah yang nyaris tak pernah cukup diperlakukan seakan standar hidup yang layak, kontrakan sempit dianggap rumah tangga normal, masa muda yang habis di jalan dianggap produktivitas. Standar-standar itu melucuti kenyataan, menutup fakta bahwa Affan hidup dalam kekurangan dan mati dalam kelalaian yang ditopang sistem.
Obituari ini bukan sekadar menuliskan kehilangan. Ia memperlihatkan bagaimana tubuh seorang anak muda bisa hilang begitu saja tanpa jejak di arsip resmi. Affan tak akan jadi nama jalan, tak akan diperingati dengan tugu. Yang tersisa hanyalah kontrakan sempit yang kini kosong, notifikasi order terakhir yang tak pernah selesai, dan helm hijau yang pecah di aspal. Dari sisa-sisa banal itulah kita belajar: bahkan pekerjaan paling sederhana pun bisa berakhir di bawah roda besi yang tak mengenal ampun.
Di tengah aspal Pejompongan, tubuh Affan Kurniawan menjadi tanda: seorang homo sacer, seorang mangled man in the asphalt, yang diserahkan begitu saja pada kekerasan.
Tan Malaka pernah menulis: terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk. Namun yang dialami Affan jauh dari itu semua. Alih-alih terbentuk, ia malah terlindas. Akhirnya pilihan jadi sangat sedikit. Berdiri untuk melawan ditindas, ketika rubuh malah dilindas.
***
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB


