KELAS LIAR #10 DI PURWAKARTA: Berisik atau Tersingkir, ketika Orang Muda Kehilangan Ruang Bicara
Kelas Liar yang mulai bergulir di Bale Warga Dago Elos, Bandung, 2 Agustus lalu berakhir di Kelas Liar #10 di Purwakarta. Orang-orang muda tetap berisik dan kritis.
Penulis Ryan D.Afriliyana 21 Oktober 2025
BandungBergerak – Ruang digital semakin bising, tapi ruang berpendapat justru menyempit. Tekanan regulasi yang tidak jelas, perundungan daring, dan polarisasi sosial membuat banyak orang memilih diam, termasuk orang muda. Dampaknya terasa nyata. Wacana publik terpusat di ibu kota, dengan narasi tunggal yang mengabaikan realitas daerah. Isu penting seperti konflik agraria, krisis lingkungan, dan suara kelompok rentan sering tak terdengar.
Kelas Liar #10 yang digelar di Purwakarta pada Sabtu, 18 Oktober 2025, menjadi ruang untuk melawan senyap itu. Tidak sekadar kelas, tapi forum bersama untuk mempertanyakan: mengapa kita harus terus bersuara? Purwakarta, sebagai kota industri, menyimpan banyak cerita penting—tentang buruh, perubahan lingkungan, dan warga yang ingin didengar. Sayangnya, suara-suara ini kerap tenggelam di tengah narasi besar nasional.

Kebebasan Berekspresi Orang Muda Terancam
Ruang digital yang dulu dianggap menjanjikan kebebasan kini justru menghadirkan ketakutan. Orang muda yang berani bersuara di media sosial makin sering menghadapi risiko, dari perundungan hingga pelaporan hukum. Di sisi lain, kebebasan pers sebagai penopang utama demokrasi terus melemah.
Catur Ratna Wulandari, dosen luar biasa STIKOM Bandung sekaligus Pemimpin Redaksi digitalmama.id, dalam sesi pertama Kelas Liar menyoroti bagaimana ekspresi publik, khususnya dari perempuan dan orang muda, semakin terbatasi.
"Apa pun selalu diawasi, bahkan ketika saya upload sesuatu di medsos selalu berpikir panjang, walau pada akhirnya tidak jadi," katanya.
Ia mencontohkan kasus Bima, Tiktoker asal Lampung yang dilaporkan ke polisi karena mengkritik kondisi jalan rusak di daerahnya. Menurutnya, kasus semacam ini menunjukkan bahwa ruang ekspresi warga makin tidak aman.
Ratna juga menyoroti menurunnya kebebasan pers di Indonesia. Berdasarkan World Press Freedom Index 2024, peringkat kebebasan pers Indonesia merosot dari 111 ke 127 dari 180 negara. Ini menunjukkan bahwa media arus utama pun menghadapi tekanan serupa, baik secara politik maupun ekonomi.
"Nah, nasibnya (kebebasan pers) enggak jauh lebih baik dibandingkan tadi (kebebasan berekspresi), ditambah ada penurunan kepercayaan pada berita," ungkap Ratna.
Ia menjelaskan bahwa model bisnis media saat ini bergeser dari iklan konvensional ke native ads dan konten sponsor. Banyak media berlomba membuat judul sensasional demi klik dan pemasukan dari Google Ads. Di sisi lain, dominasi pemilik modal dalam industri media mempersempit keberagaman narasi.
Ruang digital pun tak lepas dari persoalan. Algoritma media sosial yang seharusnya netral kini mudah dimanipulasi oleh buzzer dan pihak berkepentingan.
"Sudah dibajak loh sama orang-orang yang bisa tadi. Bisa bikin, bisa sewa buzzer, bisa meng-add gede-gedean, bisa menguasai ruang digital itu sehingga algoritma aja ngurut gitu sama dia," ujar Ratna.
Dari sisi regulasi, Ratna menyoroti keberadaan pasal-pasal karet dalam UU ITE yang digunakan untuk membungkam kritik. Menurutnya, selama regulasi seperti ini tetap dipertahankan, kebebasan berekspresi akan terus terancam.
Namun ia mengajak orang muda tidak menyerah pada tekanan. Menurutnya, bersuara tetap penting terutama di tengah situasi yang menekan.

Tantangan Jurnalisme Publik dan Warga
Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, jurnalisme publik dan jurnalisme warga muncul sebagai dua pilar penting dalam menyajikan berita yang relevan dan dekat masyarakat.
Roki Rifandi dari media alternatif Trimurti.id yang mengisi sesi kedua Kelas Liar menjelaskan bagaimana kedua entitas tersebut saling melengkapi untuk memperkuat demokrasi. Menurutnya, media yang mengusung jurnalisme publik berfokus pada isu-isu sosial, bukan meliput tokoh atau figur publik.
"Pendekatan ini bersifat bottom-up, mengambil narasi dari warga dan mengangkat perspektif mereka," ucap Roki.
Sementara itu, jurnalisme warga adalah praktik semua orang dapat menjadi jurnalis. Setiap individu yang ingin mengabarkan peristiwa di sekitarnya mereka bisa menjalankan kerja-kerja jurnalis.
"Info Purwakarta.id sebagai praktik jurnalisme warga di Purwakarta yang melaporkan hal-hal yang enggak ke-cover, enggak ke-cover sama media konvensional atau bukan media, media besar," lanjut Roki.
Meskipun memiliki potensi besar, jurnalisme warga juga menghadapi tantangan serius. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kepatuhan terhadap kode etik dan standar jurnalisme.
Banyak jurnalis warga yang tidak melakukan verifikasi, asal memposting foto atau narasi, mencampuradukkan fakta dengan opini atau bahkan pengalaman pribadi. Hal tersebut dapat menyebabkan disinformasi.
Ia mencontohkan, kasus narasi Trans7 tentang pesantren, meskipun faktanya benar, narasinya dinilai salah karena melakukan framing dan generalisasi. "Fakta yang disampaikan itu benar, tetapi dengan narasi yang disampaikan dengan bawaannya sedikit salah," jelas Roki.
Jurnalisme warga juga rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu atau menyebarkan berita titipan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Roki menyarankan supaya jurnalis warga memiliki pengetahuan tentang kode etik jurnalistik yang bisa diakses di laman Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atau Dewan Pers.
Ia mengusulkan agar para jurnalis warga fokus menjembatani publik dan proses demokrasi, mengedepankan suara masyarakat dan menjadi pengeras suara bagi isu-isu kecil yang terabaikan.
Dengan pemahaman yang kuat tentang jurnalisme publik dan warga, serta komitmen terhadap kode etik dan verifikasi, masyarakat dapat menjadi bagian integral dalam menyajikan informasi yang kredibel dan memperkuat fondasi demokrasi di era digital.
Baca Juga: KELAS LIAR #1: Membedah Pola Penggusuran Kampung Kota di Bandung dan Langkah-langkah Advokasinya
KABAR DARI REDAKSI: Mengapa Kami Menggulirkan Kelas Liar dan Mengapa Kamu Harus Terlibat

Tekanan terhadap Kebebasan Berpendapat di Kampus
Kebebasan berpendapat di lingkungan kampus masih menjadi tantangan bagi banyak mahasiswa. Hal ini disampaikan oleh Ghevira Aulia Rahima, mahasiswi UPI Purwakarta, yang mengaku bahwa menyampaikan pendapat di kampus bukan hal mudah. Meski tidak secara langsung dilarang, atmosfernya membuat mahasiswa enggan bersuara.
"Sebenarnya memang bukan ditutup, tapi kayak kita ingin mengeluarkan pendapat tuh tidak berani," ujar Ghevira, salah satu peserta Kelas Liar.
Ia menambahkan bahwa setiap pendapat yang disampaikan, baik mendukung maupun menentang suatu hal, kerap berujung pada penilaian atau penghakiman dari pihak yang tidak setuju.
"Kadang eh intinya pendapat yang kita keluarkan baik atau kontra, ketika ada yang tidak setuju, yang tidak setuju itu pasti selalu menggembar-gemborkan judge," katanya.
Ghevira merasa lebih nyaman menyampaikan pendapat di lingkup yang lebih kecil, seperti bersama teman sebaya atau komunitas. Di ruang-ruang seperti itu, ia merasa aman untuk berdiskusi dan berekspresi.
"Menurut aku so far masih apa ya, masih open karena komunitas aku masih menjunjung tinggi kebebasan berpendapat juga gitu," ucapnya.
Salah satu bentuk ekspresinya adalah membagikan ulang isu-isu sosial di media sosial. Namun, ia juga berharap orang lain bisa menghormati mereka yang memilih bersuara.
"Kalau misalkan enggak bisa say something nice, ya udah diam aja gitu," jelasnya.
Ghevira sempat mengalami tekanan ketika menyuarakan pendapat tentang penolakan RUU TNI. Ia menyayangkan sikap acuh teman-temannya terhadap isu tersebut, padahal isu itu bisa berdampak langsung pada masa depan mereka.
"Teman-teman aku tuh kayak acuh tak acuh, meskipun isu tersebut mungkin akan berdampak pada mereka di kemudian hari," ucapnya.
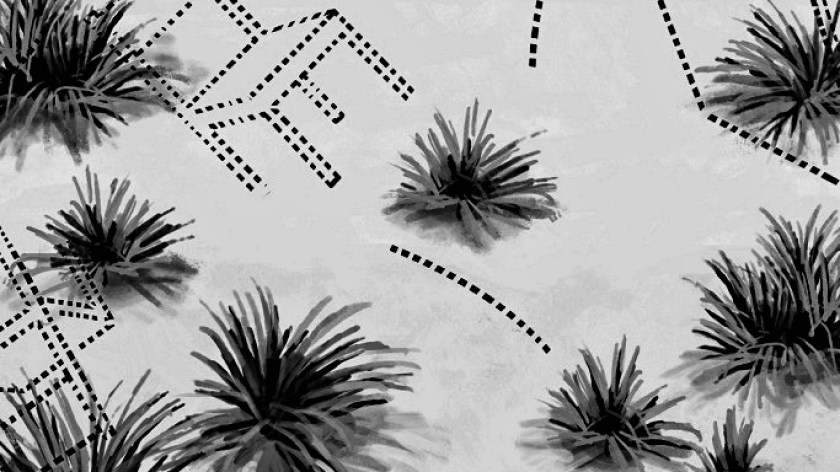
Pandangan serupa disampaikan Muhammad Chandra Hizbullah, mahasiswa FTIK Universitas Islam Dr Khez Muttaqien (Unismu), yang juga menyoroti minimnya ruang untuk berpikir dan menyampaikan pendapat di lingkungan kampus.
Menurutnya, kebebasan berpendapat sering dibatasi atas nama norma dan sopan santun, yang seolah-olah menyampaikan kritik berarti menyerang pribadi.
"Seolah pendidikan itu dibatasi dengan sopan santun, ketika menyampaikan gagasan atau kritik, seolah itu menyerang personalnya," kata Chandra.
Ia melihat bahwa kritik sering dibingkai sebagai tindakan yang tidak sopan, terutama jika dikaitkan dengan nilai-nilai agama.
"Ketika ada praktik bantah-bantahan itu sudah menjadi klaim bahwa kamu itu tidak sopan atau tidak beradab," lanjutnya.
Chandra bahkan pernah mengalami tekanan dari pihak kampus setelah menyampaikan kritik terhadap kinerja kemahasiswaan. Ia mengaku diancam dikeluarkan, namun memilih tetap bersuara.
"Karena kan kalau justru malah kata Munir, kemenangan seorang aktivis itu kan mati," tegasnya.
Sebagai bentuk perlawanan, Chandra mendorong mahasiswa baru untuk berani berpikir kritis. Ia berharap kritik tidak dianggap sebagai serangan, tetapi sebagai bagian dari proses belajar dan tumbuh.
"Bagaimana cara kita sadar bahwa, kita manusia adalah makhluk memang tidak sempurna, kenapa ketika dikritik enggak diterima gitu," ungkapnya.
Kelas Liar #10 di Purwakarta sekaligus menutup rangkaian Kelas Liar yang dimulai dengan Kelas Liar #1: Penggusuran, Tanah ini Milik Siapa? Membongkar Konflik Agraria dan Kekuatan Advokasi di Dago Elos yang digelar di Bale Warga Dago Elos, Bandung, 2 Agustus 2025. Berbagai isu yang terkait dengan ancaman terhadap demokrasi dibahas secara kritis dalam rangkaian Kelas Liar ini.
Kelas Liar hadir sebagai pengingat bahwa suara kritis, terutama dari orang muda, tetap penting. Agar suara dari pinggiran tidak terus dibungkam oleh pusat.
***
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB


