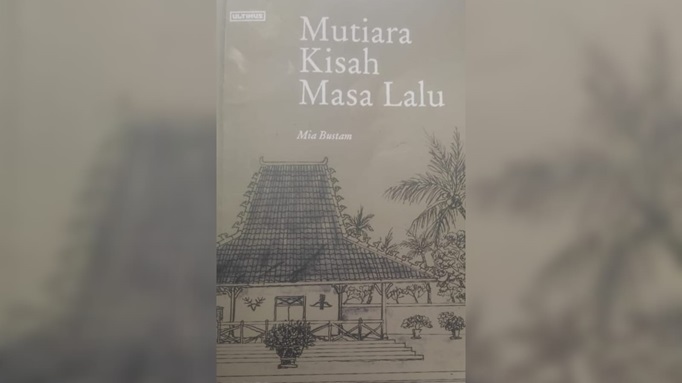RESENSI BUKU: Hikmah dari Mutiara Kisah Masa Lalu
Buku Mutiara Kisah Masa Lalu yang ditulis Mia Bustam mengajak kita mengetahui lebih rinci tentang pernik-pernik kehidupan yang terhampar pada masa Hindia Belanda.
Penulis Yogi Esa Sukma Nugraha12 Januari 2025
BandungBergerak.id – Jika hendak menilik keberadaan buku teks pascareformasi, maka kita akan mafhum bahwa klaim ihwal penulisan sejarah yang didominasi kisah orang besar belum sepenuhnya pudar. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, bahkan situasinya relatif tidak mengalami perubahan. Barangkali kenyataan ini memang sesuai dengan penuturan sejumlah ahli yang beranggapan bahwa setiap elite (politik, yang ditopang otoritas keilmuan) berusaha menetapkan satu versi yang resmi.
Begitu sulit untuk warga sipil biasa memiliki pengetahuan atau kesadaran mengenai kesejarahan secara utuh, terperinci, menyeluruh –dan lebih jauhnya lagi, beragam versi– persis seperti yang dilalui dan telah dialami orang-orang dari berbagai latar belakang. Dalam studi berkepala Dominasi Orang-orang Besar dalam Sejarah Indonesia: Kritik Politik Historiografi dan Politik Ingatan (2019), Ganda Febri dkk. mencatat bahwa kecenderungan ini justru menyuburkan watak kultus ketimbang membuat orang mampu memahami persoalan secara komprehensif. Sulit pula menemukan ahli yang mampu (dan mau) mencatat setiap peristiwa atau cerita penuh semacam itu.
Melihat keadaan sebagaimana uraian di muka, maka jelas saja buku Mutiara Kisah Masa Lalu yang ditulis Mia Bustam menjadi relevan. Ia mengisahkan sejarah kehidupan keluarga semi feodal. Bagaimanapun, dan apabila hendak ditinjau dari segi mana pun, itu memang suatu fakta sejarah yang telah terjadi. Menariknya, uraian dalam buku ini mampu menambal celah pada sejarah resmi yang sering kali terbatas, tidak jarang berpihak, dan tertuju pada hal-hal tertentu, sebab Mutiara Kisah Masa Lalu memuat narasi yang berangkat dari pengalaman sehari-hari.
Benar bahwa di Indonesia, sejarah keluarga semacam ini masih belum disadari sebagai studi yang punya signifikansi, seperti keterangan F. X. Domini Hera (halaman 294), yang menunjukkan bahwa sejarah keluarga ini sebetulnya merupakan salah satu pendalaman dari sejarah sosial. Mayoritas peserta didik di bangku sekolah atau perguruan tinggi lebih dahulu berkenalan dengan materi sejarah di luar diri mereka, ketimbang sejarah intra-personal setiap insan, sebagaimana terkandung dalam sejarah keluarga masing-masing. Padahal itu penting. Buku Mutiara Kisah Masa Lalu seolah mengajak kita menyaksikan sebuah kehidupan yang berjalan apa adanya.
Saya kira Mia Bustam merupakan pemerhati yang mumpuni ihwal manusia; mengamati bagaimana cara orang-orang sekelilingnya menjalani hidup seperti ayunan –maju-mundur, mendengarkan percakapan, dan punya hasrat lebih untuk mengulas dari dekat ihwal sosok-sosok yang memiliki hubungan emosional dengannya. Dengan lain perkataan, Mutiara Kisah Masa Lalu memuat cukup gamblang kisah keluarga dan masa kecilnya.
Kehidupan di Alam Feodal
Saya membayangkan upaya keras yang dilakukan penulis –dalam hal ini, Mia Bustam– untuk memantik ingatan masa kecilnya di usia yang sudah tidak lagi muda, dan di sebuah momen yang barangkali tidak banyak memberi waktu luang untuk mencari bahan penulisan, dan tidak terlalu mendukung upaya-upaya seperti itu. Sebagai seorang ibu, pegiat organisasi seni, yang kelak melewati nasib getir sebagai eks tapol, kehidupan masa kecilnya justru terasa menarik. Ia memuat detail-detail empirik.
Meski mengaku bukan penulis, dan tidak berpretensi menjadi penulis –sebagaimana diakuinya sendiri bahwa ia sekadar suka bercerita, terutama kepada anak-anak, tetapi buku ini justru menunjukkan kenyataan sebaliknya. Ia mempunyai bakat kepenulisan yang piawai. Dalam buku ini, penulis seolah mengajak kita mengetahui lebih rinci tentang pernik-pernik kehidupan yang terhampar pada masa Hindia Belanda.
Banyak sekali hal yang ada di dalamnya yang mustahil tersedia dalam buku teks pelajaran. Sebab, tentu saja, bakal dianggap tidak penting. Misalnya, tentang perkumpulan organisasi perempuan Puspo Rinonce; perkawinan endogami; perkembangan Fotografi; soal tradisi seperti kebiasaan menyalakan petasan di hari lebaran pada masa kolonial, makanan –dalam hal ini kue-kue yang biasa tersaji di alam feodal, adat-istiadat, bahasa sehari-hari, dan barang-barang yang biasa dipergunakan pada jamannya (lihat halaman 30, 42, 46, 96, dan 112).
Ada pula sejumlah bagian dari buku ini yang cukup menyita perhatian. Ia beberapa kali menceritakan tentang manusia dengan pengalaman unik, kadang dangkal, kadang heroik, tetapi jarang –atau jika boleh mengatakan sama sekali tidak– dianggap penting, seperti figur bapak yang berpihak pada wong cilik, tetapi kebaikannya itu malah dimanfaatkan orang yang kerap ditolongnya. Dan itu yang kemudian berbuah petaka; ihwal bagaimana perasaan tidak memiliki pekerjaan yang berbuntut pengucilan mertua (lihat halaman 47 hingga 75).
Memang ada tokoh-tokoh besar yang mengisi tulisannya, seperti Hadiningrat yang merupakan Paman Kartini. Namun di sini sosoknya tampil sebagai pihak yang melalui siasatnya menjerumuskan pihak lain. Mutiara Kisah Masa Lalu menunjukkan bagaimana kalangan menengah atas pada jamannya –yang punya jarak amat dekat dengan kehidupan sehari-hari penulisnya– juga akrab dengan situasi muram dalam kehidupan.
Sekilas kita dapat kembali mengingat apa yang telah diuraikan Friedrich Engels, dalam Sosialisme Utopis dan Sosialisme Ilmiah (1880), yang mencatat secara gamblang tentang hak atas malam pertama atau jus primae noctis, yang merupakan hak tuan tanah feodal di Eropa Abad Pertengahan untuk tidur dengan pengantin perempuan hambanya pada malam pengantin. Rupanya apa yang terjadi di sana –dalam derajat yang nyaris serupa– juga terdapat di sini. Mutiara Kisah Masa Lalu menunjukkan betapa sintingnya perilaku semacam itu.
Boleh saja jika ada yang hendak mengatakan kalau upaya penulisannya belum sempurna. Mungkin ada yang kurang tepat atau lengkap, apabila dinilai oleh mereka yang merasa punya pengetahuan lebih mumpuni tentang Hindia Belanda. Tetapi buat saya tidak masalah, dan mudah dimaafkan, karena pada dasarnya itu hanya perkara usia yang muskil dilawan. Yang jelas banyak hikmah yang sangat bisa didapat dari Mutiara Kisah Masa Lalu, yang bisa kita ambil dari figur seperti Yang Yi misalnya.
Ia seorang yang hidup di alam feodal, tetapi takzim pada perubahan yang terjadi di dalam tatanan sosial. Ia merupakan nenek dari penulis yang punya kecerdasan dan pikiran terbuka. Dengan kemampuannya yang serba terbatas karena berada di dalam kategori sosial atau kelas feodal, Yang Yi tidak pernah menari di atas penderitaan rakyat kecil. Suatu keadaan yang diakui sendiri oleh Mia Bustam, yang menyatakan begitu sulitnya untuk mengentaskan kemiskinan di tengah rakyat, bahkan golongannya sendiri –dalam hal ini, kaum feodal– memang tidak pernah memikirkannya (lihat halaman 122-124).
Satu hal menarik lainnya bagi pembelajaran anak-anak muda, menurut pembacaan saya, adalah ihwal lanskap. Kita bisa melihat bagaimana Mia Bustam menceritakan Gedung Kunstkring yang megah, dan kini berubah menjadi Palais Kunstkring, yang terletak di pertigaan Van Heutz Boulevard –sekarang Jalan Teuku Umar, kawasan Menteng– dengan patung (Van Heutsz) yang tegak berdiri sebelum diruntuhkan Fasis Jepang (lihat halaman 66); atau juga bagaimana kita bisa terperanjat oleh amatan jitu Mia Bustam mengenai persoalan agraria yang melibatkan pemuka agama dan terjadi di era Hindia Belanda (lihat halaman. 93).
Penting untuk digarisbawahi bahwa dewasa ini kita masih sering menemukan buah dari propaganda terhadap orang-orang kiri di masa lalu. Namun yang menarik adalah kenyataan bahwa persoalan ini bukan hanya muncul pasca peristiwa 1965. Jauh dari sebelumnya, atau setelah adanya pemberontakan 1926, pemerintah Kolonial Belanda tercatat melakukan hal serupa.
"Ada isu –pasti dibisik-bisikkan oleh intel Belanda– orang-orang PKI itu selalu mengendarai mobil merah (ini bohong, wong yang memberontak itu tidak punya mobil) dan suka menculik anak kecil untuk dicungkil matanya dan dibikin dawet," tulis Mia Bustam (halaman 18).
Ironisnya, justru sang ibu penulis juga turut terpengaruh dengan cerita tersebut. Itu membuat penulis terpaksa harus berhenti sejenak dari sekolah di taman kanak-kanak sampai pemberontakan tumpas. Bahkan keluarga-keluarga yang lain pun banyak yang ikut terpengaruh.
"Tiap sore, istri-istri semua perwira, termasuk Tante Ida, berlatih menembaki sasaran yang telah dibuat dengan bentuk manusia, untuk bisa melawan kalau orang-orang PKI datang menyerbu." (halaman 19).
Sekilas Tentang Mia Bustam
Mia Bustam sebetulnya bernama Sasmiati Srimoyoretno. Ia lahir pada 4 Juni 1920 dari seorang Ibu bernama Srijati dan ayah yang bernama Sasmojo, yang merupakan pejabat Binnenlands Bestuur (BB) atau pejabat sipil. Seiring perjalanan hidup, nama Mia Bustam lebih melekat pada dirinya.
Ia bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS) atau setara dengan sekolah dasar, yang hanya bisa diakses anak-anak Belanda, anak-anak Priyayi, dan anak-anak Tionghoa yang sudah gelijkgesteld (punya status setara dengan masyarakat Belanda, seperti Francisca Fanggidaej misalnya). Namun, tersirat bahwa Mia Bustam enggan memamerkan identitas dan hak kebangsawanannya itu. Sebagaimana diakuinya sendiri dalam Mutiara Kisah Masa Lalu (halaman 6) bahwa "harkat martabat seseorang tidak dinilai dari keturunannya, tetapi dinilai dari perilakunya sendiri."
Ia lahir dari klan Bustaman. Seorang jaksa di Semarang dan merupakan juru bicara sekaligus penerjemah bagi Belanda pada Perjanjian Giyanti 1755. Kenyataan ini diakui dengan sedikit mempertanyakan mengapa pendahulunya pada masa itu tidak memiliki kehendak untuk berlawan. Usai lulus sekolah, bapaknya hendak memasukkan Mia Bustam ke HBS (Hooger Burgerschool). Namun ia menolak. Saya menduga kalau Mia Bustam terpengaruh perangai Yang Yi.
Ia punya pikiran logis, dan terbuka terhadap apa-apa yang datang untuk memuliakan manusia, dan itu tampak jelas seperti kisah Yang Yi yang diceritakannya secara detail dalam Mutiara Kisah Masa Lalu, yang juga menunjukkan betapa dalamnya pemahaman Mia Bustam soal ilmu-ilmu hayat; Ia tampak mengetahui istilah yang lazim ditemui dalam biologi (Halaman 23). Ia juga menunjukkan bagaimana orang-orang yang ada di lingkaran pembuat policy tetapi masih mempunyai hati nurani. Seperti Nyonya De Jong (istri gubernur jenderal) yang merancang lembaga bernama Algemeen Steufonds voor Inheemsche Behoeftigen atau Dana Umum bagi Penduduk Pribumi Miskin (halaman 60).
Tentu saja masih banyak beberapa cerita yang tidak kalah menarik yang belum bisa ditemui di dalam ulasan ini. Dalam beberapa hal, membaca Mutiara Kisah Masa Lalu bahkan bisa membuat kita tiba-tiba mengernyitkan dahi. Satu yang pasti, buku ini menjadi warisan penting bagi kita semua, sebagaimana ditulis oleh Peter Carey dalam pengantarnya:
"Ini adalah dokumen sejarah yang langka dan berharga. Kini saatnya untuk membaca dan menikmatinya –seluruh 1.500 halaman yang dicetak dari buaian hingga liang lahat– sebuah memoar, autobiografi, dan kronik antargenerasi, yang setara dengan War and Peace karya Tolstoy."
Informasi Buku
Judul: Mutiara Kisah Masa Lalu
Penulis: Mia Bustam
Penerbit: Ultimus
Ketebalan: 302 halaman
Edisi: II, Desember, 2024
*Kawan-kawan dapat membaca tulisan-tulisan menarik lainnya dari Yogi Esa Sukma Nugraha, atau artikel-artikel lain tentang Resensi Buku