Dalam Kepungan Hoax dan Pesimisme, Komunikasi Publik Negara Harus Berubah (1)
Banjir hoax dan informasi negatif hari ini menyuburkan pesimisme di tengah mayarakat. Komunikasi publik negara harus berubah.
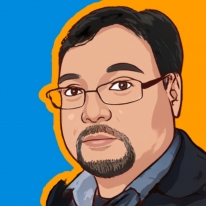
Mang Sawal
Praktisi komunikasi dan pembelajar pada Program Doktoral Unisba dengan fokus pada komunikasi sains. Aktif di berbagai kegiatan edukasi publik.
19 Maret 2021
BandungBergerak.id - Warga negara Indonesia selama empat tahun terakhir menjadi kian murung, tidak bahagia. Itu kata lembaga survei multinasional Gallup lewat World Happiness Report tahun 2018 lalu. Gara-garanya: tingginya kecemburuan sosial, tingginya ketegangan sosial, dan tidak adanya kepastian masa depan. Jika hasil survei dibaca lebih rinci, sumber gejala negatif tersebut di antaranya adalah banjir hoax. Mungkin jika ada survei baru, wabah covid19 bisa juga menjadi faktor tambahan.
Banyak riset menunjukkan, masyarakat yang gembira adalah masyarakat yang terdiri dari individu yang optimistis. Masyarakat optimistis cenderung hidup sehat dan produktif serta berumur lebih panjang. Sementara masyarakat yang pesimistis cenderung mudah terserang penyakit dan berumur pendek. Sebuah publikasi tahun 2016 di Jurnal BMC Public Health, tentang hasil riset selama 11 tahun di Rumah Sakit Paijat-Hame, Finnlandia, terhadap 2.267 manusia usia paruh baya dan usia lanjut, menunjukkan adanya hubungan tidak langsung antara sikap pesimisme dengan serangan jantung. Orang-orang pesimistis cenderung mudah mengalami serangan jantung. Studi Universitas Harvard yang terpublikasi pada American Journal of Epidemiology, Issue 1, Januari 2017, mengungkap, ada kecenderungan hubungan sebab akibat antara pesimisme dengan jumlah informasi negatif yang diterima.
Sederhananya: paparan informasi negatif berpengaruh pada pesimisme, dan pesimisme berpengaruh pada serangan jantung. Izinkan saya dengan gegabah menyederhanakan lebih lanjut: hoax, bukan hanya merokok, mengakibatkan serangan jantung.
Nah, bagaimana kemudian komunikasi publik negara menyikapi masalah seserius ini?
Disinformasi
Tahun 2018 lalu Komisi Eropa mempublikasikan hasil elaborasi sejumlah jurnalis di seluruh dunia untuk memetakan modus operandi hoax. Menurut laporan Komisi Eropa itu, hoax adalah informasi yang tidak ada dasarnya alias informasi fiktif. Karangan. Tidak ada peristiwanya, tidak ada buktinya, tidak ada saksinya, tidak ada datanya. Semua karangan. Seperti novel atau cerpen. Jika merujuk pada kategori ini, gurauan atau satire untuk tujuan komedi juga adalah hoax.
Informasi fiktif bukanlah gejala baru. Sejak awal peradaban, banyak manusia senang mengarang informasi. Bahkan ada yang nekad jadi nabi palsu karena informasi, apalagi jika itu berkaitan dengan masa depan, termasuk kehidupan sesudah mati, adalah sumber kekuasaan. Namun, manusia sudah agak cerdas menghadapi kepalsuan. Jadi kita bisa bernapas lega.
Karenanya Komisi Eropa menyebut ada yang lebih berbahaya dari cerita bohong dan akhirnya menjadi fokus laporannya, yaitu disinformasi atau berita asli tapi palsu. Disinformasi diartikan sebagai beragam fabrikasi (rekayasa) informasi menggunakan peristiwa nyata atau data-data yang ada, namun dengan sengaja diletakkan dalam konteks yang berbeda. Atau datanya dicampuraduk dengan peristiwa yang berbeda, atau bahkan menggunakan teknologi untuk menciptakan diskursus (perdebatan) di tengah masyarakat yang memunculkan ketidakpastian, keraguan bahkan pertengkaran keluarga dan perpecahan sosial. Ini jenis hoax yang berbeda.
Kita langsung tercengang melihat video sejumlah orang dengan seragam dari sebuah lembaga negara, membakar kue kering juga bubuk kopi, dan kita langsung menempelkan merek dagang di video itu dalam ingatan lalu memutuskan tidak akan membelinya karena berbahaya. Padahal selama ini banyak bahan pangan yang dengan mudah dibakar atau terbakar, bahkan ketika mengolahnya, juga dibakar di depan mata kita dan kita tidak keberatan melahapnya sampai habis. Di situlah bahayanya informasi sesat. Ia nampak meyakinkan sehingga menjadi benar. Pikiran kita tidak lagi kritis, tersihir.
Dalam buku pelatihan Jurnalisme “Berita Palsu dan Disinformasi” terbitan UNESCO (2019) diungkap, sebuah studi mutakhir yang dilakukan oleh tim riset Massachusetts Institute of Technology tahun 2018 menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan yang benar, berita palsu terbukti lebih awet umurnya, lebih jauh dan luas jangkauannya, lebih cepat perjalanannya mencapai publik, serta lebih mendalam efeknya terhadap masyarakat luas. Tim peneliti MIT yang terdiri para insinyur tersebut melacak jejak digital dan membandingkan karakter digital dan persebaran kedua jenis berita tersebut, yang benar maupun yang palsu dalam studi tersebut.
Literasi Informasi
Berita asli tapi palsu menjadi amat berbahaya, karena itu menggerus kepercayaan masyarakat terhadap segala informasi dari berbagai sumbernya dan menyebabkan disonansi kognitif yang akhirnya membuat pesimistis. Warga tidak hanya berhak atas informasi dan berhak untuk tahu saja, tetapi berhak atas kesahihan informasi.
Komisi Eropa -belajar dari pemilu AS 2016 dan referendum Inggris isu Brexit di tahun yang sama- mengusulkan agar ada upaya terstruktur, sistematis dan massif dalam melawan hoax melalui 5 strategi, yakni: keterbukaan informasi, literasi warga, pelibatkan jurnalis yang disiplin dalam verifikasi, pemeliharaan ekosistem media yang sehat, serta pemantauan disinformasi.
Membuka akses informasi seluas-luasnya efektif melawan informasi palsu atau informasi sesat. Menyediakan sarana yang mudah (user friendly) dalam mengakses informasi dapat menangkal peredaran informasi sesat. Tentunya, hal itu harus dibarengi peningkatan literasi (melek) informasi dan media pada warga. Keterampilan untuk mencari informasi dan mengonsumsi informasi perlu dimiliki warga, termasuk keterampilan untuk memilih dan mencerna isi media. Karena warga yang tidak melek (illiterate) meski disediakan akses dan kemudahan, tidak akan berperan. Pun berperan, cenderung tidak produktif. Alih-alih malah jadi produsen hoax atau pendengung hoax (buzzer).
Selanjutnya negara melalui kewenangannya dapat ikut memelihara ekosistem media agar tidak terjadi monopoli kepemilikan media serta oligopoli pasar media. Ada lembaga negara yang dapat dilibatkan seperti KPI dan Dewan Pers atau KPPU, selain jajaran kementerian terkait. Media harus diperkuat untuk dapat menjalankan komitmen untuk selalu menyebarkan informasi terverifikasi dan ikut serta dalam barisan fact-checker dunia. Model penyediaan anggaran untuk melatih jurnalis, beasiswa liputan yang independen, atau penempatan iklan layanan masyarakat yang besar dapat ditiru. Negara juga bisa memilih mitra dalam penyebaran informasi yang dikelola PPID dengan tidak melayani jurnalis yang tidak berkomitmen dengan kode etik jurnalistik dan bekerja di perusahaan media yang tidak mau menjalankan UU No.40/1999 tentang Pers. Sekaligus melatih PPID dalam desimenasi informasi publik.
Terakhir, negara memiliki kuasa untuk mengawasi peredaran disinformasi dengan memperkuat dasar hukum yang melindungi hak-hak privasi warga negara serta kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat di muka umum dan kebebasan pers ketika ada tindakan hukum atas peredaran disinformasi. Teknologi dan metode pemantauan disinformasi melalui jaringan internet sudah amat berkembang sehingga peredaran sebenarnya dalam waktu singkat dapat ditindak. Seperti tertuang dalam amar putusan PTUN Jakarta awal Bulan Juni 2020 lalu, dalam kasus pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat, negara tidak boleh menutup akses tapi memiliki tugas mengawasi konten internet untuk alasan tertentu.
Toh anggaran belanja oleh pengadaan patroli polisi siber sudah cukup besar seperti dilaporkan Majalah Tempo?
(bersambung)


