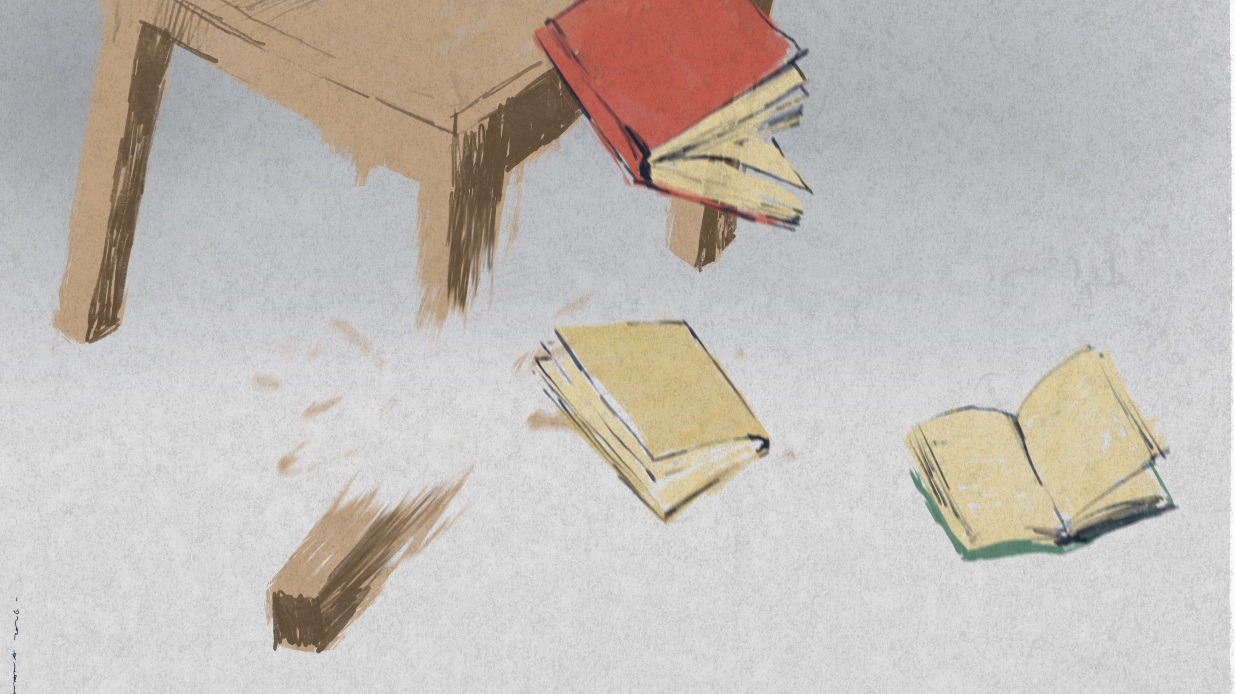MAHASISWA BERSUARA: Cengkeraman Neoliberalisasi Pendidikan dan Resistensi-resistensi Kecil yang Bisa Kita Upayakan
Pada akhirnya kita pun menyadari akar masalahnya: bukan karena kampus “gagal berbisnis”, melainkan justru karena kampus memang berbisnis dalam kerangka kapitalis.

Yoga Firdaus
Mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad)
21 Februari 2026
BandungBergerak – Hari-hari ini, membicarakan pendidikan dalam kerangka yang komersial sepertinya sudah menjadi kelumrahan. Kita melihat pendidikan dengan cara yang sangat korporatis: kampus sebagai penyedia jasa dan mahasiswa sebagai konsumen. Kita, misalnya, sibuk menuntut fasilitas karena sudah membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Bukan berarti hal tersebut salah, tetapi di titik itulah kerangka ideologis ala neoliberalisme menancap dalam kesadaran kita.
Padahal jika kita konsisten dengan amanat UUD 1945, pendidikan perlu didudukkan sebagai hak dasar setiap warga negara. Negara wajib memberikan akses yang adil dan setara. Neoliberalisasi pendidikan bukan kondisi yang niscaya, melainkan kondisi yang bisa digugat dan diperjuangkan secara kolektif. Sudah saatnya tuntutan kita berubah dari “mana fasilitasnya, padahal kita sudah bayar UKT” menjadi “fasilitas yang layak adalah hak warga negara yang wajib diberikan oleh negara”.
Dari Kampus, Dosen, hingga Mahasiswa
Pendidikan yang kian mahal tidak lahir dari ruang hampa. Tidak juga hanya lahir dari perilaku penguasa yang amoral. Namun, ia lahir secara historis dari krisis kapitalisme global. Nabil Haqqillah (2025) mencatat bahwa pada Krisis Malaise 1930, pemerintah kolonial Hindia Belanda “mengorbankan pendidikan dengan melakukan penghematan anggaran pendidikan, khususnya pendidikan bagi kaum bumiputra”. Meski ditentang oleh Volksraad dan serikat guru, kebijakan ini akhirnya tetap dijalankan.
Selanjutnya, pola serupa terjadi dalam krisis 1998. Muridan S. Widjojo dalam bukunya Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa ‘98 menceritakan ketika ekonomi ambruk, rupiah anjlok, kemiskinan melambung menjadi sekitar 118,5 juta orang, dan biaya kuliah menanjak drastis, pemerintah Indonesia menandatangani Letter of Intent (LoI) sebagai perjanjian pinjaman dari The International Monetary Fund (IMF). Dokumen tersebut berisi serangkaian kebijakan neoliberal seperti restrukturisasi perbankan, liberalisasi perdagangan, liberalisasi keuangan, dan deregulasi. Dari situlah deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan mulai terjadi.
Dua tonggak peristiwa ini menegaskan bahwa pemotongan anggaran pendidikan lahir dari kebutuhan mempertahankan kapital dalam krisis. Dan dalam setiap krisis kapitalisme, hak publik di bidang pendidikan selalu dikorbankan demi menjaga stabilitas status quo. Akar masalahnya sesederhana bahwa memang pada dasarnya kapitalisme merupakan bentuk eksploitasi terhadap kita, kelas pekerja. Konsekuensi logisnya: hak publik (kelas pekerja) yang akhirnya akan terus dilucuti demi kepentingan para kapitalis itu.
Secara legal-formal, neoliberalisasi perguruan tinggi di Indonesia dimulai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan PP No. 61/1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (PTN-BH). Dalam kerangka kebijakan ini, PTN diposisikan sebagai lembaga pendidikan yang dapat berbisnis. Dan seperti bisnis pada dasarnya, orientasinya akan mengarah pada bagaimana caranya mengakumulasi modal (mencari keuntungan lebih). Akhirnya, kampus tidak lagi berfokus pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas demi mahasiswa dan masyarakat. Jauh dari gagasan pendidikan holistik ala Ki Hajar Dewantara maupun pendidikan yang membebaskan ala Paulo Freire.
Meski definisi neoliberalisme masih diperdebatkan, secara reduktif neoliberalisme merupakan suatu sistem ideologi yang meradikalisasi prinsip-prinsip kapitalisme dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Gagasan utama dari neoliberalisme terletak pada upaya mengubah realitas sosial ke dalam pemaknaan tunggal: prinsip-prinsip ekonomi kapitalisme. Jadi, cara kerja dunia didikte sesuai dengan prinsip ekonomi seperti kompetisi, individualisme, mekanisme pasar bebas, dan fetisisme komoditas.
Neoliberalisasi pendidikan tinggi bukan hanya jargon ideologis semata, melainkan kondisi material yang kita rasakan sehari-hari. Kita dapat melihatnya dari dua kacamata: kampus dan civitas akademik, khususnya dosen dan mahasiswa.
Dari sisi kampus, riset Idha Christiani (2024) menunjukkan kehadiran PTN-BH sebagai bentuk neoliberalisasi pendidikan. Institusi ini mengalami komersialisasi, privatisasi, komodifikasi, serta kehilangan rasa humanisme di lingkungan akademik. PTN menjadi industri pendidikan yang berorientasi pada bisnis, terlihat dari fenomena naiknya UKT, naiknya Iuran Pengembangan Institusi (IPI), bertambahnya kuota mahasiswa, serta komersialisasi riset.
Ambil contoh apa yang terjadi di Universitas Padjadjaran (Unpad). Membaca dokumen Rencana (Renstra) 2025 dan Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), saya melihat bagaimana rektor mendudukkan Unpad sekaligus membawanya semakin kokoh dalam aras atau visi neoliberalisasi pendidikan. Pendidikan menjadi komoditas yang diperjualbelikan, kampus menjadi lembaga bisnis jasa pendidikan, dan masyarakat menjadi konsumen yang menjadi sumber pendapatan utama.
Neoliberalisasi pendidikan juga menyergap mahasiswa. Ia hadir dalam pilihan-pilihan kita. Ia hadir saat kita tak lagi peduli pada nilai guna dari yang kita produksi, baik tulisan, desain, foto, video, bahkan kerja-kerja reproduktif sekalipun. Yang penting bagi kita adalah bagaimana semua yang kita produksi bisa dialihbentukkan menjadi portofolio yang pada selanjutnya bisa dipertukarkan di pasar kerja, di LinkedIn, di lamaran kerja.
Pertimbangan utamanya adalah apakah sebuah kegiatan bisa berkontribusi pada pemasukan kita, entah saat ini atau di masa depan. Pilihan kita didikte berdasarkan kerangka kerja pasar bebas yang utamanya melihat nilai tukar, alih-alih nilai guna dari apa yang kita kerjakan. Kita tidak lagi berkegiatan untuk “berdampak” dan berguna bagi sesama, melainkan untuk dipertukarkan di pasar kerja.
Kita memilih untuk mengerjakan desain postingan BUMN ketimbang melakukan kerja-kerja advokasi. Bukan karena kita tidak memiliki empati atau sadar isu. Namun, karena kerja-kerja perawatan dan perlawanan tidak bisa dipertukarkan di pasar kerja.
Dalam konteks inilah, lahir hiper-individualisme yang juga menyergap mahasiswa. Menurut Darmini (2024). hiper-individualisme merupakan ciri neoliberalisme yang menempatkan pendidikan sebagai ladang pencapaian pribadi. Mahasiswa hanya fokus memenuhi SKS di kelas dan harus cepat lulus agar dapat segera “bekerja” karena biaya kuliah yang mahal.
Para pendidik kampus juga terperangkap dalam sistem yang sama. Neoliberalisme hadir di ruang kelas dengan beban kerja berlebih saat siang hari, menjelma di rumah saat malam hari dosen harus mengerjakan riset dan menyusun rencana “pengabdian”, dan menampakkan diri dalam bentuk serangkaian dokumen dan kerja-kerja administratif yang melelahkan.
Neoliberalisasi pendidikan menampilkan wajahnya paling nyata di hadapan dosen yang dihadapkan pada kerentanan akan gaji yang layak dan kerapuhan akan kepastian pekerjaan. Ia hadir ketika di sela-sela waktu mengajar, dosen masih harus menyusun materi PPT untuk seminar atau workshop di akhir pekan.
Pada akhirnya kita pun menyadari akar masalahnya: bukan karena kampus “gagal berbisnis”, melainkan justru karena kampus memang berbisnis dalam kerangka kapitalis. Kondisi ini menegaskan bahwa kesejahteraan pendidik hanya mungkin diwujudkan jika pendidikan diperlakukan sebagai hak dasar—bukan sebagai komoditas yang diperebutkan dalam logika pasar.
Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Alam Tak Lagi Bertuan Ketika Mitos Dihancurkan
MAHASISWA BERSUARA: Manusia Budak Kota
Dari Ruang pertemuan Kecil ke Imajinasi Kolektif
Meski neoliberalisme telah merasuki hidup keseharian kita, nyatanya resistensi selalu hadir. Ia hadir dari obrolan di warmindo jam dua pagi saat kita mengeluhkan UKT yang kian melambung. Ia hadir ketika pulang dari kelas dan singgah 15 menit di perpusjal dekat kampus. Ia hadir ketika kita memilih menghidupkan ruang publik dengan diskusi kecil yang rutin.
Resistensi terhadap neoliberalisasi pendidikan juga hadir dalam perbincangan di kantin, di jalanan, di bawah flyover, di sekretariat yang sempit, di sela-sela hidup yang terus bergerak kencang. Ia juga hadir di lorong kampus saat kita berpikir bahwa negara bertanggung jawab atas AC yang mati di kelas karena kurangnya anggaran, dan saat kita tidak terlalu larut membincangkan mahasiswa KIP-K yang baru saja membeli iPhone tetapi lebih tergerak mencari cara untuk menggugat negara agar memberikan pendidikan yang gratis dan layak bagi semua.
Kesadaran perlawanan perlahan dirawat dalam ruang-ruang pertemuan kecil, dan di situlah keberanian untuk berpikir alternatif hadir. Dari titik-titik kecil itu, lahir kembali imajinasi bersama bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dituntut.
Dari situ kita bisa merumuskan agenda secara lebih jelas, yakni menggugat negara agar mengambil peran utama dalam menjadikan pendidikan benar-benar sebagai hak dasar warga negara. Bukan dengan merancang strategi bisnis kampus agar tidak krisis atau memformalkan manajemen keuangan untuk mencari surplus kapital, tapi dengan menegaskan bahwa negara yang bertanggung jawab penuh untuk menyediakan pendidikan dari TK hingga S1 secara gratis dan layak.
Kita harus membangun imajinasi kolektif bahwa jutaan orang peserta didik dan pendidik di Indonesia bersama jutaan warga lain dapat menyerukan tuntutan ini secara serentak. Kesejahteraan dosen dan keadilan akses bagi pelajar hanya mungkin bila pendidikan tidak diperlakukan sebagai barang langka atau komoditas pasar. Pendidikan seharusnya dipandang sebagai public good, non-eksklusif (tak ada orang yang dikecualikan), dan non-rival (kesempatan seseorang tidak mengurangi kesempatan orang lain).
Pertanyaannya kini: sejauh mana kita bisa membangun, merawat, menghidupkan, dan menyambungkan keberanian di tengah segala keterbatasan diri kita sendiri? Atau lebih mendasar: dapatkah kita membayangkan sebuah dunia di mana hak atas pendidikan benar-benar diraih? Keberhasilan ada dalam jangkauan imajinasi kritis bersama, selama kita menolak dininabobokkan oleh narasi neoliberal, dan bersikeras bahwa pendidikan adalah hak bukan komoditas.
***
*Esai ini termasuk dalam 28 esai terpilih Sayembara Menulis Esai Kritis Mahasiswa Bersuara 2025
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB