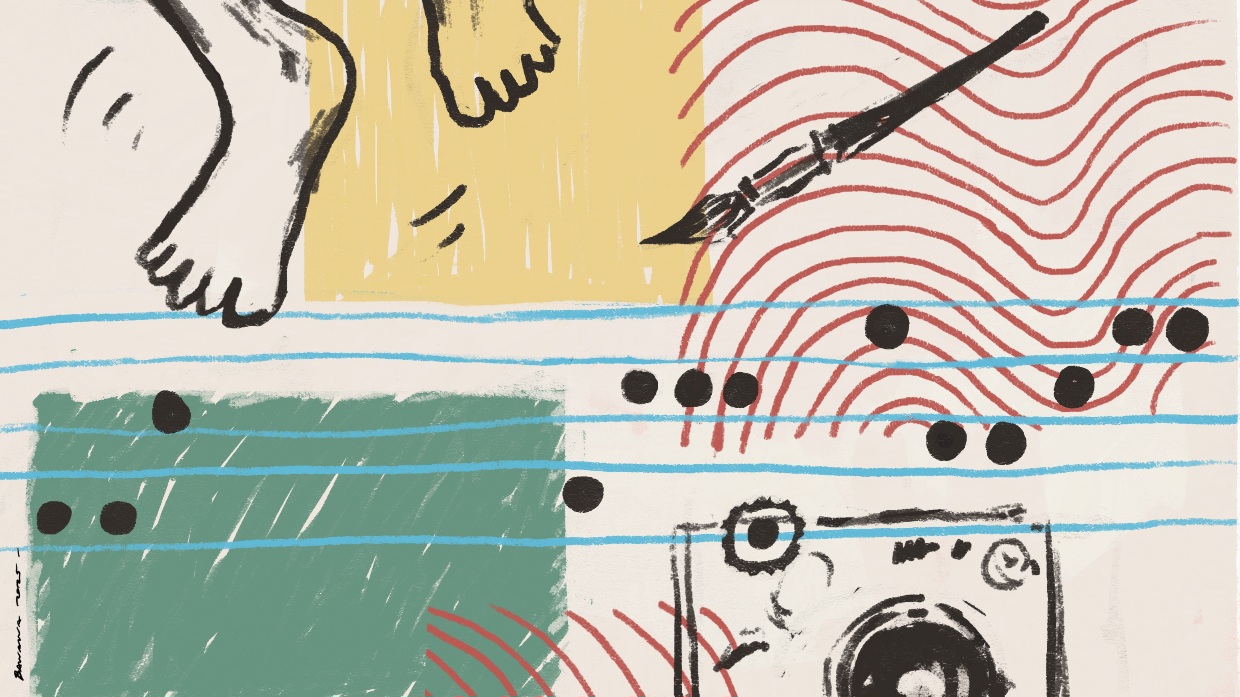CATATAN SI BOB #25: Esok Pagi, Kita Putus Asa
Marx mungkin akan terkejut melihat surplus value di era streaming: pekerja seni yang teralienasi dari karya sendiri.

Bob Anwar
Musisi dan penulis asal Kota Bandung. Dapat di hubungi di Instagram @bobanwar_ atau [email protected]
30 September 2025
BandungBergerak - Roderick bangun pukul tiga pagi. Bukan karena mimpi buruk, karena mimpi buruk datang kemudian, ketika mata terbuka dan ponsel menyala. Angka itu berkedip: 100 pendengar bulan ini. Seperti termometer macet, hidup stagnan di suhu yang sama. Dalam mitologi digital, algoritma adalah dewa yang menentukan nasib. Dan Roderick, seperti Sisyphus, mendorong lagunya ke puncak trending topik, melihatnya jatuh, lalu mengulangi.
Kata "viral", dari bahasa latin virus, adalah racun yang telah menjadi obsesi. Sesuatu menyebar dengan cepat, menginfeksi, lalu mati. Ironi yang pahit: Roderick mengejar racun ini dengan gitar bolong dan software bajakan. Ia menulis tentang patah hati yang tak pernah ia alami, berdasarkan riset platform X dan analisis playlist Spotify. Seperti antropolog yang mempelajari suku asing tanpa pernah tinggal bersama mereka, ia menulis kesedihan dengan jemari kering air mata.
Baca Juga: CATATAN SI BOB #24: Royalti dan Senar Gitar Rimbaud
CATATAN SI BOB #23: Makan Siang di Bengkel Gitar Endo Suanda
Teralienasi
Ada yang aneh dengan transformasi ini. Dulu – selalu ada kata "dulu" ketika nostalgia menyerang – ia menulis tentang hujan ibu kota yang benar-benar membasahi kemejanya. Kini ia menulis hujan berdasarkan data cuaca dan sentimen media sosial. Metamorfosis yang menggelisahkan: dari penyair menjadi analis data. Darwin pun tak pernah membayangkan natural selection berlaku pada industri kreatif.
Formula telah menggantikan intuisi. Lagu viral: intro delapan ketuk, chord progression vi-IV-I-V, lirik tentang rindu dengan rhyme scheme ABAB, durasi tiga menit empat detik. Golden ratio untuk algoritma YouTube. Roderick menghafal resep ini seperti mantra suci. Tapi siapa Tuhan yang ia sembah? Spotify dengan 0,003 dollar per stream? TikTok dengan 15 detik keabadian? Atau hantu Adam Smith yang membisikkan tentang invisible hand di telinga para content creator?
"Berapa penghasilan streaming bulan ini?" Kalimat yang selalu mengakhiri percakapan tentang seni. Seperti menanyakan berapa kilogram berat sebuah puisi. Roderick driver ojol siang hari, musisi malam hari. Ironi zaman: ia mengantarkan orang ke tujuan mereka sementara dirinya tersesat di jalan yang sama setiap hari. Dualitas yang menghasilkan kelelahan, bukan dialektika.
Platform digital berjanji demokrasi: setiap orang bisa viral. Tapi demokrasi macam apa yang dikontrol bot? Seperti pemilu dengan satu calon. Label besar masih memegang kendali distribusi seperti cukong yang menguasai pelabuhan. Roderick mendapat remah dari roti yang ia panggang sendiri dengan keringat digital. Marx mungkin akan terkejut melihat surplus value di era streaming: pekerja seni yang teralienasi dari karya sendiri.
Pertanyaan pun mengambang di atas fret gitar: untuk siapa Roderick bernyanyi? Untuk pendengar yang mungkin tidak pernah ada? Untuk bot yang menghitung engagement rate? Untuk cermin yang memantulkan bayang dirinya yang dulu percaya musik bisa mengubah dunia? Roderick mulai merasakan patah hati yang ia tulis untuk algoritma.
Metamorfosis mengerikan terjadi tanpa disadari. Kesedihan artifisial yang ia jual perlahan menjadi kesedihan otentik. Seperti aktor yang terlalu dalam menghayati karakter tragis. Roderick mulai merasakan keputusasaan yang ia nyanyikan untuk market research. Produk mengonsumsi produsennya. Midas digital: semua yang ia sentuh menjadi konten, tapi konten itu dingin dan tanpa jiwa.
Media sosial menuntut setiap seniman menjadi brand ambassador dirinya sendiri. Musik hanya satu elemen dari personal branding ecosystem. Roderick harus pintar storytelling, harus tahu kapan posting untuk optimal engagement, harus menguasai bahasa visual yang menarik di tengah lautan konten. Seperti dalang yang juga harus menjadi penonton pertunjukannya, ia kehilangan jarak kritis terhadap karyanya.
Malam ini, laptopnya kembali menyala. DAW terbuka, dan deadline, yang sebenarnya tak ada, menghampirinya segalak penagih pinjol. Ia harus menciptakan sesuatu yang "relatable" tapi unik, melankolis tapi tidak terlalu dark sampai merusak mood pendengar. Kontradiksi Zeno dalam bermusik: semakin ia mendekati autentisitas, semakin jauh dari viralitas. Semakin dekat ke viral, semakin jauh dari jiwanya.
Siklus yang Sama
Esok pagi, Sisyphus digital akan bangun lagi pukul tiga. Ritual yang telah menjadi liturgi: cek analytics, scroll media sosial, menyalakan rokok. Putus asa bukan lagi perasaan temporer, tetapi menjadi existential condition. Roderick mendorong musiknya ke puncak algoritma, melihatnya tenggelam dalam lautan konten, lalu mengulangi siklus yang sama.
Camus menulis bahwa kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Bisakah kita membayangkan Roderick menemukan kebahagiaan dalam pengakuan akan absurditas sistemnya? Dalam kesadaran bahwa ia telah menjadi pekerja digital yang teralienasi, mungkin tersembunyi satu-satunya lagu yang benar-benar ia rasakan: lagu tentang keterasingan itu sendiri.
Atau pertanyaan ini pun sudah menjadi konten yang siap dimonetisasi?
27/09/2025
***
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB