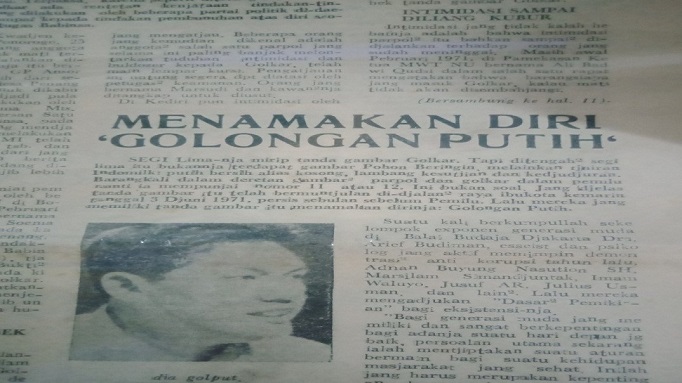Dilema Golput
Golongan Putih (Golput) pada awalnya merupakan gerakan moral menghadapi tidak sehatnya iklim politik pemilu 1971. Dalam perkembangannya mengancam legitimasi pemilu.

Indra Prayana
Pegiat buku dan surat kabar
23 Mei 2023
BandungBergerak.id – Dalam sebuah survei sederhana yang kami lakukan di antara teman-teman guru SMA Pasundan 8 Bandung, diajukan pertanyaan siapa calon presiden (capres) yang akan dipilih pada perhelatan pemilu 2024 mendatang ? Tentunya nama-nama capres yang disodorkan itu selaras dengan yang di gadang-gadang oleh partai politik pengusungnya, seperti nama Prabowo Subianto (Gerindra), Ganjar Pranowo (PDIP), Anies Baswedan (Nasdem) atau Airlangga Hartato (Golkar), dll.
Beberapa orang guru menjawab “belum ada pilihan”, “gak ada yang cocok sama sekali”, ataupun abstain terhadap capres-capres yang ada itu. Jawaban-jawaban tersebut bisa jadi mencerminkan sebuah representasi masyarakat lain yang belum mempunyai pilihan. Artinya kalau pemilihan presiden diadakan hari ini tentu banyak orang yang akan bersikap sama, yakni tidak ada capres yang bisa dipilih, oleh karena tidak mempunyai pilihan maka bisa jadi tidak akan ikut pemilu. Dalam perspektif politik disebut sebagai massa mengambang (floating mass) atau kelompok orang yang belum mempunyai pilihan politik dan itu jumlahnya sangat besar, yang harus menjadi perhatian serius dari partai poitik karena bisa berpotensi menimbulkan apatisme terhadap pemilu.
Baca Juga: Pers dan Partai Politik Kita
Buku-buku Bandung Paling Antik, Langka, dan Unik
Manifesto Seorang Ulama Pejuang
Golput Sebagai Gerakan Ekstraparlementer
Sejarah mencatat pasca kemenangan politik pemerintahan orde baru yang ditandai naiknya Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI ke-2 telah mengubah arah kehidupan sosial politik yang ada. Pemimpin orde baru ini naik tahta berdasarkan ketetapan MPRS tertanggal 12 Maret 1967 menggantikan rezim pemerintahan Soekarno yang secara de facto telah rontok legitimasinya di hadapan rakyat.
Terbentuknya pemerintahan yang baru sedikitnya telah meredakan iklim politik yang memanas sebelumnya, dan meskipun orde baru sudah semakin terkonsolidasi tetapi tuntutan untuk melaksanakan pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat semakin kencang disuarakan. Sehingga akhirnya pemilu baru bisa dilaksanakan pada bulan Juli di tahun 1971 yang diikuti oleh 10 kontestan, yakni: PNI, Partai NU, Perti, Parmusi, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Golongan Karya (Golkar). Hasilnya sudah bisa diprediksi dengan kemenangan Golkar dengan perolehan suara hampir 65% dari jumlah pemilih saat itu.
Dari seluruh kontestan pemilu yang ada ternyata tidak cukup memuaskan semua kalangan, terutama bagi generasi muda dan mahasiswa yang menginginkan perubahan secara mendasar. Ketidakpuasan itu terwakili dengan keberadaan gerakan ekstra parlementer Golongan Putih (Golput) sebagai wujud ketidakpercayaan terhadap sistem politik beserta perangkatnya.
Istilah Golput sendiri baru muncul setelah dipicu oleh artikel Imam Walujo Sumali di Harian KAMI edisi 12 Mei 1971 dengan tajuk “Partai ke Sebelas untuk Generasi Muda” sebagai alternatif dari semua partai politik peserta pemilu. Tulisan tersebut cukup menuai polemik di kalangan masyarakat. Disusul dengan pertemuan sekelompok eksponen pemuda pada awal Juni 1971 bertempat di Balai Budaya Jakarta, untuk mendeklarasikan sebagai Golongan Putih. Aktivis yang hadir pada pertemuan tersebut di antaranya Arief Budiman, Adnan Buyung Nasution, Marsilam Simandjuntak, Imam Walujo S, Julius Usman, dll.
Golput menggunakan gambar segi lima mirip dengan gambar Golkar tetapi dengan latar putih/kosong, yang dimaknai sebagai “kesucian dan kejujuran”. Arief Budiman sebagai inisiator Golput menyebut bahwa gerakan ini merupakan “kata yang tidak berkata” sebagai respons terhadap aturan main pemilu yang tidak adil dan demokratis. Sejak pendeklarasiannya, gambar-gambar Golput mulai nampak di ruang publik, tidak hanya di Jakarta tetapi tersebar juga di kota besar lainnya.
Golput pada awalnya hanya sebagai gerakan moral yang memberikan alternatif atas tidak sehatnya iklim politik pemilu 1971, tetapi dalam perkembangannya selalu menjadi bola salju di setiap pelaksanaan pemilu. Keberadaannya dianggap mengkhawatirkan mengancam legitimasi dan keabsahan suatu “pesta demokrasi”. Jumlahnya pun sangat signifikan, sebagai perbandingan pada pemilu 2019 berdasar pada data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa sekitar 34,75 juta orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau menjadi golongan putih. Jumlah itu setara dengan 18,02% dari seluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 yang jumlahnya sebanyak 192,77 juta orang. Dalam data BPS juga mengidentifikasi bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang penduduknya paling banyak tidak menggunakan hak pilihnya, jumlahnya sebanyak 5,8 juta jiwa atau 17,43% dari total pemilih di Jawa Barat.
Fenomena yang sama kemungkinan akan muncul juga pada pemilu 2024 mendatang. karena karakter Golput tidak berdiri sendiri. Setidaknya ada beberapa alasan kenapa orang bersikap golput atau tidak ikut memilih dalam pemilu. Pertama, seseorang tidak ikut pemilu karena tidak memiliki trust (kepercayaan) terhadap sistem ataupun partai politik yang ada, tentunya dengan pemahaman dan kesadarannya sendiri yang kritis. Kedua, mungkin saja seseorang tidak ikut memilih dikarenakan waktunya bersamaan dengan jam kerja dan aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan, ketiga bisa jadi tidak ikut pemilu karena bersikap masa bodoh dan tidak peduli, dsb.
Sedangkan kepada pihak yang mengampanyekan Golput, penyelenggara pemilu mengantisipasinya dengan membuat payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, dalam pasal 515 disebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36 Juta”.
Bahkan dalam beberapa kesempatan pemilu sebelumnya, sebagian ulama dan ormas keagamaan juga pernah menetapkan fatwa haram kepada fenomena Golput ini. Persoalan memilih atau tidak memilih ini telah menjadi dikotomisasi dan diseret ke wilayah transendental meskipun pemilu merupakan hak bukan kewajiban. Sebagaimana hak tentunya bisa diambil ataupun tidak diambil dan kedua pilihan tersebut sangat konstitusional, tidak bisa dimasukkan dalam wilayah melanggar hukum pidana.
Membangun argumentasi dengan “menghukum” Golput sebagai orang yang tidak bertanggung jawab terhadap bangsa, tidak peduli terhadap keberlangsungan bernegara atau anti nasionalisme, menjadi kurang relevan karena penilaian terhadap semua itu tidak berlangsung dalam setiap hajatan 5 tahun sekali. Belum lagi kalau penilaiannya di wilayah terminologi keagamaan yang mempunyai pakem mutlak, hitam dan putih tentunya akan lebih berdampak serius. Sebenarnya dalam islam suksesi kepemimpinan tanpa melalui proses pemungutan suara pernah terjadi pasca Nabi Muhammad S. A. W. wafat dan digantikan Abu Bakar Asshidiq, begitu pula ketika Umar bin Khattab naik menjadi Amirul Mukminin tidak semua kelompok mendukung, ada yang bersikap oposisi dan kritis terhadap kepemimpinannya. Bahkan dalam pidato pelantikannya sebagai Khalifah, Umar Bin Khattab mendapat ancaman dan peringatan keras dengan mengacungkan pedang dari orang yang tidak mendukungnya sebagai khalifah. Tetapi Umar bin Khattab tidak lantas menolak apalagi menghukum orang atau kelompok yang kontra, bahkan ia berucap syukur karena ada yang mengingatkan perihal tanggung jawab yang berat bagi seorang pemimpin.
Klaim pemilu sebagai jaminan untuk menghasilkan pemimpin yang mempunyai rekam jejak mumpuni dari segi manajerial maupun spiritual tidak sepenuhnya tepat, karena kita tidak mempunyai banyak pilihan terhadap figur-figur yang telah disediakan oleh partai politik. Tetapi meskipun begitu realitas politik menempatkan pemilu sebagai sarana kita untuk memilih wakil rakyat, presiden dan wakil presiden mendatang. Sedangkan pada sisi lainnya ada orang yang memilih bersikap golput, baik secara sadar ataupun tidak. Kelompok ini tidak bisa diabaikan begitu saja karena jumlahnya yang tidak sedikit, dan keberadaan Golongan Putih akan selalu menjadi perhatian sekaligus menjadi kekhawatiran dalam setiap hajatan pemilu.