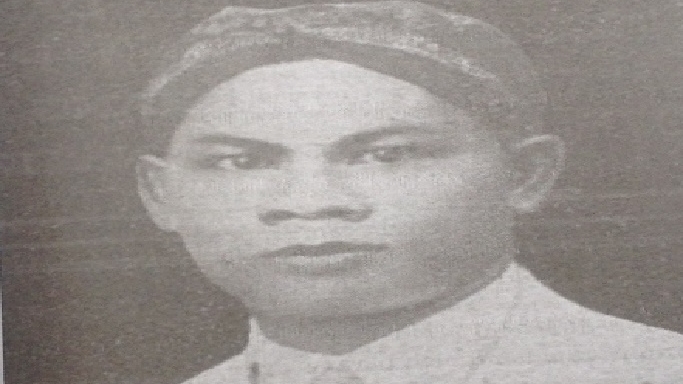MEREKA YANG PERNAH BERGERAK DI BANDUNG #6: Jejak Langkah “Si Jalak Harupat” yang Berakhir Secara Tragis
Oto Iskandar di Nata (1897-1945) dituduh menjual Kota Bandung pada Belanda.

Andika Yudhistira Pratama
Penulis tinggal di Padalarang
26 Juli 2023
BandungBergerak.id – Pada 25 Oktober 1958, Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta menggelar sidang lanjutan terkait pembunuhan Oto Iskandar di Nata, Menteri Negara Kabinet RI pertama tahun 1945. Dalam persidangan tersebut, dua orang saksi dan satu pelaku memberi keterangannya.
Dalam surat kabar Merdeka edisi 27 Oktober 1958, Mudjitaba bin Murkam – terdakwa pembunuhan Oto dari Laskar Hitam – kepada hakim, ia menyatakan tidak mengetahui penyebab dari penangkapan dan pembunuhan terhadap Oto dan H. Hasbi di pesisir pantai Mauk, Tangerang. Sebuah pernyataan yang tidak masuk akal bagi hakim.
Sedangkan Djumadi sebagai saksi pertama, pada saat peristiwa pembunuhan terjadi menjabat sebagai kepala BKR (Badan Keamanan Rakyat) di Mauk. Ia memberi keterangan bahwa pada suatu petang di bulan Desember 1945, Mudjitaba bersama empat orang lainnya dari laskar Hitam tiba di markasnya dengan membawa H. Hasbi ke hadapannya.
Dengan golok di tangannya, Mudjitaba berkata kepada Djumadi, "Ini saja tarok mata2 musuh, sebentar akan saja bawa lagi ke sini seorang mata2 musuh dari Bandung." Setelah itu, sambil berjalan meninggalkan Djumadi, ia kembali berkata, "Ini jangan hilang, kalau hilang gantinya orang2 di sini."
Selanjutnya, Mudjitaba membawa Oto ke hadapan Djumadi, sosok yang sudah dikenalnya sejak tahun 1932. Meski begitu, rasa takut menyebabkan dirinya tidak dapat berbuat banyak untuk membebaskan dan menyelamatkan kedua tahanan laskar Hitam tersebut dari maut.
Saksi lainnya, Achmad Kawi – eks anggota BKR di Mauk – turut memberi kesaksian. Menurutnya, ia bersama rekannya, Ishak, pernah diperintahkan Djumadi atas permintaan Mudjitaba, untuk mengantarkan terdakwa mengambil kedua korban di rumah penjara Mauk. Saat itu, ia melihat bahwa kedua korban sudah dalam keadaan tidak berpakaian dan tangan diikat. Kedua korban kemudian dimasukkan ke dalam sebuah mobil, termasuk dirinya mengiringi perjalanan membawa kedua tahanan tersebut, untuk mengawal Mudjitaba.
Setibanya di Pantai Ketapang, Tangerang, ia melihat segerombolan orang dengan berbekal berbagai macam senjata tajam di tangan, sudah menunggu kedatangan dua orang tahanan yang dibawa Mudjitaba. Selanjutnya, ia mendengar rintihan Oto di hadapan gerombolan tersebut, "Jah nak, saja djangan dimatiin, saja orang baik." Mendengar itu, gerombolan tersebut berteriak, "Mata2 musuh Jang dijual kota Bandung satu miliun."
Seturut Iip D. Yahya dalam Oto Iskandar di Nata: The Untold Stories (2017), tidak lama kemudian darah Oto mengucur deras setelah belati menyasar lehernya. Setelah itu, Mudjitaba dan gerombolan laskar Hitam pergi meninggalkan kedua korbannya tersebut.
Baca Juga: MEREKA YANG PERNAH BERGERAK DI BANDUNG #3: Secuplik Kisah Perjalanan Politik dan Jurnalistik S. K. Trimurti
MEREKA YANG PERNAH BERGERAK DI BANDUNG #4: Maskoen Soemadiredja dalam Gemuruh Zaman Bergerak
MEREKA YANG PERNAH BERGERAK DI BANDUNG #5: Wage Rudolf Supratman, Komponis dan Jurnalis Pergerakan
Dalam Zaman Bergerak
Oto Iskandar di Nata lahir pada 31 Maret 1897 di Bojongsoang, Bandung. Ia adalah anak dari pasangan R. Nataatmaja (R.H. Rachmat Adam) dan Siti Hadidjah. Ia mengenyam pendidikan di sekolah Bumiputera 1, yang kemudian berganti nama menjadi HIS Karang Pawulang, Bandung, pada tahun 1907. Selanjutnya pada tahun 1914, ia sekolah di HIK (sekolah guru) dan melanjutkannya di HKS Purworejo (sekolah guru atas) pada tahun 1917.
Setelah itu pada tahun 1920, ia menjadi guru di HIS (Holland Inlandsche School) Banjarnegara. Satu tahun kemudian, kariernya sebagai guru berlanjut di "HIS volksondereijs (perguruan rakyat) Bandung," tulis Iip D. Yahya dalam Oto Iskandar di Nata: Perintis Tentara Republik Indonesia (2022).
Selama masa pergerakan, ia bergabung dengan Budi Utomo (BU) cabang Bandung pada tahun 1921 dan menjadi wakil ketua pada tahun 1924. Terdapat tiga hal yang menarik dirinya untuk bergabung dengan BU, antara lain: budaya, keinginan merdeka, dan babad.
Menurutnya, BU adalah jalan untuk mencapai kemerdekaan. Setidaknya hal itu tercermin dalam pidatonya pada 12 September 1921, di Gedung Societet (sekarang Gedung Merdeka). Dalam kesempatan tersebut, Oto berujar "Kalaupun perkumpulan lokal seperti Paguyuban Pasundan harus dibubarkan, ia rela, asal persatuan itu tercapai. [...] ia bernazar akan menyembelih ayam. [...] Menurutnya, Budi Utomo adalah wadah persatuan bagi suku Jawa, Sunda, Madura, dan Bali."
Pidato tersebut menuai polemik. Sutisna Senjaya, selaku perwakilan Paguyuban Pasundan mempertanyakan sikap Oto tersebut, "Apa yang salah dengan keberadaan Paguyuban Pasundan sebab toh tujuannya sama, jadi mengapa harus ada keinginan Pasundan untuk bubar. Oto menganggap BU wadah bagi semua pengisi Pulau Jawa, sementara Sutsen memandang BU lebih identik dan memperjuangkan kepentingan orang Jawa, sementara orang Sunda lebih merasa nyaman berjuang melalui Pasundan yang tentu akan lebih memperhatikan kepentingan orang Sunda," tulis Iip D. Yahya (2017).
Polemik berlanjut dalam surat kabar dan turut menyeret tokoh Paguyuban Pasundan lainnya seperti, Ema Bratakusumah, Yusuf, Odang, dan Prawira Direja. Meski begitu, pendirian pria kelahiran Bojongsoang tidak surut. Bahkan ia menaikkan nazarnya dengan menyembelih kambing.
Namun, polemik mulai mereda pada 21 Oktober 1921, setelah Oto meminta pihak redaksi Siliwangi untuk menghentikan pemuatan berita yang memuat perdebatan yang disulut oleh pidatonya di Gedung Societet tersebut.
Pada tahun 1928, saat ia hijrah untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Muhammadiyah di Batavia, ia meninggalkan BU dan memantapkan pilihan untuk berlabuh dan bergerak bersama Paguyuban Pasundan hingga dipercaya menjabat Sekretaris Hoofdbestuur (pengurus besar). Keputusannya tersebut tidak terlepas dari "sektarian" dalam tubuh BU yang sangat terbatas pada kepentingan suku Jawa. Hal itu tentunya menggugurkan upayanya untuk mempersatukan suku-suku di Pulau Jawa ke dalam organisasi yang didirikan pada tahun 1908 tersebut.
Satu tahun kemudian, ia menjabat sebagai Ketua Umum yang gigih dalam menyeru kemandirian untuk organisasi terbesar orang Sunda tersebut, terutama dalam hal pendidikan. Maka tidak mengherankan sejak saat itu, hampir setiap cabang Paguyuban Pasundan mendirikan sekolah Pasundan.
Di samping itu, ia menjadi perwakilan Paguyuban Pasundan dalam Volksraad (Dewan Rakyat bentukan Pemerintah Hindia-Belanda) selama tiga periode dari tahun 1930-1942. Selama itu, ia dikenal sebagai sosok yang vokal menentang kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang tidak memihak bangsanya. Tidak mengherankan jika dirinya kelak menyandang nama "Si Jalak Harupat" atas keberaniannya tersebut.
Saat Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942, Oto masuk dalam jajaran Cuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat pada masa pendudukan Jepang). Selanjutnya, ia turut menginisiasi pembentukan Badan Pembantu Prajurit Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho yang "[...] diresmikan pada Rabu, 8 Desember 1943," Tulis Iip D. Yahya (2022).

Terjun dalam Dunia Jurnalistik dan Olahraga
Selain dikenal sebagai agitator yang cukup disegani, khususnya di kalangan masyarakat Sunda, ia juga dikenal sebagai jurnalis. Titik awalnya, dimulai saat ia menjabat sebagai Direktur Umum surat kabar milik Paguyuban Pasundan, Sipatahoenan, sejak kepindahan kantor redaksinya dari Tasikmalaya ke Bandung pada tahun 1931.
Seturut Indra Prayana dalam Jejak Pers di Bandung (2021), memasuki tahun 1942, Sipatahoenan terpaksa menghentikan penerbitannya. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemerintahan Militer Jepang yang membubarkan organisasi dan menutup penerbitan surat kabar yang ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Sebagai sosok yang berpengaruh di masyarakat Sunda, ia diangkat sebagai direktur surat kabar propaganda Jepang, Thahaja yang terbit di Bandung dan berkantor di Groote Postweg Oost (kini Jalan Raya Pos Timur no. 54-56).
Memasuki tahun 1944, ia memimpin majalah Pradjoerit, yang diterbitkan sebagai upaya "[...] untuk mengideologisasi para prajurit Peta dan Heiho. Juga memberikan pengetahuan umum yang dirasakan masih kurang dimiliki oleh para prajurit Indonesia," tulis Iip D. Yahya (2022).
Selanjutnya, olahraga menjadi lini berikutnya yang dijamah "Si Jalak Harupat". Masih pada masa pendudukan Jepang, pada 1 Juni 1943, ia diangkat menjadi Pemimpin Umum Gelora (Gerakan Latihan Olahraga) – induk olahraga pada masa pendudukan Jepang. Selain itu, ia menjadi bagian dari Jawa Rengo Tai Iku Kai (organisasi untuk melatih jasmani dan rohani penduduk di pulau Jawa).
Baginya, olahraga bukan sekedar untuk keperluan fisik saja, melainkan berhubungan dengan budi pekerti. Lebih lanjut ia mencontohkan sepak raga (nama sepak bola saat itu) sebagai olahraga yang sesuai dengan pandangannya.
Keterlibatannya dalam induk/organisasi olahraga, tidak terlepas dari kegemarannya terhadap olahraga, khususnya sepak bola. Bahkan sejak masa kolonial Hindia Belanda, ia pernah memimpin klub sepak bola THOR di Pekalongan pada tahun 1924-1926 dan tercatat aktif mengelola Ikatan Sport Indonesia (ISI) – semacam induk olahraga yang didirikan Bumiputera pada masa kolonial.
Di samping itu, ia tercatat sebagai anggota Hoofdbestuur PSSI dan pernah menjadi ketua pelaksana Kongres PSSI di Bandung pada tahun 1936. Sebagai ketua, ia pernah diundang untuk memberikan masukan dan "memotivasi para pemain Persib agar meraih prestasi terbaik," tulis Iip D. Yahya (2017).
Sebelum dan Sesudah Proklamasi Kemerdekaan
Mengutip Iswara N. Raditya dalam "Otto Iskandar Dinata: Misteri Kematian Jagoan dari Bojongsoang", setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Oto termasuk dalam anggota PPKI. Ia pula yang mengusulkan pengangkatan Sukarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden.
Selanjutnya, ia menduduki jabatan Menteri Negara yang ditugasi untuk mengurus persoalan keamanan cum mengkoordinir pembentukan militer yang saat itu masih bernama Badan Keamanan Negara (BKR) menjadi militer yang terorganisir sebagai kekuatan pertahanan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang terlepas dari pengaruh militer Jepang dan Belanda.
Pada saat itu, tugasnya terbilang sangat riskan, sebab tidak semua kalangan militer dengan berbagai latar belakang menyetujui idenya tersebut dan lebih memilih membentuk laskar-laskar militer sendiri. Mereka inilah yang kemudian tidak menyetujui sikap diplomatis pemerintah di bawah Perdana Menteri Sjahrir yang dianggap terlalu lunak kepada sekutu.
Hal itu berdampak pada terhambatnya penyerahan senjata Jepang kepada pemuda di Bandung. Sejak saat itu, Oto sebagai Menteri Negara dan tokoh di Bandung mulai dicurigai telah "menjual kota Bandung satu miliun, agen NICA!" dan semakin kencangnya desas-desus "Oto sebagai mata-mata Belanda."
Mengutip kembali Iip D. Yahya (2017), di tengah situasi yang sedemikian panas tersebut, Oto diperintahkan untuk datang ke Jakarta, setelah menerima kawat dari Presiden Sukarno. Selanjutnya, fitnah kepada Oto semakin kencang, hal ini tidak terlepas dari pertemuannya dengan Keosna Peoradiredja, mantan tokoh organ pemuda Pasundan (JOP) yang pro kepada NICA di Jakarta. Padahal dalam pertemuan tersebut, Oto bermaksud untuk melobi Koesna agar berpihak pada Republik.
Oto terlanjur dicap sebagai pengkhianat bagi sebagian pihak, maka pada 10 Desember 1945, saat sedang bercakap dengan Sanusi Hardjadinata di Jalan Kapas, Jakarta, Oto diculik sekelompok pemuda yang dipimpin Mudjitaba menuju sebuah penjara polisi di Tangerang.
Selanjutnya, pada 19 Desember 1945, oleh Mudjitaba, ia dihadapkan kepada Achmad Chairun – salah satu anggota Direktorium Tangerang yang memisahkan diri dari NKRI di samping Sumo – setelah itu, Oto dititipkan pada sebuah tahanan di Mauk yang berada di bawah pengawasan anggota BKR, Djumadi.
Penculikan dan pembunuhan terhadap "Si Jalak Harupat" yang terjadi dari tanggal 10-20 Desember 1945, saat itu kurang mendapat tanggapan yang berarti. Bahkan hingga 29 Desember 1950 Presiden Sukarno belum yakin bahwa pendukungnya tersebut telah wafat, dan hanya bisa mendoakan saja jika benar-benar wafat. Pengusutan atas kematian Oto berjalan alot hingga pada akhirnya dihentikan sekitar pada tahun 1959.
Karena sulitnya untuk melacak jasad Oto, maka sebagai peringatan untuk kematiannya, pada 20 Desember 1952 dilaksanakannya pemakaman kembali "Syarat Jenazah" dalam bentuk berupa pasir dan air laut dari Mauk.
Lebih lanjut, menurut Iip D. Yahya (2017), jika merujuk kepada keterangan terdakwa Mudjitaba dalam pengadilan tahun 1958, yang tidak mengetahui bahwa sosok yang ditahan dan dibunuhnya adalah Oto Iskandar di Nata, maka besar kemungkinan terdapat dalang di balik peristiwa pembunuhan dan laskar Hitam hanya bertindak sebagai eksekutor dalam peristiwa tersebut.
Pada tanggal 6 November 1973, untuk mengenang jasa-jasanya, Oto Iskandar di Nata ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 088/TK/Tahun 1973.