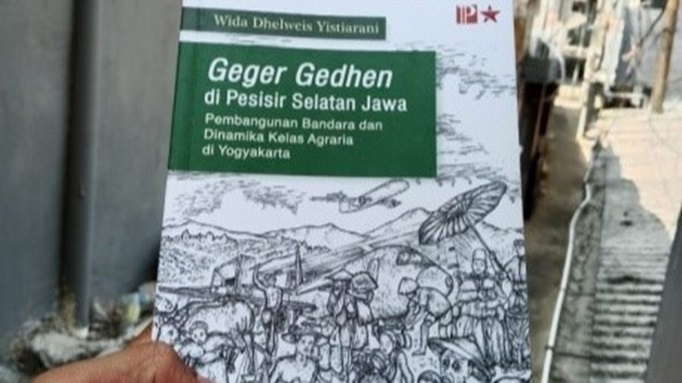RESENSI BUKU: Geger Gedhen di Pesisir Selatan Jawa, Kisah Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta dan Nasib Petani Desa
Buku Geger Gedhen di Pesisir Selatan Jawa (2024) karya Wida Dhelweis Yistiarani, memotret penghidupan petani desa yang terdampak pembangunan bandara Yogyakarta.
Penulis Patrisius Eduardus Kurniawan Jenila 25 Agustus 2024
BandungBergerak.id – Pembangunan infrastruktur sering dipahami sebagai “berkat”. Dalam arti ini, hadirnya pembangunan infrastruktur di suatu wilayah dapat mendorong “pertumbuhan ekonomi”. Dengan pembangunan infrastruktur itu pula, suatu daerah diklasifikasikan sebagai daerah maju. Sebaliknya, daerah terbelakang dikategori sebagai daerah dengan tingkat pembangunan infrastruktur yang minim.
Lantas apakah memang seperti itu? Siapa yang dirugikan dari pembangunan infrastruktur itu? Nyatanya tak semua pembangunan infrastruktur menghasilkan “berkat” bagi orang-orang di sekitar. Sebaliknya, adanya pembangunan infrastruktur justru dapat menciptakan “persoalan baru”. Persoalan baru itu bisa terkait dengan hilangnya pekerjaan seorang buruh tani, hilangnya lahan milik seorang petani, dan bisa terkait dengan akumulasi kekayaan pada segelintir orang karena adanya pembangunan infrastruktur.
Buku “Geger Gedhen di Pesisir Selatan Jawa”, yang ditulis oleh Wida Dhelweis Yistiarani, merupakan sebuah buku yang mengkaji tentang pembangunan bandara udara internasional Yogyakarta [Yogyakarta International Airport/ YIA]. Buku ini mengupas terkait dampak kehadiran pembangunan bandara udara di Kulonprogo itu terhadap penghidupan petani di Desa Geger Gedhen (bukan nama sebenarnya). Petani di Desa Geger, sebagaimana temuan buku ini, mengalami “nasib yang berbeda-beda” sebelum dan pasca pembangunan Yogyakarta International Airport [YIA].
Baca Juga: RESENSI BUKU: Membaca Catatan Hasil Semedi di Toilet
RESENSI BUKU: Sebuah Buku yang Tidak Ditujukan untuk Malaikat dan Iblis
RESENSI BUKU: On The Road, Mencari Kebebasan Melalui Pengembaraan
Dinamika Kelas Agraria dan Penghidupan Petani Desa Geger
Penulis buku ini mendekatkan pembacaan akan pembangunan YIA dengan memakai perspektif analisis kelas Marxis untuk memotret kehidupan petani di Desa Geger. Penulis menyoroti keadaan petani di Desa Geger sebelum adanya pembangunan YIA dan pasca pembangunan YIA, yang mengalami “diferensiasi kelas” sebagai akibat dari adanya dinamika agraria yang mereka hadapi.
Jauh sebelum pembangunan YIA, petani di Desa Geger, sebagaimana temuan Wida, sudah terdiferensiasi ke dalam “lokasi kelas” berdasarkan alat produksi dan relasi produksi. Petani sebagaimana ditunjukkan lewat buku ini bukanlah satu entitas yang homogen, harmonis, dan berlandaskan gotong royong dalam aktivitas kesehariannya, sebagaimana klaim dan anggapan kaum populis. Sebaliknya, yang diperlihatkan oleh Wida lewat buku ini ialah, aktivitas petani di pedesaan seperti di Desa Geger justru mengandung “[…..] eksploitasi yang dilakukan oleh kelompok sosial yang memiliki kuasa lebih besar” [hlm. 16].
Dalam buku ini, Wida memperlihatkan pembacaan terhadap “kelas” di kalangan petani di Desa Geger sebelum dan pasca pembangunan YIA. Dari riset yang dilakukannya, ditemukan “lokasi kelas” sebelum pembangunan YIA yang terdiri dari karakteristik kelas penguasa, karakteristik produsen komoditas skala kecil (PKK), dan karakteristik kelas pekerja. Dari masing-masing karakteristik kelas ini, dapat diklasifikasikan lagi ke dalam kelas-kelas yang berbeda-beda seturut dengan kepemilikan alat produksi dan relasi produksi.
Pertama, kelas penguasa adalah “mereka yang memiliki kemampuan mempekerjakan orang lain untuk mengerjakan lahan pertanian atau mereka yang memeras hasil dari hak kontrol tanah” [hlm. 36 – 37]. Kelas penguasa terdiri dari petani kapitalis, petani kapitalis birokrat, petani kapitalis yang berpendidikan tinggi serta pekerjaan profesional, dan tuan tanah.
Kedua, kelas PKK ialah “mereka yang memiliki karakteristik luas lahan cukup, cenderung mengelola pertanian dengan mengandalkan tenaga kerja keluarga, dan dapat menjual tenaga kerjanya atau mempekerjakan orang lain atas pilihan sendiri, bukan karena keterdesakan ekonomi [hlm. 40]. Menurut Muchtar Habibi (2023), sebagaimana dikutip Wida, kelas PKK ini mengalami “diferensiasi kelas, yang bisa dikategorikan ke dalam PKK subtansial, formal, klasik, dan aspiring” [hlm. 40].
Ketiga, kelas pekerja yakni “mereka yang tidak memiliki alat produksi dan menjual tenaga kerjanya sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya” [hlm. 42]. Sebagaimana kelas sebelumnya, kelas pekerja juga terdiferensiasi ke dalam beberapa kelas seperti, petani semi proletar, petani proletar, dan petani yang tak memiliki atau menguasai lahan pertanian atau yang disebut dalam buku ini sebagai “buruh sepenuhnya”.
Hadirnya pembangunan YIA di Desa Geger nyatanya menimbulkan beragam reaksi pro dan kontra. Bagi kelas penguasa, hadirnya pembangunan YIA di wilayahnya merupakan kesempatan yang dengannya mereka dapat memperoleh untung dengan melepaskan lahan untuk pembangunan YIA. Kelas penguasa, sebagaimana ditulis Wida, dapat memanfaatkan ‘ganti rugi lahan’ untuk membangun bisnis seperti kos-kosan atau mencari lahan pertanian di tempat lain.
Sementara, bagi kelas PKK, hadirnya pembangunan YIA tak serta-merta memberi mereka “berkat” seperti yang dialami oleh kelas penguasa. Bagi kelas PKK, yang terdiferensiasi ke dalam beberapa kategori kelas, pembangunan YIA di wilayah mereka ternyata membawa persoalan bagi kelangsungan hidup mereka.
Dengan luas lahan yang sangat terbatas, yang di mana lahan mereka juga dijadikan objek pembangunan YIA, ganti rugi atas lahan bisa memberi mereka ‘modal’ untuk tetap bekerja di sektor bertani, dengan tetap bekerja sebagai pekerja upahan, yang tentu mengubah lokasi kelas menjadi petani semi proletar. Tak seperti kelas penguasa yang cenderung tetap mempertahankan lokasi kelasnya, kelas PKK mengalami transformasi kelas yang berbeda-beda.
Sementara bagi petani kelas pekerja, kehadiran pembangunan YIA justru bisa mendorong mereka dalam kondisi proletarisasi. “Proletarisasi dapat diartikan sebagai pergeseran status seseorang dari pemberi kerja atau pekerja mandiri, menjadi buruh, yaitu seseorang yang menggantungkan pemasukan dari menjual tenaga kerjanya” [hlm. 74]. Berbeda dengan kelas sebelumnya, kelas pekerja makin rentan dieksploitasi dalam kerja upahan, karena tak memiliki alat produksi dan relasi produksi.
Tanggapan
Buku “Geger Gedhen di Pesisir Selatan Jawa” yang ditulis Wida, ini sangat penting dalam memotret kehidupan petani di pedesaan, yang mengalami dinamika kelas seiring dengan kehadiran pembangunan infrastruktur di wilayah mereka. Bahwa, pembangunan infrastruktur seperti halnya pembangunan YIA di Kulonprogo ternyata mengandung persoalan lebih lanjut terhadap kehidupan petani, terutama petani PKK dan kelas pekerja.
Saat ini kita dapat melihat di bawah pemerintahan Joko Widodo, berbagai pembangunan infrastruktur, yang membutuhkan lahan luas seperti jalan tol, waduk dan bendungan, begitu masif digencarkan. Pemerintah meyakini pembangunan infrastruktur ini, akan menciptakan “pemerataan pembangunan”, yang berarti akan mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan, yang dapat dinikmati oleh semua warga. Kemiskinan di pedesaan, menurut pemerintah, merupakan ekses dari minimnya pembangunan infrastruktur.
Nyatanya melalui buku ini, Wida memperlihatkan bahwa apa yang disebut sebagai “pemerataan pembangunan” ala pemerintah justru mengandung persoalan bagi kehidupan petani, yang sejak awal sudah terdiferensiasi ke dalam kelas-kelas yang membentuk relasi produksi di pedesaan. Kehadiran pembangunan justru tak “menyerap” semua kelas, alih-alih menguntungkan kelas tertentu. Sementara, kelas lain seperti kelas pekerja (petani proletar dan ‘buruh sepenuhnya’) makin terperosok ke dalam jebakan proletarianisasi, yang melahirkan kemiskinan di pedesaan.
Buku ini, menurut saya, memberi kita pemahaman tentang kondisi di pedesaan yang dipenuhi dengan berbagai persoalan laten, karena ditutupi atau tertutup oleh berbagai janji dan jargon pembangunan, yang nyatanya sangat kapitalistik. Anggapan kaum populis yang meletakan kehidupan petani di pedesaan yang homogen, berlandaskan gotong royong, dan harmonis ternyata menyimpan persoalan pelik. Melalui buku ini, Wida menyuguhkan bahwa di pedesaan, kehidupan petani ‘terdiferensiasi’ ke dalam kelas-kelas seturut dengan relasi produksi dan kepemilikan alat produksi.
Bahwa apa yang kita lihat sebagai kemiskinan di kalangan petani, tak melulu karena “minimnya infrastruktur” yang dapat mereka nikmati dalam menopang ekonomi rumah tangga. Tetapi, oleh akses atas lahan pertanian yang dapat mereka kelola dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga petani di pedesaan.
Informasi Buku
Judul : Geger Gedhen di Pesisir Selatan Jawa; Pembangunan Bandara dan Dinamika Kelas Agraria di Yogyakarta
Penulis : Wida Dhelweis Yustiarani
Penerbit : Independen dan Indopogress Institute for Research & Education [IISRE]
Tahun Terbit: 2024, cetakan pertama
Jumlah : vii + 91 halaman
ISBN : 978-623-96806-0-2
*Kawan-kawan dapat membaca artikel-artikel lain mengenai pembangunan infrastruktur, dan tulisan-tulisan lain Resensi Buku