Potret Model Bisnis Radio Swasta di Wilayah Bukan Perkotaan
Tantangan bagi profesional radio siaran terutama di daerah pinggiran yang tak terjangkau alokasi pembiayaan iklan nasional.
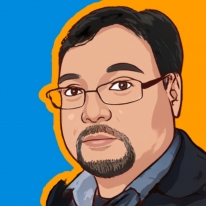
Mang Sawal
Praktisi komunikasi dan pembelajar pada Program Doktoral Unisba dengan fokus pada komunikasi sains. Aktif di berbagai kegiatan edukasi publik.
29 September 2022
BandungBergerak.id - Oh, you could study Shakespear and be quite elite. And you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh!
Petikan bait lagu berjudul Make ‘Em Laugh itu ditulis liriknya oleh Brown dan Freed, dinyanyikan Donald O’Connor di dalam sebuah film musikal berjudul Singin’ in The Rain yang diputar di bioskop pada tahun 1952. Film berdurasi 1 jam 43 menit itu termasuk dalam daftar film box office karena menghasilkan pendapatan sebesar USD 12,4 Juta, sementara biaya produksinya hanya USD 2,5 Juta.
Fokus cerita film Make ‘Em Laugh adalah kisah romantis antara seorang aktor dan seorang gadis penyanyi dengan setting waktu tahun 30-an ketika industri film bisu mendapat tantangan dari kemunculan teknologi baru yang disebut pita film bersuara. Teknologi baru itu mengubah seluruh industri film yang hanya membutuhkan aktor tampan atau cantik yang dapat bertingkah di depan kamera, menjadi talenta yang juga memiliki kemampuan untuk berdialog dan bersuara bagus. Sekaligus menghapus sejumlah pekerjaan yang ada, seperti pemain musik live di bioskop untuk mengiringi film bisu yang tengah diputar.
Begitulah, film Make ‘Em Laugh menyampaikan pesan moral sesuai dengan kepercayaan determinisme teknologi, yaitu bahwa pihak yang tidak mau menyesuaikan diri dan mengambil kesempatan pada kecenderungan baru, akan ditinggalkan. Lirik lagu di atas juga memberi pesan, jika ingin menghasilkan uang, jangan membuat yang hebat-hebat karena takkan laku, melainkan cukup yang menghibur, karena semua orang ingin tertawa.
Perubahan pada Teknologi Radio
Bagitulah dalam sejarah peradaban manusia, kemunculan teknologi baru kerap membunuh teknologi sebelumnya, meski tidak berlaku pada seluruhnya. Ambil contoh, saat ini tidak ada lagi yang menggunakan perangkat telepon engkol (putar) karena sistem kerja perangkatnya tidak lagi selaras dengan sistem baru. Tidak ada lagi mesin mobil yang dinyalakan dengan mengungkit (engkol) kipas mesinnya. Tidak ada lagi radio penerima yang memakai lampu tabung vakum sebagai penguat sinyal. Tapi sampai saat ini masih banyak yang menggunakan cangkul, sebuah teknologi sederhana yang tercatat setidaknya mulai digunakan manusia pada tahun 3500 Sebelum Masehi, seperti yang terungkap oleh ahli arkeologi di Situs Bubenec dekat Kastil Praha.
Selain cangkul, ada banyak teknologi yang cenderung tak lekang oleh waktu, misalnya, teknologi pemancaran radio. Teknologi yang dikembangkan oleh Guglielmo Marconi pada saat ia masih berusia 20 tahunan di akhir abad ke-18. Hingga melampaui millenium ke-2, teknologi pemancaran radio melalui gelombang spektrum elektromagnetik ini bahkan terus berkembang, dari analog menjadi digital. Dari sinyal pulsa menjadi kode biner. Awalnya teknologi pemancaran radio dikembangkan sebagai sarana berbagi informasi antara satu titik ke titik lain, sebagai sarana telegrafika. Namun tidak lama kemudian menjadi sarana komunikasi satu titik ke tak terhingga titik. Sering juga disebut sarana komunikasi massa.
Seperti ditengarai kaum determinis, kehadiran teknologi baru akan membawa dilema. Begitu pula kehadiran teknologi radio siaran disambut meriah oleh masyarakat sekaligus mendatangkan kekhawatiran pada pengguna teknologi sebelumnya, yaitu industri media massa cetak. Pada periode tahun 1930-an, dapat dikatakan terjadi perang dingin antara koran dan radio dalam menyiarkan berita serta pemuatan iklan (Simmon, 2016). Berkumpulnya anggota keluarga di sekitar perangkat penerima siaran radio pada masa awal perkembangan radio siaran, menciptakan nilai bisnis. Potensi yang langsung ditangkap banyak pebisnis (Patnode, 2011).
Dalam banyak literatur, radio siaran sejak awal sudah mengembangkan ragam model bisnis untuk menyokong operasi radio siaran. Di AS, sejak masa awal perkembangannya, banyak radio bekerja sama dengan perusahaan pembuat rekaman musik (saat itu masih berupa piringan hitam) untuk menyediakan materi-materi musik dengan barter penyebutan jasa pembuat rekaman. Prinsipnya, jika rekaman musik diputar, maka penyiar akan menyebut siapa perekamnya dan di mana pendengar dapat membelinya. Model ini tidak banyak menghasilkan uang karena sifat bisnisnya barter, namun sanggup mengantar penyiaran radio dan produksi musik di AS berada pada masa keemasan yang disebut dengan Radio Days.
Model Bisnis Radio
Di AS-lah, radio siaran pertama kali menjual jam siaran untuk diisi iklan berbayar. Alkisah pada tahun 1922 sebuah radio siaran bernama WEAF di New York menjual jam siarannya untuk menyampaikan pesan apa saja dari siapa saja berdasarkan hitungan menit. Model bisnis ini terinspirasi oleh model bisnis telekomunikasi perusahaan jasa telepon AS, AT&T, yang merupakan pendiri radio WEAF. Perusahaan telepon menjual jasa sambungan telepon dan mendapat bayaran berdasarkan hitungan waktu pemakaian jasa sambungan telepon. Bentuk iklan seperti ini disebut dengan iklan spot.
Model bisnis penyampaian pesan kepada siapa pun dari siapa pun pernah pula menjadi salah satu jagoan radio siaran swasta di Indonesia pada awal tahun 70-an. Model bisnis ini disebut kartu atensi atau kartu pilihan pendengar. Pengelola radio siaran mencetak lembaran kartu atensi yang dapat dibeli oleh pendengar sebanyak yang ia kehendaki, untuk dipakai sebagai alat permintaan lagu dan pengirman pesan kepada siapa lagu itu dipersembahkan, kemudian kartu itu akan dibacakan oleh penyiar pujaan pada acara favorit masing-masing. Model bisnis semacam itu tak bisa lagi dipraktikkan begitu sambungan telepon mulai menyebar ke seluruh rumah di Indonesia, karena tidak ada cara yang efisien untuk menagih dibanding kartu atensi.
Bedanya dengan Indonesia, di AS, pada awal masa perkembangan radio, kartu atensi itu dipakai oleh perusahaan untuk memastikan para penyiar menyebut nama-nama merek produk mereka. Dalam buku teks produksi siaran model bisnis ini disebut iklan ad-libitum.
Model bisnis lain yang juga berkembang di awal masa perkembangan radio di AS antara tahun 1930-1940an adalah iklan yang direkam dan dikemas seperti sebuah drama singkat. Berbeda dengan kartu atensi yang bentuk penyiaran iklannya seperti pembacaan pengumuman, iklan rekaman bisa lebih menarik karena ada efek suara dan dialog. Model bisnis ini juga berkembang di Indonesia pada saat yang sama dengan kartu atensi pada tahun 70-an. Pada masa itu, pengiklan menghubungi langsung pengelola radio dan mendiskusikan isi iklan serta bentuk akhir produksi iklan. Model bisnis ini dinilai lebih efektif terutama karena dapat memuat pesan testimonial yang dinilai lebih persuasif (Martin, 2014).
Ada model bisnis lain yang sempat berkembang sebentar pada masa awal perkembangan radio siaran di AS pada tahun 30-an namun tidak berlangsung lama, yaitu radio siaran sebagai etalase bisnis pemilik radio. Pada saat itu sejumlah radio didirikan oleh pengelola toko besar dan digunakan sebagai sarana untuk menyiarkan ketersediaan barang serta harga di toko sang pemilik radio. Dalam buku teks produksi siaran zaman sekarang, ini disebut sebagai iklan infomercial atau advertorial. Model ini pada waktu itu, di AS, tidak bertahan lama seiring berbaliknya bentuk bisnis antara perusahaan pembuat rekaman musik dan radio siaran yang tidak lagi barter, melainkan perjanjian royalti atas karya cipta musik yang disiarkan. Perubahan bentuk bisnis dengan pembuat rekaman musik itu menyebabkan naiknya biaya produksi siaran sehingga pemilik radio yang juga pemilik toko besar, melepaskan bisnis radio karena biaya operasi menjadi beban toko.
Model bisnis seperti ini masih dapat ditemukan sampai saat ini di sejumlah lembaga penyiaran lokal baik televisi maupun radio di Indonesia. Sejumlah pemilik lembaga penyiaran yang juga memiliki bisnis lain, menjadikan lembaga penyiarannya sebagai outlet bisnis lain itu, sehingga biaya operasional radio dapat ditanggung sebagai biaya promosi. Bahkan ada pula sejumlah pemilik radio yang melakukan “kerjasama” manajemen dengan pemilik produk tertentu (kebanyakan jasa pelayanan kesehatan/pengobatan tradisional) untuk menyiarkan produk itu secara eksklusif dan menerima biaya operasional bulanan dari pemilik produk.
Baca Juga: Anak Keluarga Artis Rentan Jadi Korban Perundungan
Pagebluk Covid-19 dan Tugas Jurnalistik (1)
Pagebluk Covid-19 dan Tugas Jurnalistik (2)
Model Bisnis Radio Wilayah Pinggiran
Kembali ke AS. Seiring waktu, konsolidasi perusahaan radio siaran di AS mulai terjadi. Konvergensi kepemilikan ikut mengubah model bisnisnya. Sejumlah radio mulai berjaringan, menyediakan alokasi waktu untuk siaran bersama (relay) berikut tempat pemasangan iklannya. Dengan siaran bersama, jangkauan siaran menjadi lebih luas dan karenanya nilai jual penempatan iklan meningkat pula. Bagi pengelola radio jaringan, ongkos produksi dapat ditekan, pendapatan meningkat, nilai bisnis bertambah. Bagi pemasang iklan, radio jaringan meningkatkan terpaan dan berarti juga memperkuat kesadaran merek untuk mempermudah pemasaran.
Ketika kajian opini publik dan public relations berkembang tahun 60-an di AS, maka tumbuh pula bisnis pencitraan. Dalam pencitraan diperlukan tindakan-tindakan spesifik terhadap sasaran yang spesifik. Radio siaran kemudian mulai menyesuaikan diri dengan kecederungan itu melalui fragmentasi khalayaknya. Format siaran zaman doeloe yang all-segment mulai berkembang menjadi puluhan format spesifik. Ada format yang disusun berdasarkan identitas etnik, jenjang usia, selera musik, status sosial, hobby, gender, dst. Masing-masing dengan kebiasaan (habit) dan rentang waktu (time span dan time spent) dengar berbeda-beda. Model bisnis ini bertumpu pada pengelompokan berdasar identitas pasar yang spesifik dan diperkuat dengan jangkauan dan sebaran (rating dan share) dan pasar.
Hingga saat ini, model bisnis penyiaran radio yang mengaitkan citra merek pemasang iklan dengan identitas pasar pendengar, menjadi model dominan di seluruh dunia. Pengelola radio siaran mengumpulkan data tentang pendengarnya dan menawarkan keterkaitan identitas pasar pendengarnya dengan kedudukan (positioning) produk dari calon pemasang iklan dalam sebuah proposal program siaran yang spesifik.
Secara khusus, di Indonesia saat ini, karena penyedia data spesifik khalayak media hanya satu, yaitu Nielsen, dan tidak terawasi dengan baik seperti di sejumlah negara maju, maka untuk meningkatkan minat pemasang iklan, proposal program siaran juga diikuti dengan proposal penyelenggaraan kegiatan penjualan (off air event organizing). Model bisnis radio siaran di Indonesia seperti ini makin dominan karena tidak adanya data spesifik tentang pendengar dari radio-radio siaran lokal di seluruh Indonesia.
Nasib yang sama juga dialami TV lokal. Ketiadaan data itu menjatuhkan nilai tawar jam siaran radio lokal dibanding TV jaringan. Sejumlah radio siaran di Indonesia mengembangkan konsep bertahan hidup dengan istilah Five-O – merujuk sebuah film detektif yang populer pada tahun 1970-an di Indonesia, Hawaii Five-O. Konsep itu merupakan kependekan dari On-Air, Online, OB-van, Off-Air, On Data (Nursyawal, 2016). Pengelola radio tidak hanya menawarkan jasa penyiaran iklan spot, tetapi juga branding melalui outdoor broadcast van yang berkeliling kota dan melakukan siaran di tengah keramaian, juga memberi bonus penempatan iklan di website atau platform digital lain, sekaligus dalam satu paket yang sama adalah pelaksanaan sebuah event seperti panggung musik atau event lain di mana pemasang iklan dapat melakukan branding atau penjualan di lokasi. Tentunya model bisnis ini dengan mudah dilaksanakan di daerah perkotaan di mana kerumunan massa dengan mudah tumbuh.
Untuk wilayah pinggiran atau bahkan perdesaan yang jauh dari alokasi belanja iklan nasional, maka model bisnis kolaborasi sosial menjadi referensi untuk bertahan hidup. Model bisnis ini masih menggunakan prinsip lama dari medium radio, yaitu sifat medium yang personal. Program radio disusun sedemikian rupa melulu untuk menjawab kebutuhan khalayak sasaran, dengan terlebih dahulu melakukan riset sederhana tentang identitas sosial khalayak sasaran. Berbeda dengan konsep identitas pasar yang membagi kategori segmentasi berdasar status sosial ekonomi dan gender, pengelompokan identitas sosial merupakan pengelompokan khalayak berdasarkan kecenderungan nilai-nilai hidup dan nilai sosial yang dianut khalayak sasaran. Model ini membutuhkan keterampilan sosial pengelola radio untuk menangkap nilai-nilai hidup kelompok pendengarnya dengan banyak terlibat dalam aktifitas sosial kelompok pendengar (Nursyawal, 2016). Melalui cara ini, pengelola radio dapat mengetahui agenda sosial target pendengarnya dan menawarkan fasilitas publikasi dan bantuan penyusunan acara kegiatan masyarakat, bahkan kanal untuk memperoleh bantuan dana untuk menyokong kegiatan masyarakat itu. Semacam jasa event organizing kepada kelompok masyarakat.
Pada saat yang sama, pengelola radio mengumpulkan sejumlah produsen produk konsumen yang “sejalan” dengan kegiatan masyarakat tadi, lalu pada saat kegiatan berlangsung, pengelola radio menjadi pengelola konsinyasi penjualan produk di lokasi kegiatan. Biaya produksi relatif minimal karena yang dibawa untuk menyiarkan kegiatan itu hanyalah perangkat pemancar radio digital yang tidak lebih besar dari sebuah ransel, sebuah mixer, dan kabel untuk taping dari sistem pengatur suara utama. Seluruh kegiatan tentu sudah dibayar oleh masyarakat sendiri atau sponsor kegiatan. Bentuk kegiatannya mengundang massa dan berlangsung di lapangan terbuka. Selain profit hasil konsinyasi, lembaga penyiaran mendapat benefit popularitas di kalangan pendengar karena mereka merasa kegiatan-kegiatan mereka selalu mendapat saluran publikasi.
Model lain yang menggunakan kebutuhan masyarakat untuk mengakses media penyiaran sebagai sarana produksi dan pembiayaan adalah penyiaran komunitas. Model ini digunakan oleh radio publik lokal yang merupakan transformasi radio siaran pemerintah daerah, yang sebelum berubah mendapat anggaran penuh dari negara. Setelah menjadi radio publik lokal, anggaran tidak lagi ditanggung sepenuhnya, maka radio-radio ini mulai mencari cara agar biaya produksi tertanggulangi atau ditekan. Caranya dengan mendekati komunitas-komunitas yang ada di masyarakat dan mengajak mereka menjadi produsen isi siaran. Model ini biasa dipraktikkan oleh radio komunitas yang pengelolaannya dilaksanakan oleh komunitas itu sendiri. Bedanya dengan radio publik lokal, radio komunitas tidak boleh berbisnis.
Masih banyak variasi model bisnis radio yang merupakan kelanjutan dari fase awal sejarah berkembangnya radio hingga saat ini. Namun model bisnis apa pun ternyata kembali lagi pada inti utama radio siaran yaitu isi siarannya. Riset dan pengembangan isi siaran perlu dilakukan untuk menyediakan lingkungan bisnis yang kondusif. Tantangan terberat saat ini bagi para profesional radio siaran, terutama di daerah pinggiran yang tak terjangkau alokasi pembiayaan iklan nasional, adalah mengajak kembali masyarakat untuk mendengar radio, mempertahankan mereka yang sudah mendengarkan, dengan terus mengubah gaya siaran dan isi siaran yang menarik. Baru kemudian membangun model bisnisnya yang tidak menutup kemungkinan merupakan modifikasi model lama seperti kartu atensi, yang sekarang disebut dengan istilah keren crowdfunding model subscription.


