Ketika Alam Enggan Bersahabat dengan Kita, Saatnya Mengingat Percakapan yang Terlupakan
Bencana alam hari ini adalah kegagalan kolektif kita untuk mendengar, memahami, dan menjawab informasi dari karakteristik biofisik dari ruang hidup yang kita huni.
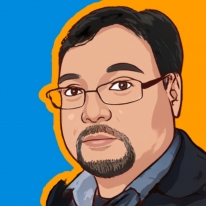
Mang Sawal
Praktisi komunikasi dan pembelajar pada Program Doktoral Unisba dengan fokus pada komunikasi sains. Aktif di berbagai kegiatan edukasi publik.
1 Desember 2025
BandungBergerak.id – Sudah dua dekade saya bekerja sebagai tenaga ahli lepas bidang komunikasi publik untuk sebuah perusahaan konsultan perencanaan wilayah. Selama itu pula saya menyaksikan Indonesia kehilangan ribuan nyawa dan ratusan triliun rupiah karena bencana yang sebenarnya bisa dicegah. Dalam dua bulan terakhir saja, dalam musim hujan di garis khatulistiwa, antara Oktober dan November 2025, Badan Nasional Pengendalian Bencana mencatat lebih dari 150 kejadian besar yang melanda. Banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, erupsi gunung, dan di Jakarta, kota yang tak pernah berhenti membangun janji dan menciptakan tanah timbul di pesisir pantai, terus tenggelam dalam kiriman banjir.
Di era media sosial ini, semua orang tampaknya tahu penyebab semua bencana ini. Curah hujan ekstrem, La Nina, efek rumah kaca, perubahan iklim, pemanasan global, adalah istilah-istilah yang akrab di telinga kita. Namun sedikit yang lantang menyebut sesuatu yang saya amati dari lapangan selama dua dekade terakhir: ada konflik mendasar antara logika kapital yang mengejar profit dari tanah dengan daya dukung ekologis wilayah kita. Ruang yang kita huni sudah enggan bersahabat dengan kita karena ada ketidaksesuaian sistematis antara penggunaan lahan dengan karakteristik biofisiknya, ketidaksesuaian yang lahir dari konflik kepentingan ekonomi-politik.
Saya ingat betul ketika pertama kali terlibat dalam tim penyusunan Grand Scenario Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Penataan Ruang (GSPKM-PR) Tahun 2004. Waktu itu kami masih optimis, dengan perencanaan yang baik dan partisipasi masyarakat yang kuat, Indonesia bisa mencegah bencana. Dua puluh tahun kemudian, saya berdiri di lokasi yang sama, entah itu di bantaran Ciliwung saat mendampingi masyarakat Daerah Aliran Sungai Ciliwung-Cisadane atau DAS Citarum pada 2018, atau di kampung-kampung terpencil di tengah laut di Kawasan Timur Indonesia saat melakukan kajian modal sosial pada 2021, saya melihat pola yang masih sama. Kita membangun rumah beton di lereng curam yang seharusnya menangkap air dan menahan tanah. Kita mengubah hutan resapan menjadi perumahan dengan gerbang megah dan nama yang berbau Eropa. Kita mendirikan permukiman atau kawasan bisnis di daerah yang sudah jadi langganan banjir sejak zaman Belanda.
Yang menarik, banyak dari pelanggaran ini bukan karena ketidaktahuan. Developer besar memahami peta risiko. Birokrat tahu wilayah mana yang seharusnya protected area. Masyarakat pun sadar bahwa bantaran sungai berbahaya. Tapi ada insentif ekonomi yang lebih kuat: land rent yang tinggi di area strategis, korupsi dalam perizinan, spekulasi lahan, dan bagi masyarakat miskin, tidak ada alternatif perumahan yang terjangkau di lokasi aman. Inilah yang John Friedmann (1987) sebut sebagai konflik antara exchange value dan use value dalam perencanaan wilayah.
Baca Juga: Legend of Aang, Museum Alexandria, dan Google Cendikia
Kematian Affan Kurniawan dan Runtuhnya Kepercayaan Publik pada Institusi Polisi
AI dan Renungan tentang Kemanusiaan
Mengembalikan Percakapan dengan Ruang
Dari pengalaman saya mendampingi puluhan kelompok masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, saya menemukan masalahnya bukan hanya teknis, bukan cuma soal saluran air yang tersumbat atau bendungan yang jebol. Masalahnya adalah apa yang dalam literatur perencanaan komunikatif disebut sebagai communicative breakdown dalam environmental governance. Ketika saya duduk bersama kelompok emak-emak di Kampung Pulo yang rumahnya sudah kebanjiran puluhan kali, atau berdiskusi dengan tetua adat di Papua Barat yang tanah ulayatnya terancam proyek besar, saya mendengar keluhan yang sama: "Kami tidak lagi sanggup membaca tanda-tanda alam seperti nenek moyang kami dulu."
Inilah yang saya sebut, dan yang kami rumuskan dalam GSPKM-PR 2004, sebagai krisis komunikasi spasial: kegagalan kolektif kita untuk mendengar, memahami, dan menjawab informasi dari karakteristik biofisik ruang yang kita huni. Konsep ini saya bangun dari perpaduan teori communicative planning (Patsy Healey, 1993), risk communication (Paul Slovic, 2000), dan environmental communication (Robert Cox, 2003). Komunikasi spasial adalah proses dialogis multi-arah di mana berbagai aktor, masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan sistem ekologis itu sendiri, bernegosiasi tentang penggunaan dan makna ruang.
Di kota-kota besar, komunikasi spasial ini sudah putus total. Di Jakarta, empat puluh persen wilayahnya sejak dulu diketahui rawan banjir, tapi izin bangunan tetap dikeluarkan dan pengeboran air tanah dalam terus berjalan lancar. Ini bukan masalah komunikasi dalam arti penyampaian informasi, peta risiko tersedia, studi AMDAL ada, tapi political will untuk menegakkan tidak ada karena tekanan elite ekonomi yang mengontrol land development. Di Papua Barat atau Maluku Utara, masyarakat adat tahu persis mana tanah yang boleh dibuka dan mana yang harus tetap tertutup, tapi suara mereka kalah oleh proyek strategis nasional. Ini adalah masalah power asymmetry dalam spatial discourse.
Komunikasi bukan hanya soal kata-kata yang keluar dari mulut manusia. Selama bertahun-tahun bekerja di lapangan, saya belajar bahwa ruang juga menyampaikan informasi lewat karakteristik biofisiknya: bentang alam dan vegetasi yang beragam, alur sungai yang berkelok-kelok mencari jalan, kerimbunan bambu di lereng yang menahan tanah, aktivitas vulkanik yang menunjukkan sistem geologi masih aktif. Dalam kerangka environmental communication, ini adalah environmental signals yang harus kita baca dan respons dengan tepat.
Di dalam GSPKM-PR 2004, kami merumuskan empat tahap keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang yang mereka huni, yang sejalan dengan Transtheoretical Model of Behavior Change (Prochaska & DiClemente, 1983). Tahap pertama adalah sadar dan mengenali (precontemplation-contemplation), yaitu kondisi masyarakat yang mulai sadar ada pesan dari karakteristik ruang yang mereka tinggali, misalnya ketika banjir kecil mulai rutin datang setiap tahun. Tahap kedua adalah terdorong dan meminati (preparation), ketika masyarakat mulai mencari tahu mengapa banjir itu terjadi, mencari tahu keberadaan peta rawan bencana, ikut sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana. Tahap ketiga adalah yakin dan menerima (action), ketika masyarakat akhirnya menerima kenyataan bahwa ruang yang mereka huni yaitu bantaran sungai memang bukan lokasi hunian yang tepat menurut prinsip planologi, dan mulai mencari solusi bersama. Tahap keempat adalah melakukan dan membentuk konsensus (maintenance), ketika individu masyarakat berperilaku baru, seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian perilaku itu diikuti lebih banyak orang sehingga menjadi norma sosial yang baru.
Namun saya harus jujur: dua puluh tahun setelah dokumen itu kami susun dan serahkan kepada pemerintah, mayoritas masyarakat Indonesia masih terjebak di tahap pertama, atau bahkan belum masuk tahap pertama sama sekali. Dan ini bukan semata-mata karena kurangnya awareness campaign. Bahkan ketika masyarakat sudah mencapai tahap keempat, mereka tetap tidak bisa pindah karena tidak ada land banking pemerintah untuk relokasi, tidak ada subsidi perumahan di zona aman, tidak ada penegakan hukum terhadap developer yang membangun ilegal.
Kajian modal sosial memakai perspektif Pierre Bourdieu (dalam Gittell & Vidal, 1998) yang kami lakukan di Kawasan Timur Indonesia pada 2021, memberikan pencerahan yang mengejutkan. Saya menemukan bahwa bonding capital di sana, yaitu ikatan keluarga dan suku, sangat kuat. Masyarakat satu suku sangat cepat bergotong royong saat bencana terjadi. Namun bridging capital, hubungan antarkelompok suku, hanya sedang-sedang saja, mengakibatkan sulitnya koordinasi antarkampung atau antarsuku ketika diperlukan aksi kolektif yang lebih besar seperti illegal fishing atau aktivitas tambang mineral.
Yang paling mengkhawatirkan adalah linking capital, hubungan dengan lembaga formal negara, yang sangat lemah. Berkali-kali saya mendengar celoteh nelayan di Indonesia Timur: "Peta fishing ground itu untuk siapa? Kami hanya percaya pada petunjuk bintang dan air laut," atau, "Untuk apa sertifikasi ikan tuna kami? Karena toh lautnya hanya dikuasai 2 orang itu. Kami hanya dapat sisa-sisa." Akibatnya, meskipun teknologi yang dikelola sebuah lembaga negara sudah sangat canggih, informasi risiko tidak sampai ke masyarakat karena tidak ada trusted intermediary. Ini adalah kegagalan risk communication klasik: pesan yang akurat secara teknis tapi gagal karena kurangnya source credibility.
Indonesia sebenarnya punya kerangka regulasi yang lengkap: UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga Perpres No. 87 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional. Semua regulasi itu memberi ruang partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang, serta sanksi tegas bagi pelanggarnya.
Tapi dari lapangan, saya melihat implementasinya sangat lemah. Pemerintah berbicara dengan bahasa teknokratis yang penuh jargon seperti dalam tulisan ini. Masyarakat bersuara dengan bahasa pengalaman sehari-hari. Lebih dari itu, ada structural silence, hal-hal yang tidak pernah dibicarakan dalam forum resmi: siapa yang mendapat keuntungan dari izin yang melanggar RTRW? Berapa besar suap untuk mengubah zona konservasi menjadi zona komersial? Mengapa perusahaan tambang bisa beroperasi di kawasan lindung?
Pembelajaran dari Lapangan, Membangun Bahasa Bersama
Dari semua pengalaman saya mendampingi masyarakat, saya menemukan bahwa solusi pertama yang paling efektif adalah membangun Forum Kelompok Masyarakat Peduli Tata Ruang di setiap desa atau kelurahan. Ini bukan ide teoretis dari meja kerja, tapi lahir dari pengalaman saya mendampingi kelompok masyarakat di Daerah Aliran Sungai Citarum pada 2005, 2010, 2018 dan Ciliwung-Cisadane 2020. Saya melihat bagaimana forum ini, yang beranggotakan hanya 15 hingga 30 orang yang tinggal di satu lokasi yang sama, bisa mengurangi dampak bencana, bukan menghilangkan risiko sepenuhnya, tapi membuat masyarakat lebih adaptif dan resilient.
Forum ini bukan organisasi baru yang birokratis dengan struktur kepengurusan yang rumit. Mereka bertemu rutin seminggu atau sebulan sekali untuk melakukan tiga hal sederhana namun krusial. Pertama, mereka membaca peta rawan bencana bersama-sama dengan cara mereka sendiri, dengan mengenali kampung mereka di peta, menunjuk koordinat rumah sendiri, mencatat kejadian banjir yang telah lalu, dan memahami mengapa itu terjadi. Kedua, mereka mengawasi pemanfaatan ruang di lingkungan mereka sendiri. Ketika ada yang membangun rumah terlalu dekat dengan sungai, mereka foto dan melakukan pengendalian melalui dialog antarwarga. Ketiga, mereka menjadi utusan warga saat ada proyek besar masuk ke wilayah mereka.
Namun saya harus mengakui keterbatasan pendekatan ini. Saya ingat betul pengalaman di Kabupaten Bekasi pada 2005, ketika kelompok masyarakat yang kami fasilitasi menolak pembangunan banjir kanal yang mereka nilai merugikan kawasan permukiman, pertanian dan nelayan lokal. Ini menimbulkan dilema planologi klasik: bagaimana ketika kepentingan lokal bertentangan dengan kebutuhan regional? Banjir kanal mungkin merugikan Bekasi tapi menguntungkan Jakarta. Ini adalah trade-off yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi yang lebih baik, tapi butuh mekanisme compensation dan benefit sharing yang adil.
Pembelajaran lain yang saya temukan efektif, terutama dari kajian di Kawasan Timur Indonesia, yaitu menggunakan modal sosial sebagai penerjemah. Di Papua Barat, Maluku, NTT, dan banyak tempat lain, otoritas adat jauh lebih dipercaya daripada camat atau bahkan bupati. Kepala suku, tetua adat, mama-mama di pasar, mereka adalah orang-orang yang suaranya didengar. Caranya: peta adat yang berisi wilayah marga, hutan larangan, atau sasi laut dalam adat di Maluku, saya overlay dengan peta RTRW resmi dari pemerintah. Hasilnya adalah peta bersama yang diakui oleh kedua pihak, peta yang tidak hanya berisi garis-garis administratif, tapi juga cerita, sejarah, dan kearifan lokal.
Tapi saya juga harus kritis: tidak semua kearifan lokal kompatibel dengan realitas kontemporer. Sistem tradisional “sasi” dirancang untuk populasi yang jauh lebih kecil dengan teknologi penangkapan ikan sederhana. Ketika menghadapi kapal pukat modern dan permintaan pasar global, sistem tradisional ini tidak selalu cukup. Yang kita butuhkan bukan romantisasi kearifan lokal, tapi hybrid governance yang menggabungkan pengetahuan lokal dengan sains modern dan instrumen planologi kontemporer seperti marine spatial planning atau payments for ecosystem services.
Solusi lain yang saya yakini perlu, meski dengan kesadaran penuh bahwa ini bukan silver bullet, adalah strategi komunikasi publik yang lebih efektif. Selama dua puluh tahun, saya sudah melihat terlalu banyak iklan layanan masyarakat yang kaku dengan narasi "Jangan Buang Sampah Sembarangan" yang diucapkan dengan nada menggurui. Dalam paradigma risk communication, kita tahu bahwa message exposure tidak otomatis mengubah perilaku. Tapi jika dikombinasikan dengan perubahan struktural, misalnya, penyediaan tempat sampah yang memadai, sistem pengangkutan yang reliable, sanksi sosial yang kuat, maka komunikasi publik bisa menjadi enabler perubahan.
Saya berimajinasi adanya serial pendek bergaya dokumenter di platform digital berjudul "Tragedi Bengawan Solo" yang diceritakan dari sudut pandang korban selamat, dari sudut pandang petugas SAR yang mengevakuasi jenazah, dari sudut pandang jurnalis investigasi yang membongkar korupsi perizinan yang menyebabkan kawasan resapan berubah jadi mal. Ini bukan sekadar emotional appeal, tapi juga membongkar political economy di balik bencana. Pendekatan yang lebih populer tinimbang dokumenter Sexy Killer.
Bayangkan pula aplikasi "Lapor" yang terhubung ke Satgas Penataan Ruang dengan mekanisme transparan: ketika warga memotret bangunan ilegal, laporan itu langsung masuk ke sistem, diverifikasi faktual dalam waktu 1x24 jam, ditindaklanjuti dalam 7 hari, dan hasilnya dipublikasi. Teknologinya ada. Yang kurang adalah political will untuk benar-benar menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Mengubah Struktur, Bukan Hanya Wacana
Solusi yang saya pelajari dari pengalaman pahit di lapangan adalah mengubah birokrasi menjadi fasilitator, bukan penguasa ruang. Terlalu sering saya melihat pemrakarsa proyek, entah itu developer swasta, BUMN, atau bahkan pemerintah sendiri, datang dengan excavator dan keputusan yang sudah final. Masyarakat hanya diberitahu, bukan diajak bicara. Dasar kuat untuk mengaku sebagai korban rezim. Saya mengusulkan Dialog Spasial wajib berkali-kali dengan masyarakat sebelum proyek dimulai. Bukan dialog formalitas di hotel berbintang dengan undangan terbatas, tapi dialog sungguhan di balai desa, di lapang terbuka, dengan bahasa yang dipahami warga, dengan kesempatan luas untuk bertanya dan bahkan menolak tanpa rasa takut.
Tentu dialog saja tidak cukup. Harus ada reformasi struktural:
Pertama, reform insentif ekonomi melalui instrumen planologi modern seperti transferable development rights (TDR). Developer yang ingin membangun di zona padat bisa membeli hak pembangunan dari pemilik tanah di zona konservasi yang setuju untuk tidak membangun. Dengan begitu, ada kompensasi ekonomi bagi yang menjaga lingkungan.
Kedua, land banking pemerintah untuk relokasi. Jangan suruh masyarakat pindah dari bantaran sungai kalau pemerintah tidak menyediakan alternatif perumahan yang layak dan terjangkau di lokasi aman.
Ketiga, transparansi penuh dalam perizinan tata ruang. Semua proses AMDAL, izin lokasi, perubahan RTRW harus bisa diakses publik secara real-time melalui platform digital. Ini mengurangi ruang untuk korupsi.
Keempat, penegakan hukum yang konsisten. Tidak ada gunanya punya regulasi bagus kalau tidak ditegakkan. Perlu political will dari kepala daerah untuk menertibkan bangunan ilegal, bahkan jika itu milik orang kuat atau developer besar.
Bencana alam tidak akan pernah hilang dari Indonesia. Ini adalah takdir geografis kita. Gunung berapi akan terus meletus karena kita hidup di Ring of Fire. Lempeng tektonik akan terus bergeser. Hujan akan semakin deras dan tidak terduga karena perubahan iklim. Tapi dari semua pengalaman saya, saya belajar satu hal penting: kita punya pilihan dalam merespons semua ini.
Komunikasi spasial adalah salah satu elemen penting, meski bukan satu-satunya. Bukan teknologi mahal yang hanya bisa dibeli negara kaya. Bukan bendungan raksasa yang butuh triliunan rupiah. Tapi juga bukan sekadar "kemauan untuk mendengar". Yang kita butuhkan adalah transformasi struktural dalam environmental governance: reform ekonomi-politik tata ruang, penegakan hukum yang konsisten, redistribusi akses terhadap lahan aman, dan demokratisasi proses perencanaan.
Saya tidak naif. Saya tahu bahwa kadang-kadang warga kota tetap membuang sampah ke kali meski sudah paham konsekuensinya, karena tidak ada sistem pengangkutan sampah yang reliable. Saya tahu developer tetap berani membangun di lahan resapan air meski masyarakat bisa membaca peta bencana, karena profit margin-nya terlalu menggiurkan dan risiko hukumnya minimal. Saya tahu masyarakat tetap tinggal di bantaran sungai meski tahu berbahaya, karena sewa rumah di tempat aman jauh di atas kemampuan ekonomi mereka.
Bayangkan ketika developer tidak lagi berani membangun di lahan resapan air bukan karena kesadaran moral, tapi karena sanksi hukumnya berat dan pasti. Bayangkan ketika masyarakat tidak perlu tinggal di bantaran sungai karena ada program perumahan bersubsidi di zona aman. Bayangkan ketika pejabat tidak berani mengeluarkan izin yang melanggar RTRW karena ada mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Ini bukan utopia. Ini adalah hasil dari reformasi struktural yang didukung oleh komunikasi publik yang efektif.
Perjalanan untuk mengembalikan percakapan dengan ruang memang panjang dan tidak mudah. Kadang saya merasa putus asa ketika melihat pekerjaan yang sudah saya dampingi bertahun-tahun tiba-tiba dihancurkan oleh satu keputusan politik. Kadang saya menangis dalam perjalanan pulang ketika forum yang sudah terbentuk, bubar karena tokoh kuncinya meninggal atau pindah kota. Tapi kemudian saya ingat wajah seorang nelayan yang bangga karena akhirnya punya kuasa atas wilayah lautnya, bukan karena dia menang melawan negara, tapi karena ada co-management scheme yang mengakui hak adat sekaligus kepentingan konservasi.
Penutup
Mari kita mengingat sebait lagu Ebiet G. Ade yang menggugah:
Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita
Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa
Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita
Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang
Mari mulai bercakap-cakap kembali, dengan kesadaran bahwa percakapan tanpa perubahan struktur hanya akan menjadi omon-omon. Mari kita dengarkan informasi dari karakteristik biofisik ruang, bersamaan kita ubah sistem insentif ekonomi dan politik yang membuat kita terus merusak. Saya masih percaya bahwa Indonesia bisa berubah. Bukan karena optimisme naif, tapi karena saya melihat bukti-bukti kecil di lapangan: forum warga yang bertahan, pejabat yang berani menolak suap, pengusaha yang memilih investasi hijau dengan cuan kecil.
Pada akhirnya, komunikasi spasial bukan hanya soal teknologi atau anggaran, tapi soal keadilan spasial: siapa yang punya akses ke lahan aman, siapa yang harus menanggung risiko bencana, siapa yang untung dari eksploitasi ruang. Ini soal kemauan politik kita untuk mengubah struktur kekuasaan yang timpang. Wallahu a'lam bishawab.
***
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB


