AI dan Renungan tentang Kemanusiaan
Kecerdasan buatan (AI) tak pernah benar-benar menyentuh esensi kemanusiaan. AI yang lahir dari data dan algoritma adalah alat yang menakjubkan sekaligus menyesatkan.
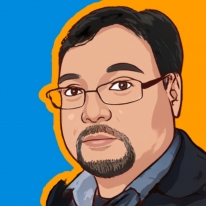
Mang Sawal
Praktisi komunikasi dan pembelajar pada Program Doktoral Unisba dengan fokus pada komunikasi sains. Aktif di berbagai kegiatan edukasi publik.
15 September 2025
BandungBergerak.id – Di tengah gempita perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, Agustus 2025 lalu, saya duduk bersama sekian banyak juri lain dalam sebuah lomba seni budaya antarpelajar SMA tingkat provinsi, sebuah panggung di mana kreativitas manusia seharusnya bersinar. Namun, di antara naskah-naskah berita, sastra, desain visual, dan komposisi musik yang mengalir, berkelebat bayang-bayang tak dinyana: jejak kecerdasan buatan (AI). Karya-karya kampiun dari kota dan kabupaten se-Provinsi Jawa Barat itu, bagai guratan kuas di kanvas digital yang sekilas tampak memesona, tapi dari sebagiannya tercium aroma algoritma, bukan produk sintesa pergulatan jiwa manusia. Ketika para juri menggali lebih dalam melalui wawancara virtual dengan peserta lomba, kebenaran itu terungkap: ia tak mampu menjelaskan denyut kreatif di balik ciptaannya. Fakta yang menyayat hati, meski masih ada penyejuk hati yang hadir menemani para juri yang menilai dan berkumpul di tengah dinginnya udara Lembang Kabupaten Bandung Barat, yaitu gerak nyanyian, tarian, dan teater monolog masih keluar dari napas murni manusia; pada saat beberapa karya naskah digital terperangkap di dalam kakunya coding mesin komputasi.
Saya berikan contoh bagaimana AI dapat hadir dengan dingin dalam sebuah puisi aktual yang sekilas tampak hangat hasil tangan manusia.
Di bawah langit Jakarta yang kelabu
seorang lelaki berjaket hijau melayani orderan
di antara teriakan dan gas air mata
Ia bukan orator, bukan pemimpin barisan
hanya roda dua dan harapan yang ia genggam
malam itu, di jalan itu, adalah jalan takdirnya
Rantis melaju, tak kenal wajah
tak kenal jerit, tak kenal welas
Melindas tubuhnya, dan sejarah mencatatnya dalam angka
Di gedung megah tempat wakil rakyat bersidang
gaya hidup mewah tak terguncang
menepikan jerit rakyat yang tertindih di aspal jalan
Affan Kurniawan,
namanya bergema di mata para mitra, di dada para warga negara
yang tak lagi percaya pada kata-kata yang sunyi dari kepedulian.
Puisi ini hanya perlu beberapa detik untuk muncul dengan prompt yang tepat. Fenomena ini adalah cermin zaman kiwari, di mana AI, dengan jaringan saraf tiruannya, menari di atas kibor, meniru pola pikir manusia, namun tak pernah benar-benar menyentuh esensi kemanusiaan. AI, yang lahir dari data dan algoritma, adalah alat yang menakjubkan sekaligus menyesatkan. Ia mampu merangkai kata, melukis gambar, bahkan mencipta melodi, tetapi ia tak pernah merasakan getar jiwa atau pergulatan batin seorang seniman. Publik, bagai kupu-kupu yang terpikat sari bunga, terpesona oleh hasil AI tanpa mempertanyakan asal-usulnya. Padahal, di balik kilau teknologi itu, ada risiko bias dalam data, ketidakadilan dalam desain algoritma, dan kepentingan komersial yang tak selalu jujur. Bahkan ditengarai menurut riset Shumailov, dkk (2023) dalam artikel ilmiah berjudul “The Curse of Recursion: Training on Generated Data Makes Models Forget” dari ribuan konten yang tersebar dalam mesin pencari, ternyata ditemukan konten AI yang mengambil data dari konten AI pula, yang dijulukinya “feedback loop”. Dalam riset sebelumnya, Cinelli, dkk, (2021) yang dipublikasikan dalam artikel berjudul “The Echo Chamber Effect on Social Media”, menemukan efek yang sama pada manusia, yang disebutnya efek gema, dalam jutaan percakapan manusia di dunia maya. Ketika manusia menerima informasi yang sebenarnya berasal dari dirinya sendiri kemudian digunakan sebagai pembenar pikirannya.
Baca Juga: Raja Ampat dan Anatomi Komunikasi Krisis: Pertunjukan Dominasi Kekuasaan di Panggung Ruang Publik dengan Sutradara Tuan Kapital
Deepfake Gaji Guru Beban Negara: Bahasa Resmi vs Sentimen Masyarakat
Kematian Affan Kurniawan dan Runtuhnya Kepercayaan Publik pada Institusi Polisi
Antara Keajaiban dan Ilusi
AI, dalam narasi media, sering digambarkan sebagai entitas yang "berpikir", yang "cerdas," bahkan diiklankan sebagai “solusi untuk para penulis, siswa, mahasiswa, guru dan dosen”, dipuja bak berhala modern. Namun, realitasnya paradoks, ia lebih sederhana sekaligus lebih rumit. AI hanyalah cermin dari data yang kita berikan, sebuah bayang-bayang yang menari sesuai pola yang telah kita ajarkan. Ia tak memiliki kehendak apalagi bebas, tak memiliki jiwa, hanya algoritma yang menelusuri jejak-jejak digital yang kita tinggalkan. Namun, kesederhanaan ini justru menjadi pedang bermata dua. Ketika masyarakat memuja hasil AI sebagai kebenaran mutlak, mereka lupa bahwa data yang membentuknya bisa bias, diskriminatif, bisa cacat. Seperti lukisan indah namun retak di bawah permukaan catnya, AI sering menyembunyikan ketidaksempurnaan di balik fasadnya yang memesonakan. Lihatlah para dosen yang sudah terbiasa tanpa alat bantu membedakan mana tugas mahasiswa yang otentik dan mana hasil AI.
Di Indonesia, bayang-bayang AI menyelinap dalam keseharian, sering kali tanpa disadari. Sebuah Deepfake, dengan keajaiban manipulasi videonya, belum lama telah mengguncang opini publik perihal siapa sebenarnya yang menjadi beban negara, guru atau anggota DPR? Beruntung, video deepfake lain masih berkisar pada satire politik dan belum sampai pada penyalahgunaan yang mengerikan. Di lapak pasar digital, e-commerce, sistem rekomendasi dan media sosial membentuk pilihan kita, bagai penutup mata yang memaksa dengan lembut dan hangat agar pelupuk terlena lalu terlelap.
Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, AI ikut mengatur lampu lalu lintas dan memantau pergerakan warga, namun tidak banyak yang tahu di mana langkah kita terekam, dianalisis, dan disimpan. Warga hanya melihat petikan rekamannya di media sosial dinas perhubungan atau kabarnya dilampirkan dalam tagihan tilang elektronik ETLE. Dalam dunia pendidikan, aplikasi berbasis AI menawarkan jawaban instan, dan sering kali mencuri kesempatan siswa untuk bergulat dengan konsep, untuk merasakan kepuasan dari memecahkan masalah dengan mata kepala dan tangan mereka sendiri.
Fenomena lain yang menggugah perenungan mendalam adalah iklan tentang jasa kecerdasan buatan berbiaya rendah, yang menawarkan segala bentuk kreasi, dari esai yang terstruktur hingga karya ilmiah yang rumit, lukisan digital yang memikat, pengeditan video dan audio yang mulus, hingga penciptaan musik dan seni visual, hanya dengan beberapa dolar Amerika Serikat. Kemudahan ini, bagai gelas air putih dingin yang menggoda tabir tipis kemalasan manusia, tanpa kepemilikan watak yang kuat, berpotensi meredupkan cahaya apresiasi terhadap perjalanan kreatif yang otentik: di mana keringat, kegagalan, dan inspirasi ilahi menyatu dalam jiwa penciptaan manusia, menjadikannya bukan sekadar produk, melainkan cermin kehadiran kemanusiaan.
Di arena politik, lembaga survei dan tim kampanye memanfaatkan crawler AI untuk menyelami lautan opini publik, namun pemilihan kata-kata dalam menambang data, antara "dilindas", "terlindas", atau "melindas" membawa racun bias inheren yang tak terlihat, memungkinkan analisis berubah menjadi senjata manipulasi yang halus. Sebagaimana digambarkan dalam film semi-dokumenter berjudul The Social Dilemma, di mana suara kolektif menjadi boneka algoritma.
Sementara itu, di sektor layanan pelanggan, chatbot berbasis AI mendominasi interaksi, menciptakan ironi yang menyayat: banyak pengguna, tanpa sadar, berdialog dengan avatar yang dingin, di mana informasi yang disajikan sering kali terbatas, gagal menangkap nuansa konteks rumitnya persoalan manusia. Bak menari dengan hantu dalam irama kaku tanpa emosi, sehingga layaklah mempertanyakan apakah kemajuan ini benar-benar melayani, atau justru mengasingkan kita dari hubungan insani.
Gejala-gejala itu menegaskan urgensi komunikasi sains tentang teknologi, yang etis dan bertanggung jawab, di mana kita harus merenungkan: tanpa pemahaman yang mendalam, masyarakat berisiko terperangkap sebagai wayang dalam pertunjukan manipulatif teknologi, alih-alih menjadi dalang yang sublim menuju harmoni antara kode-kode mesin dan roh manusia.
Tantangan Komunikasi Sains: Menjembatani Jiwa dan Mesin
Komunikasi sains di era AI bukanlah sekadar menyampaikan fakta, melainkan menenun jembatan antara dunia teknis yang kaku dan jiwa manusia yang penuh warna. Kita tak bisa lagi bergantung pada jargon teknis atau diagram baku untuk menjelaskan machine learning atau neural networks. Publik bukanlah ilmuwan; namun mereka adalah penutur cerita, pencinta puisi, dan pemimpi yang merindukan makna. Oleh karena itu, komunikasi sains harus berbicara dalam bahasa mereka, bahasa narasi, analogi, dan visual yang hidup.
Bayangkan machine learning sebagai seorang anak kecil yang belajar mengenal dunia: ia melihat ribuan gambar kucing, dari berbagai sudut, hingga akhirnya bisa berkata, "Ini kucing!" tanpa ragu. Neural networks, bagai jaringan jalan di sebuah kota tua, menjadi semakin kuat setiap kali informasi melintas melalui jalur-jalurnya. Dengan narasi seperti ini, AI tak lagi tampak sebagai monster, melainkan alat yang akrab, yang bisa dipahami, bahkan dicintai, sekaligus tetap patut diwaspadai.
Media sosial, entah TikTok atau Instagram, atau lainnya, telah menjadi saluran utama di mana publik menyerap informasi tentang AI. Di sinilah peran komunikator sains menjadi krusial. Kita harus berkolaborasi dengan kreator konten, dengan influencer digital yang mampu mengemas kebenaran ilmiah dalam bentuk yang memikat. Google DeepMind menawarkan alternatif jalannya dengan video animasi yang menjelaskan reinforcement learning melalui cerita yang sederhana namun memukau. Di Indonesia, inisiatif serupa mulai muncul, meski masih seperti setitik cahaya di tengah tebalnya kabut. Indonesia AI Society dan platform seperti Kelas Pintar telah mencoba, namun kita membutuhkan lebih banyak nyala api, lebih banyak cerita yang relevan, lebih banyak visual yang menyentuh hati.
Menuju Masa Depan yang Berpijar
Untuk membangun literasi AI di Indonesia, kita perlu strategi yang tak hanya informatif, tetapi juga transformatif. Pertama, kolaborasi multisektoral harus menjadi tulang punggung: ilmuwan, komunikator sains, jurnalis, dan kreator konten bekerja sama menciptakan narasi yang jujur dan relevan. Kedua, literasi AI harus masuk ke kurikulum sekolah, bukan sebagai pelajaran teknis semata, tetapi sebagai pelajaran tentang etika, keterbatasan, dan potensi teknologi. Ketiga, platform digital harus bertanggung jawab menyaring misinformasi dan mendukung edukasi publik. Terakhir, kita harus menumbuhkan kultur kritis: masyarakat harus belajar bertanya, "Siapa di balik AI ini? Apa tujuannya? Dan siapa yang diuntungkan?" Atau kemudian memiliki budaya untuk mengakui, “karya saya ini pada tahap tertentu dibantu AI”. Sikap ambigu yang menolak Ai tapi sekaligus menjadi konsumen setia secara diam-diam, perlu dibongkar. Seorang kawan bereksperimen membuat novellete dengan kolaborasi 2 buah AI yang dijulukinya sebagai Neng Copi dan Bobu karena ragu apakah publik akan menerima karyanya jika secara terbuka disebut, “naskahnya dibuat bersama AI”.
Indonesia, dengan mozaik budaya dan kompleksitas sosialnya, adalah kanvas yang sempurna untuk melukis model komunikasi teknologi yang inklusif. Kita bisa menjadi pelopor di Asia Tenggara, menunjukkan bahwa AI bukanlah sekadar alat, tetapi cermin dari nilai-nilai kita sebagai bangsa berkarakter. Namun, tanpa komunikasi sains yang jujur dan tulus, AI berisiko menjadi bayang-bayang yang memperdalam jurang digital, menguntungkan segelintir pihak sambil meninggalkan yang lain dalam kegelapan.
Seperti pengalaman saya di lomba seni budaya yang saya sampaikan di awal tulisan ini, AI mengingatkan kita pada dualitas manusia: antara kreativitas yang tak terbatas dan keterbatasan yang tak terelakkan. Komunikasi sains yang efektif adalah jembatan yang menghubungkan keduanya, antara mesin dan jiwa, antara teknologi dan kemanusiaan. Mari kita kembali bermimpi, bertanya, dan mencipta masa depan yang lebih otentik, lebih insani. Tak membiarkan mesin memimpin kemanusiaan. Kita adalah dalangnya.
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB



