Refleksi 2025: Mengapa Isu Kontroversi Ijazah Jokowi Berkepanjangan?
Kasus kontroversi ijazah Jokowi menjadi cerminan cara masyarakat Indonesia menghadapi informasi di era digital.
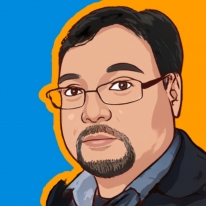
Mang Sawal
Praktisi komunikasi dan pembelajar pada Program Doktoral Unisba dengan fokus pada komunikasi sains. Aktif di berbagai kegiatan edukasi publik.
22 Desember 2025
BandungBergerak.id – Malam pergi. Pekan berlalu. Tahun pun berganti. Tak dinyana, enam tahun sudah, orang-orang menghebohkan selembar kertas yang mengambang di udara, tak jatuh, tak pula terbang, bak daun kering yang enggan merindu tanah.
Begitulah, sejarah Indonesia akan menambah catatan tentang peristiwa penting yang berlangsung bertahun-tahun. Selain perang Diponegoro atau de Java Oorlog yang berlangsung dari 1825 hingga 1830, kemudian Perang Kemerdekaan RI dari 1945 hingga 1949. Kini bertambah dengan perdebatan tentang keaslian dokumen akademik Joko Widodo (Jokowi), seorang pemimpin negara, yang berlangsung sejak tahun 2019, dan melampaui tahun 2025. Di masa depan, anak-anak akan memperoleh bahan kelakar tentang peristiwa penting di Indonesia yang ternyata berlangsung di malam hari, yaitu antara pukul 18.25 hingga 18.30, lalu 19.45 hingga 19.49 dan pukul 20.19 hingga 20.26.
Kontroversi berkepanjangan tentang keaslian dokumen akademik ini telah menembus ruang publik dan privat, memecah belah opini publik di media massa dan media sosial, bahkan merenggangkan hubungan antartetangga di meja pingpong dan pos ronda. Sependek pengetahuan penulis, isu ini bermula sebagai bisikan di kalangan oposisi politik pada 2019 dan sempat mereda setelah ada yang dipenjara oleh vonis hakim, sebelum bangkit kembali pada 2024 ketika Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) melaporkan dugaan pemalsuan ke Bareskrim Polri. Perdebatan kemudian memanas dari Januari hingga April 2025, usai viralnya sebuah video yang mempertanyakan kejanggalan teknis pada dokumen, seperti penggunaan font Times New Roman serta analisis digital forensik independen yang meragukan keaslian foto. Bulan Mei 2025, polisi mengumumkan telah melakukan uji forensik terhadap dokumen yang diperkarakan dan menyatakan dokumen tersebut asli, diperkuat oleh verifikasi arsip universitas terkait, sehingga terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Bareskrim atas laporan TPUA. Kemudian November 2025 Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka penyebar fitnah dan hoaks atas laporan pemilik dokumen.
Di media massa dan media sosial, sepanjang tahun, muncul dua realitas berbeda. Realitas A yang memegang teguh verifikasi institusi resmi negara, serta Realitas B yang menganggap verifikasi tidak transparan, proses hukum sebagai kriminalisasi, dan kekhawatiran atas adanya moral hazzard dalam politik. Kedua realitas ini dipercaya secara fanatik oleh sebagian masyarakat yang sebenarnya berpijak di tanah air yang sama, namun seakan hidup di alam yang berbeda. Bak air dan minyak dalam bejana.
Kasus ini penulis bahas jelang pergantian tahun bukan karena menyangkut nama seseorang yang pernah jadi presiden, melainkan karena menjadi cermin atas cara masyarakat Indonesia menghadapi informasi di era digital. Sebagian akademisi mulai cemas, kontroversi ini secara fundamental akan merusak kepercayaan publik kepada institusi sosial penting, seperti perguruan tinggi dan hasil riset ilmiah, integritas lembaga penegak hukum dan peradilan, hingga otoritas media massa yang digantikan oleh influencer dan buzzer. Pola yang sama, yaitu tuduhan viral, pengabaian pemeriksaan fakta, dan hilangnya ruang dialog deliberatif, dikhawatirkan akan terulang pada setiap kontestasi politik mendatang jika masyarakat tidak benar-benar belajar dari kasus ini.
Demokrasi yang sehat memerlukan warga yang meski berbeda pendapat, namun masih mengakui adanya "fakta bersama" yaitu “kita adalah bangsa yang satu: bangsa Indonesia”. Ketika landasan fakta bersama itu hilang, yang tersisa hanyalah perang narasi emosional, dan berdampak serius pada kesehatan mental, menciptakan kecemasan dan sinisme massal.
Tampak serius ya? Tapi benarkah sinyalemen itu? Bagaimana sikap kita? Untuk menjawabnya, pertama kita harus memahami mengapa kontroversi ini sulit dihentikan. Kemudian menggunakan bantuan teori ilmu sosial, kita analisis dampak kontroversi ini, untuk memperoleh panduan dalam menghadapi situasi serupa pada siklus musim politik berikutnya.
Baca Juga: Obligasi Kaum Cendikiawan
Deepfake Gaji Guru Beban Negara: Bahasa Resmi vs Sentimen Masyarakat
Ketika Pengetahuan Turun dari Menara Gading: Pelajaran dari The Conversation Indonesia untuk Ruang Publik Kita
Perjuangan untuk Dapat Pengakuan
Melalui penelusuran sejumlah pustaka yang dapat diperoleh dengan mudah saat ini dengan bantuan agregator metadata anna’s archive yang menghubungkan kita dengan shadow libraries macam LibGen dan z-library, setiap orang dapat dengan mudah menemukan sejumlah pandangan ahli yang relevan dengan tema kita.
Pertama datang dari Walter Lippmann, jurnalis dan pemikir Amerika, dalam bukunya “Public Opinion” (1922). Ia menjelaskan dunia ini terlalu luas dan terlalu jelimet untuk kita alami dan pahami sendiri. Karena itu, kini kita melihat dunia melalui perantara-perantara dan membentuk “pictures in our heads” atau "gambar di benak kita" tentang kenyataan, yang disebut Lippmann sebagai pseudo-environment atau dunia bayangan. Gambar-gambar dalam benak kita dibentuk dari potongan informasi media sosial, cerita tetangga, teman, celoteh grup WA, stereotip yang menempel seperti tercurah dari mulut influencer bernama Resmob. Lippmann terkenal dengan kutipan, “We define first, then see” (Kita memutuskan terlebih dahulu, baru menilai kenyataan). Artinya, ketika kita sudah memutuskan orang itu sebagai "koruptor" atau "pahlawan" maka semua informasi berikutnya akan disaring melalui lensa tersebut, sehingga bukti yang mendukung akan diterima, dan bukti yang bertentangan akan ditolak atau diabaikan. Kita bisa lebih lanjut mempelajarinya dari ilmu psikologi yang disebut “bias konfirmasi”. Di era media sosial, algoritma menciptakan “filter bubble” (gelembung penyaring) yang membuat pseudo-environment setiap orang menjadi semakin terisolasi (Pariser, 2011, The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You). Lini masa seseorang terus menerus disuapi hanya yang ia sukai.
Kemudian dua tokoh propaganda modern, Edward Bernays (1928, Propaganda) dan Harold Lasswell (1927, Propaganda Technique in the World War), memperkuat bahwa pikiran kita dapat direkayasa. Bernays mengajukan konsep “Engineering of Consent” (rekayasa dukungan, yaitu mengarahkan opini publik tanpa mereka sadari sedang dipengaruhi). Teknik propaganda mereka, yang masih digunakan hingga hari ini, meliputi Testimonial (menggunakan tokoh terpercaya), Name-Calling (memberi label negatif seperti "pembohong" atau "rezim zalim"), Card Stacking (memilih fakta menguntungkan saja), Bandwagon (menciptakan kesan "semua orang dukung kita"), Plain Folks (pura-pura polos), Transfer (asosiasi dengan simbol), dan Glittering Generality (kata-kata indah tanpa dasar, seperti “pohon sawit itu ada daunnya juga”). Propaganda modern bekerja dengan merekayasa lingkungan informasi sehingga orang merasa sedang berpikir mandiri, padahal sebenarnya sedang dipandu, dikendalikan. Sementara Lasswell menawarkan model analisis untuk melihat “siapa yang mengatakan apa, kepada siapa, melalui saluran apa, dan apa akibatnya”.
Perspektif berikutnya dari Peter Berger & Thomas Luckmann. Melalui buku klasik “The Social Construction of Reality” (1966) mereka menjelaskan bahwa apa yang kita anggap "kenyataan" adalah hasil dari konstruksi sosial. Prosesnya meliputi tiga tahap yang terus berulang: Eksternalisasi (manusia menciptakan narasi), Objektivasi (narasi itu terasa objektif, seolah sudah ada dari dulu), dan Internalisasi (kita menyerapnya sebagai kebenaran alamiah). Dalam konteks kontroversi yang sedang ramai, di kedua kubu (pro dan kontra), proses konstruksi sosial berjalan sempurna, di mana narasi mereka (misalnya, "Ini fitnah politik" di Kubu A dan "Ini skandal yang disembunyikan" di Kubu B) menjadi "fakta yang semua orang tahu" dalam kelompok mereka, dan setiap anggota kelompok tidak lagi mempertanyakan asumsi tersebut. Kepercayaan ini diperkuat oleh plausibility structure, komunitas atau social environment (grup WhatsApp, forum online) yang terus-menerus menguatkan narasi yang sama di antara masing-masing. Implikasinya, kedua kelompok sama-sama yakin "benar".
Selanjutnya yang bisa membantu kita memahami mengapa kontroversi terus berkepanjangan adalah Axel Honneth, filsuf Jerman dari Mazhab Frankfurt. Dalam bukunya “The Struggle for Recognition” (1992), ia menyebut, manusia membutuhkan tiga bentuk pengakuan: Love/Care (membentuk kepercayaan diri dasar), Rights (membentuk harga diri sebagai subjek hukum), dan Social Esteem (membentuk harga diri sosial atas kontribusi). Ketika salah satu pengakuan itu dirampas, yang disebut misrecognition atau peniadaan-pengakuan, ia menciptakan luka psikologis yang dalam, membuat orang berjuang mati-matian, bahkan lebih keras daripada berjuang untuk berkuasa, agar mendapatkan pengakuan itu kembali. Honneth menyimpulkan bahwa konflik sosial yang paling keras bukanlah tentang distribusi sumber daya, melainkan tentang pengakuan identitas. Setiap pihak bertarung bukan hanya untuk kebenaran, tetapi untuk mempertahankan harga diri.
Perspektif yang terakhir, amat dikenal oleh praktisi kehumasan, yaitu Pakar Public Relations Frank Jefkins (1994, Public Relations) yang memberikan rumusan sederhana: Citra = Performance + Behaviour + Communication. Menurut Jeffkins, Communication (cara narasi dikomunikasikan) bisa lebih kuat daripada Performance (prestasi nyata) sehingga prestasi dapat dirusak oleh komunikasi lawan yang lebih keras, lebih emosional, dan lebih viral. Di era media sosial, yang paling keras berteriak dan paling sering mengulang-ulanglah yang memenangkan perang citra, menjadikan kebenaran faktual sebagai hal tidak penting lagi. Sebenarnya ide ini sudah lama dicetuskan oleh tokoh kontroversial, Adolf Hilter dalam bukunya, Mein Kampf (1925, Buku 1 Bab X, Ursachen des Zusammenbruches):
“Es blieb aber doch immer etwas hängen. Beharrlichkeit ist hiebei die erste und wichtigste Voraussetzung zum Erfolg... Was zunächst in der Frechheit seiner Behauptung als idiotisch erscheint, wird später als bedenkenswert empfunden und schließlich geglaubt.”
Terjemah singkatnya, ketekunan dalam menyampaikan sesuatu yang tampak bodoh, akan menyebabkan itu dipercaya pada akhirnya. Ide ini kerap disampaikan dengan frasa, “kebohongan yang terus menerus disampaikan, lama-lama akan dipercaya sebagai kebenaran”.
Dampak Kontroversi Berkepanjangan
Dari lima perspektif itu, kita dapat melihat, kontroversi berkepanjangan akan membawa dampak pada tiga level kehidupan bermasyarakat.
Memakai perspektif Lippmann, di tingkat individu, banyak warga yang tidak terlalu fanatik pada politik akan mengalami “information anxiety” (kecemasan informasi) karena dibanjiri informasi yang saling bertentangan, juga merasa kehilangan “ground truth” (landasan kebenaran), dan mengalami apa yang disebut Lippmann “disorientasi kognitif”. Wujud nyatanya adalah rasa sebal, jengah, atau sebaliknya, menolak ikut membicarakannya dan apatis, sebagai mekanisme mengurangi kebingungan. Kedua sikap itu sebenarnya merupakan tekanan mental.
Kontroversi ini juga menyebabkan distorsi prioritas hidup, di mana orang menghabiskan waktu untuk berdebat atas isu yang sebenarnya tidak bisa mereka kendalikan. Atau habis waktu untuk mendengar podcast yang saling bertentangan isinya. Obsesi ini, menurut Honneth, adalah soal harga diri, karenanya waktu yang habis untuk "perang" di media sosial dinilai sebagai perjuangan.
Selain itu terjadi gangguan sosial mikro, di mana hubungan antartetangga, saudara, kolega, tidak lagi nyaman karena perbedaan kubu. Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa hilangnya common ground (tempat berpijak yang sama) karena perbedaan "konstruksi realitas" membuat dialog jadi mustahil. Merujuk Honneth, ketidaksetujuan dianggap sebagai bentuk misrecognition ("Kamu bodoh/tertipu"), yang secara psikologis menyakitkan dan berujung pada pemutusan hubungan sosial.
Pada level Makro, terjadi Fragmentasi Epistemologis: masyarakat terpecah menjadi “epistemic tribes”. Anak sekarang menyebutnya, fandom. Setiap kelompok memiliki "sistem pengetahuan" sendiri, hidup dalam pseudo-environment masing-masing, dan mengalami proses internalisasi yang sempurna, di mana mereka merasa "punya kebenaran objektif" dan bukan sekadar "percaya begitu saja". Karena merasa punya banyak informasi, padahal semua datang dari podcast yang isinya senada. Gejala yang mirip dengan polarisasi horizontal, dari perbedaan pendapat menjadi perang kubu, antara "Kami yang kritis" versus "Pro Rezim”. Aktivis vs Penjilat. Tidak cukup bagi satu pihak untuk benar, tetapi pihak lain juga harus mengakui bahwa mereka salah. Masing-masing merasa superior secara moral dan intelektual, serta menurunnya empati sosial, di mana lawan hanya dilihat sebagai "musuh yang harus dikalahkan".
Dampak berikutnya erosi pada modal sosial, konsep yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu pada akhir 70-an, yang menurut Robert Putnam dalam buku Bowling Alone (2000), adalah fondasi masyarakat yang sehat. Kontroversi mengikis ikatan (bonding) antarwarga, menciptakan kecurigaan politik di tempat kerja dan komunitas, dan melemahkan kohesi sosial secara keseluruhan. Terakhir, terjadi normalisasi ujaran kebencian, seperti “Termul”, “Ahli Abal-abal”. Teknik name-calling ini efektif karena menghentikan dialog dan memobilisasi emosi, membuat orang tidak lagi melihat pihak lain sebagai manusia utuh.
Dampak paling serius adalah delegitimasi institusi sosial penting yang permanen. Universitas, kepolisian, dan pengadilan, yang seharusnya menjadi "pusat kepercayaan" dalam memverifikasi kebenaran, tidak lagi dipercaya. Muncul generalisasi, setiap putusan yang tidak sesuai keinginan salah satu kubu dianggap hasil "tekanan politik” atau "dibeli". Krisis kepercayaan ini juga menciptakan demoralisasi pada para profesional berintegritas di dalam institusi, karena kerja profesional mereka dianggap sebagai "bagian dari skenario politik". Dampak jangka panjangnya adalah brain drain dan self-fulfilling prophecy, di mana institusi yang terus dituduh bias akan semakin kehilangan independensinya.
Isu ini juga menciptakan preseden buruk untuk kontestasi politik masa depan. Tuduhan yang diviralkan di media sosial telah menjadi “template” serangan politik yang terbukti efektif karena berbiaya rendah, viral, sulit dibantah dan meninggalkan stigma permanen. Terakhir, kasus ini adalah distraksi massal dari isu substantif. Energi warga habis untuk membahas satu dokumen selama bertahun-tahun, sementara isu-isu mendesak yang secara langsung memengaruhi rakyat, seperti jurang kemiskinan, kualitas buruk pendidikan, politik upah buruh rendah, krisis air bersih, dan bencana buatan manusia akibat sampah atau alih fungsi lahan yang masif, ketamakan pemilik modal, dan lain-lain, tidak mendapat perhatian memadai. Bagi pihak tertentu, distraksi ini menguntungkan karena mengalihkan perhatian publik dari kebijakan-kebijakan pro-elite yang dibuat hari ini, ke arah debat kusir yang hingar bingar.
Rekomendasi
Untuk membangun ketahanan kolektif menghadapi kontroversi serupa di masa depan, diperlukan langkah-langkah praktis dan filosofis. Yang paling sering disarankan adalah lakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima. Namun jarang yang mengutip nasihat Socrates untuk mempraktikkan kerendahan hati epistemik (epistemic humility), yaitu kesediaan untuk mengakui “saya tahu bahwa saya tidak tahu". Jika itu kita miliki, maka mengubah pendapat karena ternyata salah, bukan berarti merendahkan diri, atau aib, melainkan kesiapan belajar dan tanda kedewasaan.
Sementara untuk memeriksa fakta, ada beberapa teknik yang populer, selain Model IMVAIN, ada juga Model SIFT (Mike Caulfield, 2017, Web Literacy for Student Fact-Checkers):
S = STOP: Berhenti sejenak. Jangan langsung percaya atau share;
I = INVESTIGATE the Source: Selidiki siapa yang membuat klaim, apa track record-nya, dan apa motivasinya;
F = FIND Better Coverage: Cari sumber lain yang lebih kredibel atau lebih komprehensif tentang topik yang sama;
T = TRACE Claims to Original Context: Cari konteks asli klaim, dari tanggal, lokasi, dan peristiwa aslinya, karena sering kali klaim dipotong atau diambil di luar konteks.
Tandai red flags pada informasi provokatif, pemakaian nama tokoh terkenal namun tidak ada sumber yang jelas. Sesekali membaca isi media dari spektrum politik yang berbeda atau bergabung dengan grup diskusi yang menerapkan aturan kesopanan ketat. Secara periodik, lakukan pula "digital detox" dengan berhenti membuka media sosial selama beberapa jam kemudian beberapa hari. Yakinlah, hidup kita tidak terpengaruh oleh ketiadaan internet dan ini mengembalikan ketenangan mental.
Ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat, praktikkan mendengar aktif. Hindari langsung membantah atau menghakimi. Sebaliknya, tanyakan dengan tulus, "Kok kamu bisa yakin gitu, sih? Jelasin ke aku, dong". Secara psikologis ini disebut mempraktikkan pengakuan timbal balik (mutual recognition), yaitu memberikan pengakuan pada posisi pihak berbeda tanpa harus menyetujui pendapat mereka. Sepakat untuk tidak sepakat. Pendekatan ini adalah strategi untuk membuka ruang dialog tanpa menghantam harga diri semua pihak.
Berikutnya adalah dukung jurnalisme berkualitas, yang merupakan penangkal disinformasi. Berdonasi, berlangganan media kredibel, seperti Bandung Bergerak ini, membaca artikel sampai selesai, dan membedakan antara fakta dan opini, antara berita dan endorse, adalah langkah penting.
Penutup
Setelah menelusuri bagaimana ilusi, rekayasa, dan kebutuhan akan pengakuan membentuk realitas kita, kita menyadari bahwa kontroversi berkepanjangan ini adalah cermin berharga. Bahwa kebenaran objektif di ruang publik modern sering kali hanyalah produk dari narasi yang paling keras dan paling gigih disampaikan. Menyambut tahun baru, penulis mengajak kita untuk mempraktikkan kerendahan hati epistemik, dengan mengakui kita ternyata tidak tahu banyak, dan untuk mengarahkan energi bukan pada pertarungan narasi yang menghabiskan waktu, melainkan pada isu-isu substantif yang benar-benar memengaruhi kualitas hidup bangsa Indonesia. Jadikan tahun depan sebagai momentum untuk tidak cepat memercayai "gambar" yang dibentuk algoritma, dan membangun kembali ikatan sosial yang terkikis sebagai Bangsa Indonesia yang bermartabat dengan standar hidup yang tinggi. Tidak asal punya kerjaan, tapi tetap miskin. Berbeda pendapat adalah ruang dialog yang matang, tidak perlu bawa perasaan. Yuk, bergerak !!
***
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

