Teror Pertanyaan Kapan Nikah Menjelang Lebaran
Kemajuan ekonomi tanpa kohesi sosial hanyalah sebuah "bom waktu" kesepian.
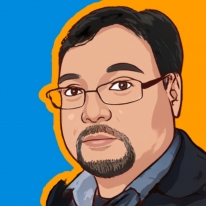
Mang Sawal
Praktisi komunikasi dan pembelajar pada Program Doktoral Unisba dengan fokus pada komunikasi sains. Aktif di berbagai kegiatan edukasi publik.
26 Januari 2026
BandungBergerak.id – Dua puluh tahun lalu, jelang setiap reuni keluarga besar di Indonesia, biasanya pada Lebaran Idulfitri, selalu ada semacam ketakutan kolektif terhadap pertanyaan “kapan nikah” dari para sesepuh. Dulu, ketika keluarga besar berkumpul, jumlahnya dapat mencapai ratusan orang. Sehingga pertanyaan itu tentunya akan menyerang bertubi-tubi pada waktu yang sama. Seiring waktu, 10 tahun terakhir, ketakutan kolektif itu mulai memudar seiring berkurangnya jumlah tetua dan berkurangnya jumlah anggota keluarga besar. Berbeda dengan generasi dahulu yang beranak banyak, generasi berikutnya adalah keluarga kecil. Ayah saya kakak beradik mencapai 15 orang, saya sendiri kakak beradik jumlahnya 4 orang, anak saya dua orang. Sehingga kemarin, ketika keluarga besar berkumpul jumlahnya tinggal puluhan. Jika hanya keluarga inti yang berkumpul maka jumlahnya bahkan tidak mencapai dua lusin. Teror pertanyaan “kapan nikah” juga berkurang drastis, bahkan akhir-akhir ini, yang bertanya mulai malas mengajukan pertanyaan itu.
Realitas ini dipertajam oleh data Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia yang mencatat penurunan angka pernikahan selama 10 tahun terakhir. Awal tahun 2026, kompas.com kembali merekap tren itu, dari data BPS tahun 2014 hingga 2024 dan melaporkan, penurunan jumlah pernikahan di Indonesia mencapai 30 persen selama dekade terakhir. Jumlah pasangan yang menikah di atas usia 30 tahun juga meningkat. Paling banyak alasannya adalah ekonomi. Termasuk di antaranya memilih karier mapan terlebih dahulu, baru berkeluarga. Realitas ini membawa serta realitas lain, makin banyak lajang yang tinggal sendiri di apartemen sewaan, menurunnya belanja rumah tinggal, makin berkurangnya interaksi sosial karena waktu habis di kantor atau jalan menuju kantor. Tekanan pekerjaan dan di perjalanan meningkatkan tekanan mental sekaligus muncul kebutuhan relaksasi individual. Tahun 2022 beredar kabar di linimasa telah ada layanan “teman sewaan” di Ibukota, tahun 2024 podcast Detik TV “20 detik” menampilkan pendiri usaha jasa yang disebut “Gue Temenin Jalan” itu ke depan kamera dan memaparkan jasa layanannya secara terbuka. Setelah sekian tahun melayani konsumen, terkonfirmasi, alasan pengguna jasa ini adalah para pekerja amat terbatas waktunya, di sisi lain, mereka ingin tetap nampak normal, seperti punya teman atau pacar dan jalan-jalan di Mal.
Gejala ini sudah dipotret ada pada masyarakat industri Amerika Serikat tahun 1950-an oleh 3 orang sosiolog, Riesman, Glazer dan Denney, yang mengungkap adanya perubahan karakter masyarakat Amerika Serikat pasca industri, “kesepian di tengah kerumunan”, dalam buku mereka The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character. Karakter masyarakat pasca industri disebut other-directed atau outward oriented. Sikap yang adaptif terhadap keinginan orang lain karena kuatir dengan posisi karier mereka. Tidak lama kemudian muncul pula Teori Presentasi Diri dari Erving Goffman mengamati perubahan struktur sosial Amerika Serikat dan Inggris pada masa industrialisasi. Dalam bukunya The Presentation of Self in Everyday Life (1956), Goffman menyebut dalam kehidupan sosialnya, manusia tidak memiliki identitas tunggal. Selalu berubah untuk memperoleh kesan (impression) baik. Buku yang merupakan pengembangan dari disertasinya di Universitas Chicago ini, lahir dari pengamatan terhadap masyarakat urban dan industri, di mana interaksi sosial menuntut pengelolaan kesan demi keberlangsungan relasi. Teori Presentasi Diri kemudian berkembang menjadi Teori Pengelolaan Kesan pada konteks komunikasi organisasi dan akhirnya tahun 70-an menjadi Teori Dramaturgi untuk konteks komunikasi politik. Intinya, manusia bisa bersandiwara dengan memiliki banyak topeng untuk setiap keperluan.
Baca Juga: Cucun Syamsurizal vs Gen Z: Gagalnya Komunikasi Politik dalam Ruang Publik
Ketika Pengetahuan Turun dari Menara Gading: Pelajaran dari The Conversation Indonesia untuk Ruang Publik Kita
Refleksi 2025: Mengapa Isu Kontroversi Ijazah Jokowi Berkepanjangan?
Masyarakat Pura-pura Pasca Industri
Berpura-pura demi citra sosial dan karier menginspirasi banyak film Hollywood, terutama karena teror “kapan nikah” bukanlah monopoli budaya timur, melainkan juga budaya barat di masa lalu sebelum industrialisasi. Ada film, The Proposal (2009) yang diperankan Sandra Bullock dan Ryan Reynolds yang pura-pura menikah demi karier. Kemudian Holidate (2020) yang mengisahkan tokoh perempuan lajang bernama Sloane yang diperankan Emma Roberts, yang pura-pura punya calon untuk bisa menjawab pertanyaan “kapan nikah” di acara kumpul keluarga pada libur hari raya.
Tahun 2024, ada film Rental Family yang tayang di Netflix karya sutradara Kaspar Astrup Schröder, yang memperoleh penghargaan di beberapa festival film seperti SXSW Film Festival, CPH:DOX, Hot Docs. Penonton film drama komedi ini tidak akan menyangka jika film itu ternyata masuk kategori film dokumenter karena diproduksi dengan gaya fly on the wall. Film produksi kolaborasi antara Good Company Pictures Denmark dengan Danish Film Institute, Lembaga Penyiaran Publik Denmark-DR, dan Creative Europe MEDIA ini memperlihatkan dokumen sosiologis tentang masyarakat yang "patah". Film ini mengisahkan perusahaan bernama Family Romance yang memberikan layanan penyewaan manusia untuk berperan sebagai apa pun yang diminta pelanggannya.
Inspirasi bisnis ini muncul dari pengalaman seorang pria bernama Yuichi Ishii yang lahir di Jepang pada awal 1980-an, seusai membantu seorang teman yang merupakan ibu tunggal. Teman tersebut kesulitan mendaftarkan anaknya ke sebuah sekolah swasta prestisius karena persyaratan harus memiliki "ayah". Ishii kemudian berpura-pura menjadi sang ayah, dan dari sanalah ia menyadari bahwa ada potensi pasar yang besar untuk menjadi "sosok pengganti" di Jepang (Batuman, Japan’s Rent-a-Family Industry, The New Yorker, 23 April 2018). Selama lebih dari satu dekade sejak perusahaannya berdiri tahun 2009, Ishii telah memerankan ribuan peran berbeda untuk kliennya. Saking banyaknya peran berbeda itu, terkadang ia sendiri lupa siapa "Yuichi Ishii" yang sebenarnya (Lodge, "Rental Family’ Review: A Moving, Many-Sided Portrait of a Japanese Business Built on Performance, Variety, 2024).
Kerapuhan Sosial Pasca Industri di Jepang
Melalui narasi visualnya, film ini memaparkan beberapa fakta sosial yang terjadi di Jepang pasca industri. Masyarakat Jepang memang menghadapi masalah besar setelah era industri. Laporan dari Kementerian Kesehatan Jepang, yang tertuang dalam dokumen “Labour and Welfare of Japan. White Paper on Suicide Prevention in Japan 2024” menunjukkan tren mengkhawatirkan. Selain masalah depopulasi karena rendahnya angka kelahiran dan perkawinan, hingga dekade terakhir, fenomena Kodokushi atau kematian dalam kesendirian terus meningkat. Data dari Kepolisian Nasional Jepang menunjukkan ribuan lansia ditemukan meninggal di rumahnya tanpa diketahui siapa pun setelah berhari-hari karena tidak adanya jaringan sosial.
Seorang pakar sosiologi terkemuka Jepang, Sugimoto menulis dalam bukunya An Introduction to Japanese Society (2020) bahwa industrialisasi menyebabkan adanya isolasi sosial yang bukan hanya menjadi masalah manusia lanjut usia, tetapi juga dewasa muda yang merasa tertekan oleh ekspektasi sosial (tatemae) yang sangat berat. Sebelumnya, seorang guru besar Antropologi Universitas Duke, Allison menulis buku Precarious Japan (2013) tentang hal yang sama, bahwa kemajuan industri di Jepang justru diikuti oleh hilangnya "rumah" secara emosional, peningkatan angka bunuh diri, dan munculnya jasa-jasa substitusi hubungan manusia.
Fenomena ini adalah akumulasi dari luka sejarah pasca-industri Jepang. Pada medio 1980-an, Jepang berada di puncak kejayaan ekonomi, namun keberhasilan itu menuntut tumbal berupa runtuhnya struktur keluarga tradisional Ie (keluarga luas) menjadi keluarga inti yang terfragmentasi. Memasuki 1990-an, pasca pecahnya bubble economy, muncul ketidakpastian kerja yang melahirkan fenomena Hikikomori atau penarikan diri secara ekstrem dari masyarakat (Harayama, Society 5.0: Aiming for a New Human-centered Society, Hitachi Review, 2017;66(6):8-13).
Layanan keluarga sewaan muncul bukan karena orang Jepang kekurangan uang, melainkan karena mereka mengalami "kelaparan" akan kehadiran manusia di tengah masyarakat yang terkotak-kotak di dalam ruang-ruang apartemen. Seperti yang diungkapkan Allison, masyarakat pasca-industri di Jepang telah masuk ke dalam kondisi "kehidupan yang ringkih" (precarious life), di mana ikatan sosial organik telah digantikan oleh transaksi pasar.
Menghadapi kehancuran jaringan sosial tersebut, pemerintah Jepang pada tahun 2016 meluncurkan sebuah visi besar yang dikenal sebagai Society 5.0. Konsep ini secara resmi diperkenalkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe dalam forum CeBIT 2017 sebagai upaya mentransformasi Jepang menjadi masyarakat "Super Pintar" (Kantor Sekretaris Kabinet Jepang, Society 5.0, 2016).
Secara filosofis, Society 5.0 berasumsi bahwa jika Industri 4.0 berfokus pada efisiensi mesin, maka Society 5.0 harus berfokus pada kesejahteraan manusia (human-centric). Isinya adalah integrasi total antara ruang siber (AI dan Big Data) dengan ruang fisik untuk menyelesaikan masalah praktis. Teori yang melatarinya adalah Socio-Technical Systems, yang berargumen bahwa kemajuan teknologi harus selaras dengan struktur sosial untuk menghindari disrupsi kemanusiaan.
Dalam praktiknya, Society 5.0 mencoba "menjahit" kembali hubungan manusia melalui bantuan teknologi. Jika tidak ada orang yang merawat lansia karena depopulasi, maka robot pendamping dengan kecerdasan buatan akan hadir. Jika warga desa terisolasi karena usia, kendaraan otonom akan mengantarkan kebutuhan mereka. Namun, di sinilah letak paradoksnya: mampukah algoritma dan mesin menggantikan kehangatan organik yang hilang? Harayama menekankan bahwa Society 5.0 bukan tentang teknologi semata, melainkan tentang bagaimana teknologi itu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi setiap individu.
Refleksi untuk Indonesia
Bagi Anda yang saat ini berusia 19 hingga 34 tahun, dalam visi Indonesia Emas 2045, masa depan ada di pundak kalian. Kita berambisi menjadi kekuatan ekonomi baru. Namun, cermin dari Jepang mengingatkan, apakah kita akan mengejar pertumbuhan yang tinggi tapi harus menyewa "teman" untuk sekadar ngobrol di hari tua?
Saat ini, Indonesia masih memiliki modal yang telah hilang di banyak masyarakat negara maju, yaitu Modal Sosial (Social Capital) yang kuat. Kita masih memiliki budaya gotong royong yang bersifat kolektif organik (Salim, Sosiologi Pembangunan: Perspektif Indonesia. 2019). Kita memiliki ruang publik yang cair, seperti warung kopi, pos ronda, lapangan ping-pong atau pelataran masjid, yang mencegah manusia merasa sendirian. Kekuatan struktur keluarga tambahan (extended family) seperti tetangga, di Indonesia masih menjadi jaring pengaman yang luar biasa kuat. Nilai religiositas kita juga berperan penting sebagai mekanisme pertahanan mental (coping mechanism), karena agama di Indonesia bukan sekadar urusan privat, melainkan perekat komunitas yang memberikan makna hidup saat tekanan duniawi terasa menyesakkan. Pengelola rumah ibadah di Indonesia saat ini juga menjadi agregator sosial.
Kemajuan ekonomi tanpa kohesi sosial hanyalah sebuah "bom waktu" kesepian. Kita harus memelihara modal sosial ini seiring pengembangan modal keuangan dan modal manusia. Untuk itu, penulis merekomendasikan agar masalah sosial pasca-industri tidak terjadi di Indonesia, diperlukan langkah-langkah struktural yang nyata dari penyelenggara negara.
Pertama, rekayasa ruang publik yang inklusif. Negara harus mewajibkan, setiap pengembang perumahan atau kawasan industri untuk menyediakan ruang interaksi sosial, berupa ruang terbuka hijau dan balai warga, yang selama ini hanyalah opsi yang dapat ditukarguling menjadi lahan pemakaman atau sekedar median jalan serta menyokong "program komunitas" agar ruang tersebut hidup secara organik, misal: festival kuliner lokal, atau panggung talenta lokal, atau pameran proyek sains anak-anak. Jangan biarkan pembangunan kota hanya menciptakan tembok-tembok beton yang mengisolasi manusia. Kedua, harus ada regulasi keseimbangan kerja-hidup (work-life balance). Kita harus menuntut kebijakan yang memberikan hak bagi pekerja untuk memutus kontak dengan tempat kerja setelah jam kerja selesai (right to disconnect). Jika sesampainya di rumah WA dari bos terus datang, maka fungsi sebagai makhluk sosial akan lumpuh. Memberikan insentif bagi pabrik yang menerapkan standar kesehatan mental pekerjanya sebagai bagian dari K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Ketiga, kurikulum sekolah harus seimbang antara kecakapan teknis (riset dan teknologi) dengan kecerdasan sosial dan spiritual. Kita butuh generasi yang tidak hanya pintar memakai mesin Ai, tetapi juga peka terhadap temannya yang sedang kesulitan. Terakhir, sistem jaminan sosial berbasis komunitas. Negara harus kembali memberdayakan unit sosial terkecil seperti RT/RW untuk menjadi garda terdepan deteksi dini masalah kesehatan mental dan isolasi sosial. Tidak melayani birokrasi administratif seperti catat penduduk atau urusan bansos saja, tetapi juga menjadi wahana peningkatan literasi sosial psikologis misalnya berkampanye untuk tidak menghakimi orang yang depresi sebagai kurang beriman atau kompetisi rumah tangga zero waste atau remaja masjid hoax buster atau kampaye zero gadget saat kumpul keluarga.
Indonesia harus maju secara ekonomi, namun warganya tetap menjadi "manusia".
***
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB



