Masih Adakah Pers Indonesia
Masalahnya bukan makin banyak yang tidak percaya pers, melainkan pers makin sulit diakses dengan cara-cara yang relevan dengan kebiasaan digital baru.
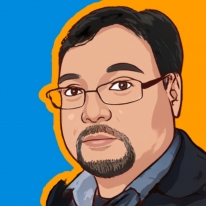
Mang Sawal
Praktisi komunikasi dan pembelajar pada Program Doktoral Unisba dengan fokus pada komunikasi sains. Aktif di berbagai kegiatan edukasi publik.
5 Februari 2026
BandungBergerak.id – Sebagai lulusan pendidikan tinggi ilmu jurnalistik, akhir-akhir ini saya makin trenyuh melihat kenyataan yang ada. Makin banyak lembaga media massa yang disebut media pers, tutup karena tidak lagi sanggup membiayai operasionalnya. Lalu ada hasil survei yang menyebut banyak pihak yang menyesal telah memilih kuliah menghabiskan biaya dan waktu di bidang jurnalistik, tapi tidak jelas masa depan pekerjaannya. Pada saat yang sama, banyak keluhan dari masyarakat tentang banyaknya orang yang mengaku wartawan tapi bukan mencari informasi sebagai bahan berita, melainkan mencari gara-gara dan memaksa meminta uang atau fasilitas. Seorang pejabat provinsi pada Bulan Juni 2025 di depan ratusan mahasiswa di Bogor mengatakan, dirinya tidak mengalokasikan anggaran untuk media massa dan menyarankan seluruh pimpinan daerah menyampaikan informasi publik melalui kanal media sosial saja agar lebih efisien. Belum termasuk keluhan khalayak media sosial yang menerima informasi melalui lini masanya yang tampak seperti berita, tapi tidak jelas sumbernya, tidak akurat, bahkan hoaks.
Setiap tahun, Hari Pers Nasional diperingati di Bulan Februari. Tahun 2026 ini akan berlangsung di Kota Serang, Banten. Tapi makin lama makin besar tanda tanyanya, apa sebenarnya yang diperingati? Masih adakah pers nasional itu? Saya pribadi berharap jawabannya memberi harapan, tapi kenyataan di atas, menyiratkan tak ada harapan. Mungkin saya tidak sendiri. Banyak dari kita, para pembaca, pendengar, pemirsa dan pengguna internet, sudah terlalu lama menunggu jawaban. Kita melihat berita sensasi, potret peristiwa yang tidak lengkap, dan konten yang kadang lebih mirip promosi ketimbang laporan jurnalistik.
Baca Juga: Represi, PHK Massal, dan Swasensor Membayangi Dunia Pers Hari Ini
UU Pers Dinilai Sudah Kuat, yang Lemah Justru Penegakan Hukumnya
Keberpihakan Pers di Gelombang Demonstrasi Melahirkan Narasi Warga Jaga Media
Industri Media yang Pincang
Sebagai konsumen, saya selalu membayangkan media pers itu perkasa, punya pengaruh besar dalam masyarakat, kantornya mentereng, dan wartawannya cerdas. Tapi akhir-akhir ini makin banyak singgah di lini masa, laporan tentang industri media pers di Indonesia yang berjalan makin pincang.
Ketika saya cari tahu dan mengunjungi sejumlah sumber digital, termasuk laman Dewan Pers, ternyata media online (daring)sejak dekade terakhir muncul seperti cendawan di musim hujan, jumlahnya puluhan ribu. Namun media massa kini tidak lagi menjadi tempat orang beriklan, bahkan pemerintah pun tidak lagi beriklan di media massa. Media digital dan influencer media sosial kini menjadi tempat iklan ditampilkan. Media massa kehilangan keperkasaannya, di tengah kerumunan cendawan ini para pekerja pers bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Di gaji amat rendah atau sama sekali tidak digaji dan dibiarkan memakai statusnya sebagai wartawan untuk mengemis atau memeras demi memperoleh uang. Sementara wartawan yang profesional makin sering mendapat intimidasi.
Berikut ini tabel data antara tahun 2023 dan 2024, dari laman Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen, dan sumber digital lain:
|
Aspek |
Kondisi Aktual |
|
Media cetak yang masih bertahan |
< 20% dari jumlah satu dekade lalu |
|
Media terverifikasi Dewan Pers |
± 2.700 |
|
Jumlah pekerja media pers |
50.000–70.000 |
|
Penurunan pendapatan iklan media akibat dominasi platform asing |
40–60% (Google–Meta Share, 2024) |
|
Kasus kekerasan terhadap jurnalis |
60 kasus (AJI, 2024) |
Kenyataan ini memperlihatkan masalah berat akibat ekosistem industri media yang makin oligopolistik di tangan segelintir perusahaan multinasional.
Media Sosial vs. Pers
Data Reuters Institute 2024 menunjukkan hampir 80 persen generasi muda Indonesia mendapatkan berita pertama kali dari media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan X. Begitu pula saya, meski tidak lagi muda. Bukan karena saya tidak peduli pada pers, tapi karena pengalaman pengguna (UX) media sosial lebih cepat, lebih visual, dan lebih alami dalam keseharian masa kini yang didominasi smartphone.
Lagi pula, ketika benar-benar ingin memastikan suatu informasi benar atau tidak, saya tetap mencari media pers yang saya nilai profesional. Dan masih banyak yang sama seperti saya perilakunya. Edelman Trust Barometer 2024 menunjukkan kepercayaan publik Indonesia terhadap pers masih berada di kisaran 55-60 persen, ini lebih tinggi dibanding kepercayaan terhadap media sosial yang hanya 30-40 persen.
Jadi masalahnya bukan makin banyak yang tidak percaya pers, melainkan pers makin sulit diakses dengan cara-cara yang relevan dengan kebiasaan digital baru. Dulu pers harus dihampiri untuk memperoleh kontennya, kini pers yang harus menghampiri khalayak untuk membeberkan kontennya. Memang ketika pers mulai mengikuti pola distribusi digital itu, perilaku redaksinya tenggelam dalam arus kuat algoritma sehingga judul berita yang memancing klik menjadi racun terhadap dirinya sendiri. Ketika pers ikut masuk ke dalam jaringan media sosial, isinya menjadi terlalu banyak informasi dangkal yang hanya mengikuti tema yang viral. Terlalu banyak kesalahan faktual yang harus dikoreksi belakangan, dan seterusnya.
Meski sering kesal pada kualitas isi media, saya tidak pernah percaya bahwa influencer akan menggantikan wartawan, dan media sosial menggantikan peran pers. Influencer tidak memiliki kewajiban verifikasi. Konten viral tidak wajib memuat dua sisi cerita dan tunduk pada perintah undang-undang untuk menjadi wahana supremasi hukum dan keadilan seperti dibebankan kepada pers. Pengelola media sosial tidak memiliki organisasi pemeriksaan atau verifikasi isi informasi sebelum tayang, serta tidak diawasi oleh lembaga negara bernama Dewan Pers.
Saya pernah melihat bagaimana hoaks tersebar lebih cepat daripada klarifikasinya. Saya pernah melihat bagaimana isu publik dipelintir hanya karena algoritma mendorong apa pun yang memancing emosi. Bagi saya, di tengah dunia maya yang bising dan penuh ilusi mirip vanity fair dalam novel alegoris abad ke-17 karya John Bunyan berjudul The Pilgrim’s Progress, pers adalah pihak yang bisa diharapkan untuk membawa kembali ke realitas. Melalui pers, saya melengkapi pemahaman terhadap dunia yang luas dan rumit ini.
Komunitas Pers Harus Berubah Cepat
Saya ingin pers Indonesia tetap hidup dan peringatan Hari Pers Nasional tidak berubah menjadi seperti peringatan Hari Pahlawan untuk mengingat semangat dan jasa orang-orang yang sudah wafat. Saya ingin jurnalis bekerja dengan aman dan terhormat. Saya ingin media menjadi tempat mempercayakan pemahaman yang tepat tentang dunia yang penuh sandiwara. Namun pers tidak bisa berharap dukungan publik tanpa berubah.
Pertama, tolong hentikan budaya clickbait. Saya ingin informasi, bukan jebakan. Judul yang menipu hanya akan membuat khalayak kapok membaca berita dan merendahkan wibawa jurnalistik.
Kedua, tolong jadikan akurasi sebagai nilai utama lagi. Saya bisa memaafkan kesalahan ketik, tetapi tidak bisa menerima jika kesalahan itu terjadi karena redaksi memilih kecepatan daripada ketepatan, atau menjauh dari kebenaran karena tekanan kuasa modal atau politik.
Ketiga, tolong tingkatkan transparansi. Bukankah sudah ada pedoman media siber dari Dewan Pers? Jika ada koreksi, lakukan secara jelas dan jujur. Jika ada konflik kepentingan, sampaikan. Kepercayaan lahir dari keterbukaan dan kejujuran.
Keempat, tolong berhenti menjadi corong kekuasaan. Jaman kiwari publik bisa melihat ketika berita dipoles sedemikian rupa termasuk karena kaitan kepemilikan media. Publik masa kini memiliki saluran informasi yang banyak.
Kelima, jurnalis perlu perlindungan dan kesejahteraan yang layak. Tidak mungkin kita mendapatkan berita berkualitas jika orang yang memproduksinya hidup dalam ketidakpastian. Dalam hal ini tentunya pimpinan perusahaan pers harus berpikir keras mencari model bisnis baru di era digital, termasuk pemanfaatan token digital atau supporting bisnis digital lain agar tidak bergantung pada pemberian kue iklan dari perusahaan digital multinasional. Artinya, tidak melulu mengikuti tren algoritma, usunglah elemen-elemen jurnalisme seperti disitir Kovach dan Rosenstiel.
TikTok, Instagram, dan YouTube bukan tempat terlarang, kuasai secara kreatif setiap fiturnya agar membangun social engagement. Atau sekarang ada platform baru yang kabarnya bebas bias dominasi Amerika Serikat seperti UpScrolled untuk memperluas jangkauan.
Penutup
Saya, seperti jutaan konsumen lainnya, masih memerlukan pers. Kami memerlukan media yang kembali menjalankan peran dan fungsinya. Jurnalisme yang tidak lelah mengungkap kebenaran, menjadi pelantang suara kelompok yang dibungkam atau tak mungkin bersuara. Pers yang berani kembali pulang kepada kepentingan warga dan bukan jongos penguasa. Redaksi yang siap menerima kritik dan tidak hanya mengritik pihak lain.
Jika itu terjadi, pers akan kembali memeroleh kepercayaan penuh dan dicari publik dengan dukungan penuh. Berlangganan karya jurnalistik yang bermutu dan membela kepentingan pelanggannya, tidak lagi dianggap buang-buang uang.
***
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

