MALIPIR #48: Membaca Lokatmala
Antologi puisi Lokatmala (2024) mengabadikan jejak kepenyairan Nita Widiati Éfsa pada puisi Sunda dalam masa hampir tiga dasawarsa.

Hawe Setiawan
Sehari-sehari mengajar di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra UNPAS, ikut mengelola Perpustakaan Ajip Rosidi. Menulis, menyunting, dan menerjemahkan buku.
14 Februari 2026
BandungBergerak.id – Salah satu kumpulan puisi yang sempat saya baca dalam beberapa pekan belakangan adalah Lokatmala (2024) karya Nita Widiati Éfsa. Buku ini terbit melalui tangan penyunting dari Cimindi, Didin Tulus, yang pada 2015 menerbitkan kumpulan cerita pendek karya ayah Nita, Djohar Éfsa (Éfféndi Saléh Asmadiredja).
Nita adalah penyair dan akademisi kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, tahun 1964 yang tinggal dan bekerja di Malang, Jawa Timur. Bukunya ini, dalam 97 halaman, menghimpun sekitar 60-an puisi. Puisi tertua berasal dari 1986, sedangkan yang terbaru dari 2014. Dengan kata lain, buku ini mengabadikan jejak kepenyairan Nita dalam masa hampir tiga dasawarsa. Setahu saya tidak banyak ibu yang sanggup berkreasi sedemikian lama dalam puisi Sunda. Kiranya ia tergolong yang terkuat di kalangan generasinya.
Sekiranya boleh saya memakai timbangan badan sendiri, ada alasan buat mengagumi dedikasi demikian. Bayangkan, misalnya, pada 1989, ketika saya masih runyam sebagai mahasiswa Unpad, orang seperti Nita yang belajar di IKIP (kini UPI) sudah sanggup menulis baris-baris berikut ini: "... Implengan mucuk dina buludru ibun/Anjeun sagara nu remen limpas ku cimata/Getih..." Waktu itu orang seperti saya pasti bilang, "Bukan main!" Bahasa figuratif demikian niscaya datang dari lingkungan asal, lingkungan sehari-hari, dan pilihan bacaan yang tersendiri.
Kata-kata tadi saya petik dari "Lokatmala", puisi yang judulnya dijadikan judul antologi ini. Lokatmala adalah nama tumbuhan jamu dari keluarga Artemisia. Daunnya meruncing dan memanjang serupa kujang. Dari kecenderungan lirik Nita, saya menduga lokatmala dalam buku ini mengacu pada nuansa tembang Cianjuran yang mengagumi keelokan pegunungan Priangan: "lokatmala marakbak baranang siang/ adumanis jeung cantigi... (lokatmala mekar terang benderang/bersanding dengan cantigi)". Setidaknya, ke dalam suasana itulah ingatan saya sendiri cenderung terpaut tiap kali mendengar nama lokatmala.
Kecenderungan yang saya maksudkan terisyaratkan dalam sajak pertama dalam antologi ini, "17 Oktober di Jurang 74". Sajak empat larik itu diakhiri dengan baris berikut: "Na kalbu uteuk ngawahan, cianjuran nyégétan rasa (Dalam batin nalar bertolak, cianjuran mengiris rasa)". Kalau boleh saya menduga-duga lagi, Bandung dasawarsa 1980-an kiranya merupakan tempat Nita menumbuhkan kreativitas berpuisi dengan orientasi estetik yang cenderung klasik. Dikatakan bahwa ia memilih Beethoven dan tembang Cianjuran.
Baca Juga: MALIPIR #45: Kampungmu dalam Bacaanmu
MALIPIR #46: Sketsa tentang Puisi
MALIPIR #47: Puisi Tujuh Belas Tahun
Bahasa dan Daerahnya
Nita menulis bukan hanya dalam bahasa Sunda, melainkan juga dalam bahasa Indonesia. Menurut catatan Téddi Muhtadin yang disertakan sebagai pengantar dalam antologi ini, karya Nita dalam bahasa Indonesia tampaknya diumumkan sebelum karyanya dalam bahasa Sunda. Dalam hal ini ia termasuk ke dalam golongan penulis dari Jawa Barat yang diberkati kesanggupan untuk berkarya dalam kedua bahasa itu–tidak seperti sebagian penulis setempat yang memilih salah satu di antara keduanya. Lagi pula, kalau kita melihat latar keluarga asal dan pendidikan formalnya, ia memang terdidik dan terlatih dalam bahasa dan sastra Sunda.
Terpaut pada bahasa, saya melihat satu hal yang menarik dari antologi ini. Salah satu sajak yang disertakan di situ berjudul, Ieu Kuring Mulang (Ini Aku Pulang), dengan dedikasi yang dikatakan "keur Sunda (buat Sunda)". Dari sajak yang digubah pada 2005 itu, samar-samar saya menangkap kesan bahwa buat Nita, Sunda kedengarannya bukan sekadar bahasa melainkan pula "sarakan", yang secara harfiah bisa berarti "kampung halaman" atau "tanah kelahiran" atau bahkan "tanah air". Sang aku yang bersuara dalam sajak itu, orang yang mendapati dirinya antara pergi menjauh dan datang kembali, antara lain berkata: "Tapi sarakan nu éndah ditéang saukur anjeun (Tapi kampung halaman yang indah dikunjungi semata engkau)".
Ada pula sajak yang lebih tua, dari tahun 1990, yang judulnya, Sunda. Idiom yang satu ini tampaknya mencerminkan tambatan harapan tersendiri, meski harapan itu datang dari diri yang dikatakan "teu manggapulia (tak berdaya)".
Dengan kata lain, dalam kaitannya dengan bahasa ibu dan daerah asal sang penyair, puisi Nita turut mewarisi suara yang lazim disampaikan oleh para pendahulunya, terutama mereka yang berkarya seusai Perang Dunia II. Suara generasi Pak Djohar rupanya turut merembes ke dalam lirik-lirik sang anak.
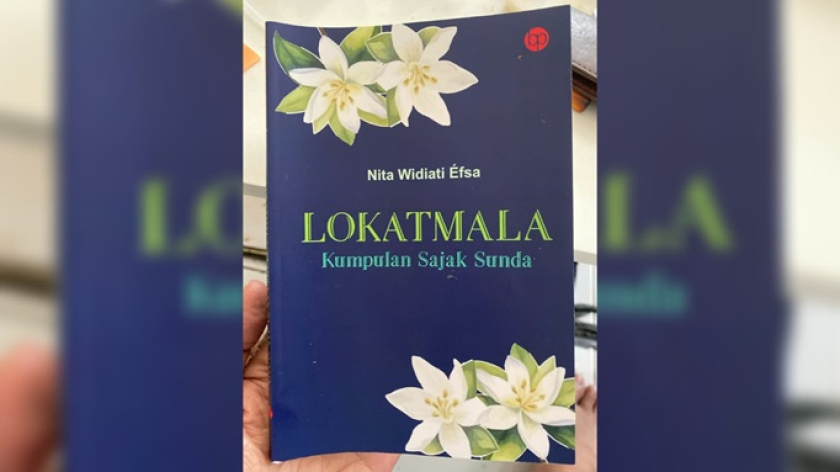
Pola dan Suaranya
Selayang pandang tampak beberapa pola: suara liris disampaikan sebagai "lagu", "surat", juga catatan atau renungan dalam "lalampahan (perjalanan)". Cinta, kerinduan, kesunyian, juga ketuhanan lazim jadi pokok persajakan. Suaranya sering kali membetot ke dalam diri, tapi ada kalanya tercurah ke lingkungan yang lebih luas.
Geografi puisinya meliputi, antara lain, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Tuban, Surabaya, Bali, Singapura, hingga Mekah.
Catatan perjalanannya, misalnya Sapanjang Jalan ka Bandung, bisa mendua arah: lukisan pemandangan tempat-tempat yang dilalui di satu sisi, dan refleksi pengalaman yang terpaut pada tempat-tempat tersebut di sisi lain. Ia melukiskan tempat-tempat yang kiranya terpaut pada biografi.
Ada pula metafora "lalampahan cinta (perjalanan cinta)" yang dipakai dalam dua sajak. Cinta yang diibaratkan sebagai perjalanan, dan sering jadi pokok persajakan, itu ada kalanya dikatakan bersifat "platonis" dan ada kalanya pula dikatakan sebagai "lalakon cimata (kisah air mata)".
Ada pula sajak tentang Palestina: Di Trafalgar Square Hiji Jangji: Palestina Merdéka. Barangkali sajak Nita tergugah oleh demonstrasi di Trafalgar Square, London, pada 20 Mei 2006, yang menyatakan solidaritas publik kala itu terhadap kemerdekaan Palestina. Hari ini, tatkala zionis Israel tiada hentinya melakukan genosida atas bangsa Palestina, teristimewa di Gaza, sajak ini patut dibaca lagi.
Pilihan saya dari kumpulan ini adalah Selecta, lukisan tentang seorang anak yang tertidur dari sudut pandang seorang ibu. Dalam lukisan itu sang anak, yang disapa sebagai "ratu sabuana (ratu sejagat)", ditamsilkan sebagai kuntum melati dalam rangkuman sanggul sinden.
Dengan itu semua, saya berharap puisi Téh Nita tidak berhenti di tahun 2014. Semoga akan terus bermekaran sajak-sajaknya dalam bahasa yang satu ini, terus dan terus, meski saya tahu bahwa menjadi dosen di Indonesia hari ini sering menguras tenaga yang sebetulnya kita perlukan buat puisi.
***
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB



