Pilih Bayar atau yang Gratis?
Pembajakan muncul bukan karena konsumen tidak mau membayar, tetapi karena akses legal tidak menyediakan pilihan yang terjangkau.
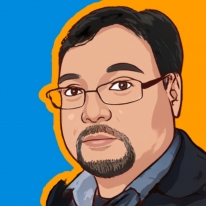
Mang Sawal
Praktisi komunikasi dan pembelajar pada Program Doktoral Unisba dengan fokus pada komunikasi sains. Aktif di berbagai kegiatan edukasi publik.
16 Februari 2026
BandungBergerak.id – Pada sebagian masyarakat, ada semacam ideologi normalisasi perbuatan buruk yang terbentuk akibat kemiskinan akut, yaitu: kalau ada yang murah mengapa harus yang mahal. Jika ada yang gratis, mengapa harus yang berbayar? Di Indonesia, ideologi itu menjadi iklim kondusif bagi pembajakan. Apa saja bisa dibajak di Indonesia. Tidak hanya sawah. Pada pelantar digital (digital platform) kulakan dalam jaringan (e-commerce), tanpa rasa malu terpampang beragam jenis produk bajakan, parfum, tas, sepatu, celana dalam, buku, obat, paket langganan nonton film, lisensi software, dst. Bahkan pengiriman paket belanja pun bisa dibajak di tengah jalan. Apa sih yang tidak bisa di Indonesia, iya kan?
Pembajakan memang bukan kelakuan khas Indonesia. Perusahaan riset MUSO yang memantau lalulintas digital pada tingkat dunia ke laman-laman berisi barang bajakan atas produk film, penerbitan, musik, software, mengungkap, Amerika Serikat dan Rusia-lah negara dengan jumlah pengguna (user) terbesar yang mengunjungi laman berisi produk bajakan. Kemudian mereka menjual kembali bajakan itu ke daerah dengan akses internet terbatas. Indonesia, menurut data itu, berada jauh di bawah AS, tetapi masih signifikan, peringkat 12 (MUSO, 2024). Kalau korupsi sih memang nomor wahid, tak terkalahkan Indonesia mah.
Ada 229,4 miliar kunjungan ke laman berisi barang bajakan pada 2023 dan sekitar 216,3 miliar pada 2024. Dengan konten film televisi dan penerbitan digital sebagai produk yang paling banyak dibajak di pelantar digital, sementara film bioskop, software, dan karya musik cenderung menurun karena banyak opsi “saluran lain” yang tersedia selain mengunduh bajakan (MUSO, 2023 Piracy by Industry Data Review; MUSO, 2024 Piracy Trends and Insights). Pada sektor karya musik, menurut laporan organisasi industri rekaman dunia, IFPI, 26 persen menggunakan layanan “stream‑ripping” untuk mengubah audio dari video, menjadi file yang bisa disimpan dan diputar berulang-ulang, tanpa harus bayar langganan (IFPI, Engaging with Music, 2023).
Konteks Indonesia memang menarik. Di tingkat dunia, tercatat bukan pengunjung terbesar ke laman produk bajakan global. Namun pembajakan produk lokal, luar biasa masif. Industri yang rusak parah akibat pembajakan adalah penerbitan buku. Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Arys Hilman mengatakan, 60 persen buku di Indonesia telah dibajak, kerugiannya bisa mencapai lebih dari Rp116 Miliar setahun. Padahal sudah ada jalur legal yang sebenarnya mudah diakses, yaitu e‑Resources Perpusnas yang memberi akses gratis kepada anggota Perpustakaan Nasional untuk berbagai jurnal dan e‑book berlisensi. Melalui aplikasi iPusnas masyarakat dapat dengan mudah membaca buku digital secara legal (perpusnas.go.id). Faktanya berbagi PDF buku teks kuliah di grup-grup Telegram masih menjadi praktik umum. Dalam rilis Ikatan Penerbit Buku Indonesia (IKAPI) berjudul “Darurat Pembajakan Buku!”, praktik pembajakan, baik fisik maupun digital, disebut telah berlangsung lebih dari 40 tahun dan makin parah di era kulakan dalam jaringan dan buku digital.
Dalam konteks pembajakan buku, sebagian pihak melihat pembajakan bukan sebagai tindakan mencuri, melainkan sebagai tindakan "yang perlu" untuk pemerataan pengetahuan. Semacam tindakan altruistik. Contoh paling fenomenal adalah Sci-Hub, yang didirikan oleh Alexandra Elbakyan. Hingga tahun 2024, platform ini menyediakan akses gratis ke lebih dari 88 juta artikel ilmiah. Elbakyan berargumen bahwa membatasi akses terhadap ilmu pengetahuan adalah pelanggaran Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Sci-hub, Database, 2024). Sci-hub sendiri berjejaring dengan pelantar digital khusus pengepul (agregator) produk penerbitan, Anna’s Archive.
Baca Juga: AI dan Renungan tentang Kemanusiaan
Teror Pertanyaan Kapan Nikah Menjelang Lebaran
Masih Adakah Pers Indonesia
Pembajakan: Halal atau Haram?
Produksi film, riset ilmiah, merekam musik, menulis buku, menyusun kode software, semuanya memakan waktu, tenaga, dan uang. Ketika distribusi ilegal mengambil alih dukungan finansial khalayak, beban kreator makin berat. Industri hiburan baru-baru ini memberi contoh bagaimana produksi film dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) memaksa negosiasi ulang batas-batas etika industri kreatif. Gilda aktor Amerika Serikat (SAG‑AFTRA) kini mewajibkan adanya persetujuan dan kompensasi bila studio membuat atau menggunakan “replika digital” wajah atau suara aktor dalam karya buatan AI (authorsguild.org). Gilda penulisnya (WGA) menegaskan AI bukan penulis, sehingga naskah yang dihasilkan mesin tidak bisa dipakai untuk menghapus nama penulis dari daftar kredit sebuah film dan mengurangi standar bayaran penulis manusia. Di Indonesia, para konten kreator baru saja membentuk organisasi AKKSI, belum bergigi, sementara AI sudah mulai digunakan dalam program berita TV dan film sinetron. Jadi, sikap para pekerja kreatif Amerika Serikat yang gigih itu, mengingatkan para pekerja kreatif bahwa ancaman hari ini tidak selalu berbentuk file .mp4 bajakan, tetapi juga berupa penggandaan suara dan bentuk rupa tanpa persetujuan kreator oleh para majikan pembuat karya itu sendiri, dengan pesuruh setia bernama AI.
Dunia akademik pun punya persoalan serupa, meskipun polanya berbeda. Banyak perpustakaan mengeluhkan paket langganan penerbit jurnal raksasa, sering disebut “Big Deal”, yang harganya terus naik dan memaksa kampus memilih antara membayar langganan ratusan dolar AS atau memutus akses terhadap sumber kajian literatur riset-riset mereka. Studi tentang “Big Deal” menunjukkan nilai yang didapat kampus sering tidak sebanding dengan biaya langganan, karena hanya sebagian kecil jurnal yang benar-benar dikutip atau dipakai intensif dalam sebuah penelitian (Shu, dkk., Is It such a Big Deal? On the Cost of Journal Use in the Digital Era, 2018). Diskursus ini memicu munculnya gerakan akses terbuka (disingkat OA, open access), supaya publik bisa mengunduh artikel ilmiah tanpa perlu membayar (paywall). Tetapi implementasinya seperti jalan tol di Indonesia, tidak mulus, penuh hambatan, sehingga jalan belakang seperti Sci-Hub menjadi pilihan.
Pembajakan adalah Perlawanan
Manusia belajar dengan cara yang tidak sama, termasuk dalam memperoleh sumber belajarnya. Bagi sebagian mahasiswa dan peneliti dengan sumber daya terbatas, Sci‑Hub dianggap “penyelamat” dari paywall yang mahal. Bagi penerbit, inilah pencurian besar-besaran. Terlepas dari perbedaan sudut pandangnya, angka pengakses laman Sci‑Hub menunjukkan satu hal: kesenjangan akses terhadap pengetahuan itu nyata luar biasa.
Adalah sebuah fakta, industri penerbitan ilmiah cenderung oligopolistik, sebab hanya beberapa pemain besar yang menguasai pasar jurnal dan memonetisasi lewat biaya langganan maupun biaya pemrosesan artikel (APC) yang dipungut dari penulis artikelnya untuk jurnal OA. Riset Butler menunjukkan penerbit besar menikmati keuntungan finasial yang tinggi, sementara perpustakaan kampus kerap menanggung besarnya biaya langganan (Butler et al., The oligopoly’s shift to open access, 2023). Dampaknya sangat terasa di negara berkembang, di mana biaya “artikel per unduh” atau langganan tahunan berada jauh di atas kemampuan anggaran kampus apalagi gaji dosen. Sehingga “jalur lain” dianggap perlawanan terhadap dominasi pasar.
Di luar konfrontasi itu, sebenarnya ada solusi yang sudah berjalan. Program Research4Life, termasuk inisiatif HINARI yang dikelola WHO untuk bidang kesehatan, memberi akses gratis atau berbiaya rendah bagi kampus di negara berpendapatan rendah-menengah. Ini contoh konkret tiered pricing atau harga berjenjang sebagai upaya memperkecil jurang akses dan mengurangi pembajakan.
Sementara itu, karya budaya masih berada di wilayah abu-abu. Jika selembar film seluloid mulai lapuk atau sebuah pita kaset satu-satunya hampir putus, menyalinnya ke format digital bisa menyelamatkan sejarah. Hukum hak cipta di Amerika Serikat memberi pengecualian khusus kepada perpustakaan atau pengarsip untuk menggandakan karya tertentu demi keperluan preservasi dengan syarat akses publiknya tetap dibatasi agar dapat memelihara kemungkinan menghargai jerih payah pencipta karya budaya.
Indonesia tidak ada regulasi semacam itu. Hak cipta atau kekayaan intelektual, menjadikan karya cipta sebagai hak milik mutlak, sehingga karya budaya yang terancam punah bisa jadi ikut terbawa mati bersama pemiliknya. Atau realitas berbeda seperti di Sinematek Indonesia. Lembaga arsip film nasional ini menyimpan ribuan judul tetapi sudah lama menghadapi keterbatasan dana, fasilitas, dan sumber daya manusia untuk konservasi dan digitalisasi. Banyak akademisi dan komunitas film terlibat membantu, namun kebutuhan melampaui kapasitas (Annissa, A.BR & Putranto, WA, Preservasi Arsip Film Seluloid di Sinemetak Indonesia dalam Upaya Melestarikan Warisan Budaya, 2020). Pada ranah naskah kuno, sejumlah komunitas lokal dan Perpusnas menggelar pelatihan alih media dan katalogisasi agar manuskrip nusantara tidak hilang ditelan waktu.
Di tingkat lokal, juga ada inisiatif digitalisasi sebagai upaya preservasi, seperti pelantar digital Sunda Digi yang menghadapi persoalan sama. Menurut pengurus Pusat Studi Sunda, Rahmat Taufik, kepada penulis, sejak dibangun tahun 2023, digitalisasi karya budaya Sunda belum mencapai 70 persen dari bahan yang dikelola Sunda Digi. Sementara karya budaya yang belum dikelola masih lebih banyak lagi. Jumlah sumber daya tidak berbanding lurus dengan laju kepunahan budaya yang ada. Sekaligus terdapat sisi kritis dari ketiadaan regulasi, yaitu perlindungan atas karya budaya yang telah didigitalisasi terhadap pembajakan. Sunda Digi misalnya, telah berulang kali mengalami upaya pembobolan bank data. Kemungkinan data artefak budaya itu memiliki potensi sebagai aset digital, entah dalam bentuk mentah atau menjadi token seperti NFT.
Garis besarnya jelas: ketika negara tidak menyediakan dukungan untuk pelestarian dan perlindungan hukum, maka unsur-unsur budaya itu diam-diam menghilang atau artefaknya dimiliki oleh kelompok kuasa tertentu di luar kelompok budaya itu sendiri. Seperti saat ini, banyak artefak sejarah Indonesia berada di negara lain. Kita harus meminjam kepada mereka untuk mempelajarinya.
Mencari Jalan Tengah
Pembajakan adalah respons rasional terhadap institutional failure, kegagalan pasar menyediakan akses yang wajar, kegagalan regulasi mengakomodasi realitas sosio-ekonomi, dan kegagalan masyarakat mengakui nilai kerja kreatif. Solusi efektif bukan pengawasan ketat dan memperberat hukuman, tetapi mengubah struktur insentif sehingga pilihan legal menjadi pilihan yang paling mudah, paling masuk akal, dan paling memberikan manfaat.
Pembajakan muncul bukan karena konsumen tidak mau membayar, tetapi karena akses legal tidak menyediakan pilihan yang terjangkau. Pengguna konten hiburan memakai stream-ripping untuk memenuhi kebutuhan kendali penuh atas konsumsi yang tidak dipenuhi aplilkator. Membatasi akses terhadap konten berkualitas dengan harga tinggi adalah bentuk kekerasan simbolik yang melanggengkan stratifikasi sosial dan mendorong perlawanan sosial melalui pembajakan.
Contoh ironis adalah pembajakan software justru mempercepat adopsi teknologi dan menciptakan network effects yang menguntungkan vendor dalam jangka panjang, sekaligus indikasi bahwa model bisnis berbasis lisensi berjangka sudah jenuh. Baudrillard (1981) pernah menyitir, manusia memiliki barang bukan karena fungsinya tetapi status sosial. Pembajakan menawarkan "affordable signaling to be associated with brand".
Penutup
Pembajakan tidak akan pernah hilang 100 persen, akan selalu ada free riders dan hardcore pirates. Tetapi kita dapat mengurangi pembajakan dari "banyak yang melakukan" menjadi "kelompok kecil", dari "biasa aja" menjadi "malu dong". Masyarakat sebenarnya mau melakukan yang benar. Mereka hanya perlu diberi akses yang mudah, murah secara relatif dan paling memberi manfaat, maka pembajakan akan kehilangan daya tariknya. Yang juga penting, kreator mendapatkan penghargaan yang adil atas karya mereka, sehingga dapat terus berkarya dan memperkaya kemanusiaan. Penulis sendiri berpandangan, yang harus dimurka adalah perusahaan multinasional dengan kekayaan luar biasa yang terus membajak karya pekerja kreatif miskin.
***
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB


