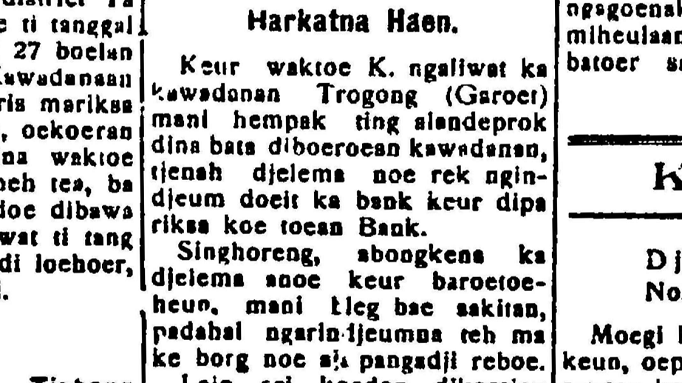SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #33: Bangsa Haen dan Bangsa Herman
Siptahoenan menggunakan kata Haen singkatan dari Marhaen dan Herman merujuk pada bangsa Belanda termasuk kalangan bangsawan yang berkuasa sebagai kontras pembeda.

Atep Kurnia
Peminat literasi dan budaya Sunda
16 September 2023
BandungBergerak.id – Dalam perkembangannya, istilah Marhaen, yang diperkenalkan Sipatahoenan sejak 1926, kerap kali disingkat menjadi Haen. Kata tersebut biasanya didahului dengan sapaan “Ki”, “Bangsa”, “Si”, “Kaom” dan lain-lain. Kata Haen biasanya digunakan untuk membuat kontras dengan kalangan bangsawan, tetapi lebih banyak dengan bangsa Belanda (Herman).
Mari kita telusuri bukti-buktinya. Oea Nany menyatakan (“Beurang djeung Peuting” dalam Sipatahoenan, 6 Maret 1928): “Taroehan, sasen lawan saketip, lamoen koerang behoeftena bangsa Ki Haen, anggoeranan leuwih tea. Kapan ti bareto oge koe koering mindeng didadarkeun dina Sip” (Mari bertaruh, satu sen lawan satu ketip, daripada kebutuhannya bangsa Ki Haen berkurang, pasti akan lebih. Kan sejak dulu pun saya kerap menjelaskannya dalam Sipatahoenan). Kemunculan kata Ki Haen dalam tulisan tersebut untuk mengkritisi Tuan Zeilinga, yang notabene bangsa Belanda dan bekas presiden Javasche Bank.
Oea Nany kembali lagi dengan tulisan “Bitjara Helfferich” (Sipatahoenan, 31 Juli 1928) tentang orang Jerman yang tadinya miskin tetapi setelah berusaha di Indonesia menjadi kaya sekali (“Nja boekti geuning manjisian, djati kasilih koe djoenti. Di kota kota redes bangsa asing, da moen koeli atoeh ngaratoes ngareboe, moen dagang modal ngalaksa, ari Haen mah pakatjar toekang ‘itoe tjokot ieu bawa’”).
Kata “Bangsa Haen” saya temukan dalam berita “Pikarisieun” (Sipatahoenan, 4 Maret 1930). Di situ tertulis, “Djisim koering teu kinten moedjina ka pamarentah desa, babakoena ka Djoeragan Tjamat Panawangan anoe sakitoe soson sosonna kana ngalereskeun, sareng moegi-moegi saterasna hemanna ka bangsa Haen teh” (Saya sangat memuji pemerintah desa, terutama Tuan Camat Panawangan yang sangat bersungguh-sungguh memperbaiki, dan semoga menerus kasih sayangnya kepada bangsa Haen).
Dalam “Bedryfscontingenteering” (Sipatahoenan, 10 Oktober 1934) dikatakan “Oepami dilenjepan mah bangsa Haen nepikeun ka kiwari, estoening djadi toeschouwer [noe laladjo] maloeloe dina sagala atoeran economie atawa handel teh” (Bila diresapi, bangsa Haen hingga kini sungguh hanya menjadi penonton belaka dalam segala urusan ekonomi dan perniagaan). Demikian pula dalam kalimat sindiran “Sing pertjaja, groote Europeesche ondernemingen teh moal nepi ka tega moepoel oentoeng samemeh boeroeh pagawena – babakoena bangsa Haen – diomean” (Percayalah, perkebunan-perkebunan milik bangsa Eropa yang besar takkan tega mengambil untung sebelum para buruhnya, terutama bangsa Haen, diperbaiki) (“Woorden …”, Sipatahoenan, 27 April 1937).
Berikutnya, kata “Si Haen” bisa dibaca dari tulisan “Patjet Rotjet. Sindanglaja tambah Kaperlaja” (Sipatahoenan, 12 Mei 1930). Pada paragraf awal tertulis, “Geus puguh kaom sanah eta rea doeitna kahajangna teh rek hantem bae meulian of njewaan tanah keur ondernemingen meakeun si Haen, dalah di bangsa oerang oge rea keneh pisan noe harawek teh, teu inget ka si Tjilik. Malah ieu mah noe rek ditjatoerkeun teh lalakon hidji Ningrat noe Hermanachtig” (Sudah tentu kaum sana [Belanda] banyak uang, keinginannya terus membeli atau menyewa tanah untuk perkebunan, sehingga menghabiskan [jatah] Si Haen, bahkan bangsa bumiputra pun banyak sekali yang serakah, tak teringat kepada si kecil. Bahkan yang akan diceritakan di sini adalah kisah tentang seorang bangsawan yang berkuasa seperti bangsa Herman).
“Si Haen” bisa juga muncul dalam “Keras Contra Keras” (Sipatahoenan, 30 Juni 1930), yaitu pada kalimat-kalimat sindiran sebagai berikut: “Koe pangersa noe kawasa Herman (tjek AID Jansen) maratoeh di dieu; koe sabab Herman teh meneer Herman. Koe sabab Herman teh ditangtoekeun keur Si Haen, njieunan gedong, njieunan solokan solokan, koe sabab Herman nangtajoengan Haen dina kateuoenianana enz, enz. (Dengan kehendak yang kuasa Herman [kata AID Jansen] menetap di sini; karena Herman adalah Tuan Herman. Sebab Herman ditentukan bagi Si Haen, untuk membuat gedung, membuat selokan-selokan, sebab Herman melindungi Haen dalam hal ketidakberesannya, dll, dll)”
Selanjutnya Oea Tynah menyajikan “Kaom Haen” dalam “Kotjeak Oerang Padesan” (Sipatahoenan, 16 Mei 1931). Katanya “Nja kitoe deui dina lobana panganggoeran, boh kaom Europa, boh kaom Haen anoe geus malangarti, teu woedoe mindeng pada ngadadarkeun, dipahadrengkeun dibadamikeun koemaha pioebareunana” (Demikian pula dalam hal banyaknya pengangguran, baik kaum Eropa maupun kaum Haen yang berpendidikan, kerap kali diuraikan, didiskusikan bagaimana solusinya).
Baca Juga: SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #30: Soeriadiradja, Redaktur di Batawi
SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #31: Turut Mendirikan Persatoean Djoernalis Indonesia
SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #32: Asikin, Abas Nataadiningrat, dan Kosim
Bangsawan dan Belanda
Dari berbagai kutipan di atas, saya mendapati kontras yang dibuat para penulis dan redaksi Sipatahoenan untuk membandingkan posisi Haen dengan kalangan bangsawan dan bangsa Belanda (yang disebut Herman), termasuk kalangan bangsawan yang berkuasa seperti halnya orang Belanda (“Ningrat noe Hermanachtig”).
Mengenai kontras antara kalangan bangsawan dan Marhaen (Haen) bisa dibaca dari tulisan Saepi yang berjudul “Pasoendan Batawi” (Sipatahoenan, 13 Maret 1928). Di situ Saepi mengatakan “Ari koe kitoe tea mah da lain djamanna, hidji pagoejoeban anoe rek ngoedag kamerdikaan lemah tjaina, make rek ngabeda beda NINGRAT djeung MARHAEN, da poegoeh oge ari geus koemboeh djadi hidji mah euweuh NINGRAT euweuh MARHAEN, saroea bae” (Bagaimanapun bukan zamannya lagi, satu paguyuban yang hendak mengejar kemerdekaan tanah airnya tetapi mau membeda-bedakan antara ningrat dengan Marhaen, karena tentu saja bila sudah bercampur gaul menjadi satu, tidak ada ningrat, tidak ada Marhaen, sama saja).
Dalam tulisan “Patjet Rotjet. Sindanglaja tambah Kaperlaja” (Sipatahoenan, 12 Mei 1930) penulis yang mengatasnamakan dirinya No Wahid mengkritisi tindakan seorang wedana yang mengambil tanah orang Eropa yang sudah lama tidak digunakan, dan sudah menjadi hak milik umum, bukan untuk keperluan rakyat kebanyakan (Haen).
Cerita lain lagi ada pada catatan kaki untuk rubrik “Ti Pipir Hawoe” pada edisi 26 Juni 1930. Catatannya berbunyi “Ajana ieu tjaritaan (soeal djawab) antara boedak djeung Abah, sanggeus kadjadian aja hidji menak (pangkat loehoer) bendoe pohara ka hidji Haen, lantaran teu dipangtepakdekoekeun dina waktoe njarita” (Adanya cerita ini [soal jawab] antara anak dan Abah, adalah setelah adanya kejadian seorang bangsawan [berpangkat tinggi] yang marah sekali kepada seorang Haen, sebab dia tidak merundukkan tubuhnya saat berbicara).
Satu contoh lagi dalam laporan bertajuk “Pasar Gambir” (Sipatahoenan, 28 Agustus 1936) yang paragraf awalnya dimulai dengan kalimat-kalimat sebagai berikut “Sakoemaha biasa, oenggal taoen dina panoengtoengan minggoe boelan Augustus, lapang Koningsplein anoe sabeulah koelon, djadi tempat anoe sakitoe ramena. Sa-Batawi, ti Si Haen ka Sang Ningrat, ti noe leutik nepi ka noe gede, toemplek-toembleg … (Sebagaimana biasa, setiap tahun pada akhir minggu bulan Agustus, sebelah barat lapang Koningsplein menjadi tempat yang sangat ramai. Dari seantero Batavia, dari Si Haen hingga Sang Ningrat, dari orang kecil hingga orang besar, tumplek)”
Namun, yang paling banyak tentu saja, kontras antara Marhaen dan Haen dengan Herman. Ezel, misalnya, dalam tulisannya “Economie di Banten” (Sipatahoenan, 4 April 1930) menggunakan kata Marhaen untuk membuat perbandingan ekonomi antara bumiputra dengan Tionghoa dan Herman. Nasib bumiputra antara lain digambarkannya sebagai berikut: “Lain manawi, tapi enja aja oelah asa-asa pok bae aja kitoeh, boga bangsa deungeun, da bangsa oerang mah ngan djadi koelina bae, toer padahal noe digolangkeun teh, hasil boemi oerang priboemi; noe migawena oerang priboemi, ngan oentoengna keur batoer, boh oerang Tionghoa boh Herman” (Bukan barangkali, tetapi betul ada, jangan khawatir, katakan saja ada, punya bangsa asing, sebab bangsa kita hanya menjadi kulinya belaka, padahal modal yang mereka putar, hasil bumi bangsa bumiputra; yang mengerjakannya bumiputra, tetapi keuntungannya untuk orang lain, baik untuk orang Tionghoa maupun Herman).
Dalam berita “Kasoesahan Hal Imah” (Sipatahoenan, 26 Maret 1930) yang intinya mengenai kesusahan mempunyai rumah di Batavia, ternyata tidak saja dialami oleh bumiputra, melainkan juga oleh bangsa Herman (“Ieu kasoesahan lain di oerang priboemi bae, dalah di kaom Herman oge saroea bae”). Salah satu sebabnya, konon, harga sewa rumah terus dinaikkan. Demikian pula para anggota dewan Kabupaten Cianjur yang digambarkan dalam berita “R.R. Tjiandjoer” (Sipatahoenan, 9 Januari 1931) terdiri atas bangsa Herman, Tionghoa, dan Haen (“Sabadana, noe pangheulana kagiliran njetem nja eta lid Herman, geus kitoe ditema koe Tionghoa, panoetoepna lid Haen”).
Yang mengerikan, kabar pejabat bangsa bumiputra (Haen) di daerah Pekalongan dan Cirebon, konon, harus menyebut “gusti” kepada pejabat bangsa Belanda (Herman) bila menggunakan bahasa Melayu. Dalam “Bebe Priboemi di Volksraad” (Sipatahoenan, 12 Agustus 1932) dikatakan “Tjenah aja deui kadjadian, di Pakalongan djeung Tjirebon lamoen ngomong basa Malajoe sok make ketjap ‘goesti’, si bebe Haen ka bebe Herman”).
Marhaen itu Orang Sunda
Dari uraian di atas, kata Haen sebagai singkatan dari Marhaen dan Herman yang merujuk kepada bangsa Belanda tentu saja merupakan cerminan dari kebijakan redaksi Sipatahoenan untuk menggarisbawahi perbedaan budaya, nilai, dan jatidiri antara bangsa bumiputra Indonesia yang terjajah dan bangsa Belanda penjajahnya. Dengan kata lain, penggunaan kata Haen dapat dikaitkan dengan konteks nasionalisme yang dianut oleh para anggota dan pengurus Paguyuban Pasundan, penerbit Sipatahoenan, untuk mempertebal identitas nasional, sekaligus penanda untuk melawan dominasi penjajahnya.
Itu sebabnya, dapat dimengerti, bila dalam Sipatahoenan, ada beberapa penulis atau kontributor yang sengaja menggunakan nama samaran Haen untuk tulisan yang mereka hasilkan. Misalnya tulisan “Pagoeron Normaalschool” (Sipatahoenan, 26 Januari 1929) yang ditulis oleh Haen, demikian pula dengan tulisan dalam rubrik “Pagoejoeban Sagawe” dengan tajuk “Onderneming Personeel Naha Rehe” (Sipatahoenan, 3 Juni 1931) yang juga ditulis oleh Haen.
Judul-judul tulisan di Sipatahoenan banyak pula yang menggunakan kata Haen dan Marhaen. Yang berhasil saya temukan antara lain “Harkatna Haen” (Sipatahoenan, 11 Maret 1931), “Bijdrage Marhaen ka Nagara” (Sipatahoenan, 13 Oktober 1932), “Nasibna Si Haen” (Sipatahoenan, 7 Desember 1934), dan “Hiroep Haen di Desa” (Sipatahoenan, 2 Februari 1935).
Di luar Sipatahoenan, bahkan, konon, sempat ada surat kabar mingguan berbahasa Sunda yang menggunakan kata Marhaen. Keterangan ini, saya dapatkan dari berita “Weekblad Marhaen” (Sipatahoenan, 14 April 1932). Menurut kabar, hari itu di Jakarta terbit mingguan yang namanya disebut dalam judul, dengan menggunakan bahasa Sunda, dan pengelolanya sebuah badan komisi redaksi (“Meunang bedja poe ieu di Djakarta ngaloearkeun weekblad noe titelna saperti di loehoer. Ieu soerat kabar basana basa Soenda. Pingpinan ditjekel koe hidji badan commissie van redactie”).
Apakah ini juga menjadi pertanda bahwa kata Marhaen berasal dari nama orang dan bahasa Sunda? Bisa disebutkan memang demikian. Dua buktinya saya temukan dalam buku Di Padesan (1926) karya H. Schroo dan Raden Djajadiredja dan buku Loetoeng Kasaroeng: een mythologisch verhaal uit West-Java (1949) karya F.S. Eringa.
Dalam Di Padesan, nama Marhaen digunakan sebagai orang yang bekerja sebagai petani penggarap yang bekerja untuk ayah tokoh Soebandi (“Dina bidji poë djoeng manehna njampeur oelin barang gok papanggih katjida saronoëunana. Soebandi kasampak keur tjangogo deukeut Marhaen panjawah bapana keur diadjar nganjam, tapi lain nganjam samak, ieu mah njieun wawajangan koe gagang këmbang djoekoet”). Sementara dalam daftar pustaka yang digunakan F.S. Eringa, saya mendapati bahwa orang bernama Marhaen telah menulis artikel berjudul “Dialect Loeragoeng: Kagegelan ti poen Marhaen Tjibolerang” dan dimuat dalam majalah Poesaka Soenda (1926).