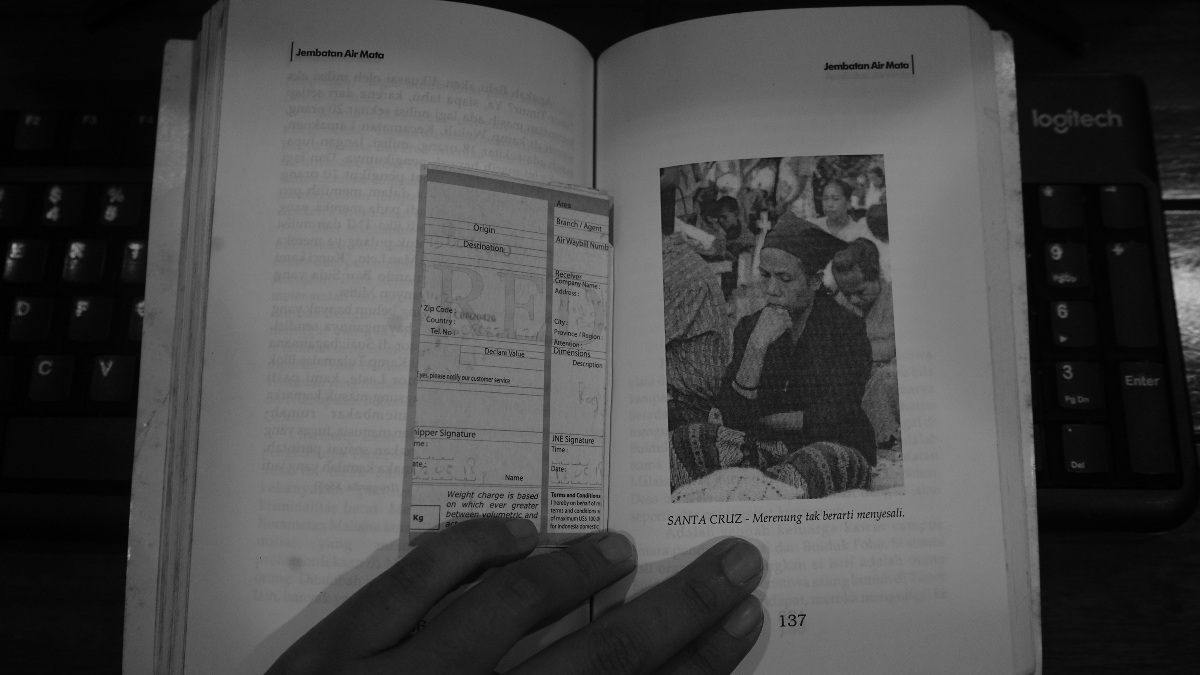Marka Buku buat Hidup Santuy
Dengan marka buku, saya selalu dibuat sadar akan adanya jagat di mana saya tidak harus terburu-buru.

Hawe Setiawan
Sehari-sehari mengajar di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra UNPAS, ikut mengelola Perpustakaan Ajip Rosidi. Menulis, menyunting, dan menerjemahkan buku.
25 Januari 2025
BandungBergerak - Tidak seperti melahap kerupuk, jarang saya menamatkan buku sekali duduk. Buku saku tipis Tao Te Ching terjemahan David Hinton kelihatannya bisa dilahap dalam waktu singkat. Nyatanya tidak begitu. Sering saya termenung-menung di satu halaman. Saya perlu jeda dengan menandai batas baca. Marka buku (bookmark) jadi tanda perhentian sementara atau tonggak perjalanan yang tertunda.
Kalau saya membaca buku sebelum tidur, biasanya baru jalan satu-dua paragraf saja mata sudah terkantuk-kantuk. Kata-kata yang tercetak terasa berjatuhan menimpa kelopak mata. Dalam keadaan seperti itu marka buku tak ubahnya dengan Syahrazad yang menjanjikan kelanjutan cerita esok malam.
Namun, ada kalanya marka buku membuat diri saya hampir putus asa. Itu dialami ketika saya membaca Romance of Three Kingdoms, terutama ketika jeda membaca kelewat lama. Begitu banyak tokoh di dalam cerita klasik tersebut dengan nama-nama diri yang tidak ramah dengan lidah Indonesia. Tiap kali mau meneruskan pembacaan, saya mesti balik lagi ke awal cerita: “Empires wax and wane...” dan seterusnya.
Kreativitas dalam Budaya Kertas
Dalam wujud fisiknya, ada dua jenis marka buku. Ada marka buku yang melekat pada punggung buku, lazimnya berupa pita halus lagi tipis yang salah satu ujungnya bercagak kayak lidah ular. Lazimnya, marka buku seperti ini terdapat dalam buku hard cover, seperti kitab suci atau buku saku buat cendera mata. Bentuk inilah yang kiranya dijadikan model bagi marka buku digital yang bisa kita klik dalam buku-buku elektronik. Ada pula marka buku yang terlepas dari buku seperti yang sekarang sering kita pakai, biasanya dari kertas selebar dua jari.
Sering saya memanfaatkan etiket belanjaan sebagai pembatas halaman. Benda kecil itu tipis dan ringan, tapi tidak lemas. Sayang kalau dibuang. Tak sedikit yang desain grafisnya bagus. Ada kalanya marka buku memakai uang kertas yang nilai nominalnya kecil. Kalau dipakai membaca buku tebal, lembaran uang yang tadinya kusut jadi mulus seperti habis disetrika ketika kita tamat membaca. Pernah pula dari sebuah buku bekas saya mendapatkan secarik amplop putih kecil bergambar Villa Isola yang ternyata berisi surat cinta.
Kiranya, saya tergolong pembaca yang senang memelihara kemulusan buku. Golongan pembaca lainnya suka melipat halaman buku, alih-alih memberinya marka buku. Dalam bahasa Inggris, perbuatan seperti itu disebut dog-earing: melipat sudut halaman buku sehingga bentuknya mirip kuping anjing. Waduh, kalau membacanya banyak jeda, niscaya lipatan di sudut halaman banyak juga. Cacat dong!
Kita tahu bahwa dalam sejarahnya halaman buku baru dikasih nomor belakangan. Pada mulanya lembaran manuskrip atau buku tidak dikasih nomor. Bayangkan, jika kita membaca buku tanpa nomor halaman, tentu kita memerlukan marka buku untuk menandai halaman terakhir yang telah kita baca.
Memang, marka buku bisa membuat kita lupa pada nomor halaman. Waktu keluar dari teks, kita tidak lagi merasa perlu mengingat-ingat nomor halaman buku yang kita tinggalkan. Akibatnya, kalau marka buku terlepas, kita jadi repot. Namun, buat saya, marka buku lebih banyak memberikan manfaat ketimbang menimbulkan mudarat.
Marka buku menyediakan peluang kreativitas. Dalam budaya kertas, benda kecil yang satu ini bisa jadi bagian dari seni lipat-melipat dan hias-menghias seperti origami. Bisa juga marka buku dimanfaatkan pula sebagai medium informasi atau bahkan olah seni. Pernah saya mendapatkan hadiah marka buku dari kulit tipis dengan dekorasi wayang.

Baca Juga: Dari Baghdad ke Bandung, Menyuarakan Kemanusiaan di Palestina Lewat Kesusastraan
Mengupas Novel Klasik Sebagai Syarat Lulus Mata Kuliah Kritik Sastra Unpas
Tidak Harus Terburu-buru
Buat saya, marka buku kiranya turut membuktikan bahwa membaca buku pada dasarnya merupakan kegiatan nan lambat. Selalu perlu waktu untuk bergerak dari pendahuluan menuju kesimpulan, dari awal hingga akhir cerita. Tidak terburu-buru. Manusia literat tidak pernah cepat-cepat mau tamat. Niscaya orangnya sabar. Dalam proses membaca, selalu ada jeda, dan itulah yang ditandai dengan marka buku.
Sekarang zaman distraksi digital. Banyak orang tampaknya kian suka melahap tulisan ringan lagi singkat dengan hanya satu-dua kali mencolek layar ponsel: postingan viral, cuitan terkini, unduh cepat dari satu ke lain laman. Apakah keterampilan membaca buku yang sabar dan menyita waktu sedang berakhir? Ketika kita jadi terburu-buru, jangan-jangan membaca lambat sedang beringsut ke masa lalu. Saya tidak tahu. Buat saya, membaca buku merupakan alternatif dari berselancar dengan internet.
Dalam penglihatan saya, lingkungan kerja sehari-hari kini didominasi oleh watak Sangkuriang: maunya serba cepat, efisien, dan produktif. Tidak ada waktu buat kontemplasi, meditasi, menyepi. Hal yang disebutkan belakangan rasanya lebih dekat ke watak Kabayan: lambat, banyak melamun, dan, tentu saja, tidak produktif. Watak Kabayan cocok nian dengan kegemaran membaca buku.
“Lambat berarti menjelajah. Buku yang baik menjangkau diri kita, mengendap dalam diri kita, dengan kelembutan dan kekuatan yang datangnya bertahap (Slowness means discovery. A good book dawns on us, and within us, with gradual sweetness and strength),” tulis David Mikics dalam Slow Reading in a Hurried Age, buku buat para pecinta buku untuk tetap anteng membaca secara mendalam di tengah tsunami konten dewasa ini.
Sewaktu-waktu, kita bisa keluar dulu dari jagat komunikasi berinternet yang tiada hentinya mengirim notifikasi hingga perhatian kita terbagi-bagi. Dengan memutus wifi atau memilih mode pesawat, saya bisa memusatkan perhatian kepada buku yang saya cintai. Dengan begitu, saya bisa berdialog dengan pengarang, membuka diri bagi tokoh cerita, masuk ke dalam gugusan gagasan, secara tenang dan anteng. Itulah pengalaman membaca yang kiranya tidak tergantikan oleh cuitan dan postingan media sosial.
Marka buku adalah tanda pengingat yang bersahaja mengenai sejauh mana kita sanggup berjalan menjelajahi jagat pustaka dari hari ke hari. Dengan benda kecil itu, saya selalu dibuat sadar akan adanya jagat di mana saya tidak harus terburu-buru. Jagat dengan hidup yang santuy.
*Kawan-kawan dapat menikmati artikel-artikel lain tentang literasi atau tentang buku