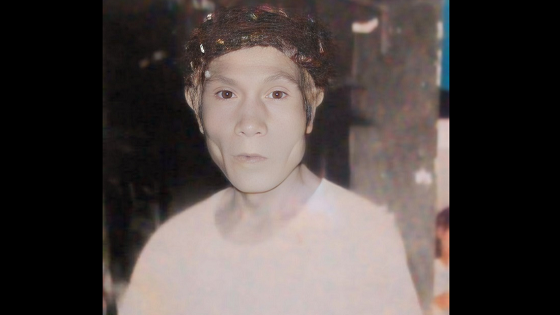Ciguriang, Kampung Dobi dalam Ingatan #16: Abah Ilim Jadi Panutan di Mata Keluarga dan Tetangga
Abah Ilim, kakekku, adalah dobi tiga zaman: Belanda, Jepang, dan republik. Selain sesepuh di keluarga kami, Abah Ilim juga kerap diminta nasihat oleh tetangga.
Ernawatie Sutarna
Ibu rumah tangga, peminat sejarah, anggota sejumlah komunitas sejarah di Bandung.
26 Januari 2025
BandungBergerak.id - Pekerjaan sebagai dobi dilakukan Abah Ilim melalui tiga zaman. Abah memulainya pada masa pendudukan Belanda, karena ayah angkat Abah Ilim yang juga kakaknya satu ayah, juga berprofesi sebagai dobi. Ayah angkat abah itu, abah uyut saya bernama Abah Mulya, berasal dari Garut dan hijrah ke Bandung. Mengapa Abah Ilim menganggap Abah Mulya seperti ayahnya, mungkin karena usia mereka yang terpaut sangat jauh, sedangkan ayah mereka meninggal pada saat usia Abah Ilim masih sangat kecil. Karena kebersamaan mereka itulah, Abah Ilim mendapatkan profesi yang sama dengan Abah Mulya. Tentu saja dengan sendirinya ilmu dan kebiasaan dalam melakukan pekerjaannya menurun dan juga menjadi keahlian Abah Ilim.
Abah Ilim pun menjalani profesi ini di zaman pendudukan Jepang. Hanya sayang, saya tidak sempat bertukar cerita dengan Abah tentang masa pendudukan Jepang dan profesi abah secara detail, Ambu pun tidak begitu paham karena Ambu lahir setelah masa pendudukan Jepang. Di masa setelah kemerdekaan, Abah Ilim masih setia dengan profesinya, menjadi seorang dobi, binatu, tukang cuci. Ketika saya, cucunya mulai mampu merekam peristiwa di dalam ingatan, juga menyimpan rekaman-rekaman kegiatan ketika Abah bekerja. Bagaimana tahap-tahap yang abah siapkan ketika akan bekerja, sedang bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya, mungkin untuk sebegian besar orang itu hal yang sangat biasa, tapi bukankah kenangan yang paling sulit untuk dilupakan terkadang justru dari hal-hal yang awalnya tidak kita anggap berarti?
Dalam kenangan saya, Abah Ilim adalah sosok luar biasa. Dalam kesederhanaan sikap dan tutur bahasanya, Abah menanamkan banyak sekali pelajaran hidup tanpa saya merasa diajari. Hanya saja setelah saya kembali lagi mengingat kenangan tentang Abah, saya baru bisa menarik pelajaran apa yang sebetulnya ada dalam sikapnya itu, dan itu masih bisa berlaku untuk hari ini, bahkan esok atau lusa. Di mata saya, Abah adalah sosok yang tidak terlalu banyak bicara. Sorot matanya tajam, membuat segan, tapi memberikan rasa aman.
Abah bukan hanya sesepuh di keluarga kami, tapi juga di antara warga. Kami sering kedatangan tamu yang sekadar meminta pandangan dari Abah. Bahkan di sela pekerjaannya sebagai dobi, sering para orang tua terutama para ibu yang meminta doa pada sebotol air untuk meredakan demam yang diderita anaknya atau untuk nyebor saat anaknya terkena tampek. Abah tidak menyebut dirinya orang pintar, saya pun sebagai cucunya tidak pernah mendengar orang menyebut seperti itu. Abah hanya berprinsip, jika apa yang dilakukannya bisa membantu orang lain, maka itu akan terus dia lakukan.
Kami cucu-cucunya pun mendapatkan air doa dari abah jika kami hareeng, demam, tidak enak badan. Air di botol itu sebagian besar dicampurkan ke dalam air untuk mandi, dan satu gelas dipisahkan tersendiri untuk kami minum. Biasanya setelah mandi dan minum air doa, panas demam akan mereda.
“Abah itu kalem, tara curak-carek, komo ka batur, gak pernah bermasalah dengan orang lain,” kata Ambu, putrinya. Dan memang seperti itu pula kesan dari kami cucu-cucunya. Tidak galak tidak pula memanjakan. Hanya saja jika kami ketahuan main jarambah, Abah akan menasehati dengan beberapa kata saja, “Ulah ka dinya deui,” dan kami pun menurut apa yang diminta Abah.
Baca Juga: MULUNG TANJUNG #16: Ciguriang, Kampung Dobi dalam Ingatan (14)
MULUNG TANJUNG #17: Ciguriang, Kampung Dobi Dalam Ingatan (15)
MULUNG TANJUNG #18: Ciguriang, Kampung Dobi dalam Ingatan (16)
Selain pekerjaan sebagai dobi, binatu, Abah juga beternak domba, itik atau meri, dan ayam tentu saja. Ada beberapa ekor domba yang Abah pelihara, dengan kandang yang berada di halaman rumah kami, hal itu cukup membuat hari-hari kami menjadi cukup ramai dengan suara domba yang bersahutan, lalu ayam yang dibiarkan di halaman pada siang hari dan masuk kandang yang seadanya pada malam hari. Beberapa dari ayam itu tidur di dahan-dahan pohon sirsak. Yang paling ramai memang suara itik yang selalu berombongan kian kemari. Selain sirsak dan jambu batu, ada pohon pisang, juga pohon belimbing di depan rumah yang rajin berbuah.
Menurut Ambu, pada saat ambu dan kakak adiknya masih kecil juga ada beberapa pohon lain seperti durian dan anggur. Yang saya ingat ada pula pohon alpukat dan mangga. Tanaman obat pun banyak tumbuh di halaman kami seperti dadap, jarak, jawer kotok, baluntas, sampai pandan, dan suji. Bukan hanya kami yang memanfaatkan tanaman itu, tapi juga tetangga yang mungkin memerlukan.
Hal yang menyenangkan selain mengikuti Abah Ilim mencuci di Ciguriang adalah mengikuti Abah dan Ma Abah ngarit, menyabit rumput ke Kerkop, begitu kami meyebut GOR Pajajaran. Ketika Abah Ilim dan Ma Abah sibuk menyabit rumput untuk pakan domba, kami pun sama-sama sibuk, sibuk berlari ke sana ke mari mengejar papatong. Sekali lagi saya sendiri paling suka berlarian di antara rumput-rumput yang tumbuh tinggi itu, saat itu saya bisa berpura-pura menjadi Laura Ingalls yang sedang bermain di prairie. Ketika carangka, keranjang besar yang kami bawa dari rumah sudah penuh dengan rumput, kami pun akan pulang.
Abah Ilim yang lahir pada tahun 1910 dengan nama Salim, meninggal di usia 82 tahun pada tahun 1992. Banyak hal yang bisa kami pelajari dari abah, kesabaran, kebijaksanaan, kebaikan pada sesama. Menolong siapa pun yang tertimpa kesulitan, hal yang pernah Abah lakukan ialah menampung dua orang pengamen topeng monyet selama berhari-hari, karena salah satunya jatuh sakit. Kedua orang itu ditampung Abah dan Ma Abah dengan diperlakukan sebagai tamu, dijamu dan diobati, tanpa saling mengenal sebelumnya.
*Kawan-kawan yang baik, silakan menengok tulisan-tulisan lain Ernawatie Sutarna atau artikel-artikel lain tentang Sejarah Bandung