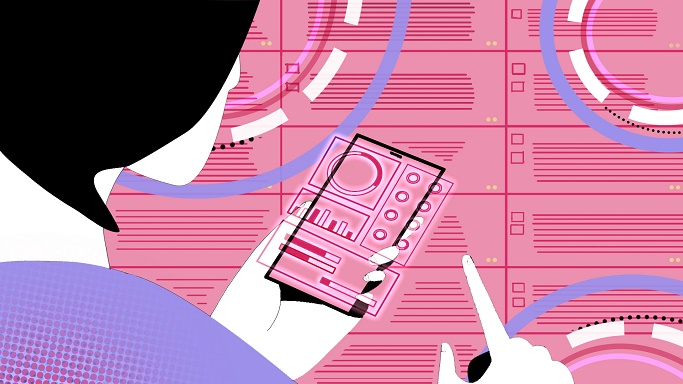Susahnya jadi Jomlo di Zaman ini
Menjomlo menjadi kesusahan yang dipilih oleh manusia modern saat ini. Perasaan kesepiannya dipalak menjadi komoditas industri.

Laila Nursaliha
Desainer Kurikulum. Berminat pada Kajian Curriculum Studies, Sains dan Teknologi pendidikan, serta Pendidikan Guru.
4 Februari 2025
BandungBergerak.id – Di setiap zaman, menjadi jomlo itu selalu tidak mudah. Dari zaman gelap hingga zaman terang benderang. Kecuali bagi para jomlo yang sudah rela hati untuk berkhidmat untuk kesendiriannya. Tapi tetap saja, bukan pilihan mudah.
Perbedaan paling mencolok jomlo zaman dulu dan zaman sekarang adalah teknologi komunikasi. Zaman dulu, relasi jomlo mengandalkan orang terdekat sehingga pilihan pasangan terbatas. Zaman sekarang, komunikasi terlalu banyak sehingga tak semendalam dulu. Hanya satu persamaan yang bisa diambil di antara para jomlo ini adalah keterasingan dari masyarakat bahkan dari dirinya sendiri.
Pada dasarnya, menjadi jomlo itu susah. Selain memang sendirian saja, salah satu kesusahannya seperti yang ada di tulisan Tofan tentang masalah ekonomi yang tak ditanggulangi negara. Tentu saja, peran negara ini meningkatkan jumlah Jomlo di sebuah negara. Negara inilah yang membuat pilihan aman untuk seseorang agar terus tetap menjomlo.
Dibalik satu kesusahan itu, sejauh ini saya masih bangga dengan status kejomloan saya. Senada dengan tulisannya Yogi Esa tentang Kejomloan, tempo hari. Percaya tidak percaya, kejomloan saya 100% berguna meskipun bukan di ranah yang ideologis-ideologis amat. Tentu saja ini akan menambah optimisme di kalangan para jomlo.
Misalnya menjadi anak yang bisa membantu orang tua kapan saja, membantu teman-teman atau saudara yang sudah berkeluarga, di dunia pekerjaan pun kami bisa cukup diandalkan untuk bekerja lembur tanpa kecemasan yang berarti ataupun untuk memangkas anggaran. Khusus anggaran, begini alasannya, “Dia kan masih jomlo, belum punya tanggungan”. Meskipun agak menyesakkan tapi itulah sedikit kegunaan jomblo.
Baca Juga: Sialnya Kita Miskin, Bernadya Mungkin Tidak Merasakannya
Kejomloan Saya adalah Kesalahan Negara!
Tofan dan Betapa Pentingnya Keterlibatan Kaum Jomlo dalam Persoalan Aktual
Menjomlo hubungannya dengan Kecemasan Berkomitmen
Elyakim Kislev, penulis buku Happy Singlehood, menyebutkan ada dua faktor mengapa seseorang menjomlo. Di antaranya yaitu faktor sosial dan psikologis. Tulisan Tofan yang berjudul “Kejomloan Saya adalah Salah Negara” adalah satu contoh realistis yang tak bisa dipungkiri sebagai salah satu hambatan untuk memulai berkomitmen. Hubungan cinta tidak bisa dilepaskan dari ekonomi, entah cinta yang membutuhkan kebebasan ekonomi atau ekonomi yang kemudian akan mengeksploitasi hasrat manusia.
Selain faktor ekonomi dan kebijakan negara yang tak bisa mengatrol kualitas ekonomi, meningkatnya populasi jumlah lajang salah satunya ada nilai-nilai yang berubah, kesempatan kerja dan pendidikan, perubahan pola beragama, dan perubahan teknologi. Saat ini, manusia sudah mulai menempatkan pernikahan di urutan sekian setelah karier dan pendidikan. Prioritas ini menjadi bergeser seiring dengan berkembangnya nilai-nilai.
Perubahan-perubahan itu bukan terjadi dalam waktu singkat, namun berakar dari pertumbuhan dunia modern yang cenderung rasional. Harvey Cox, pada tahun 1965 sudah menggambarkan hubungan manusia terbagi menjadi hubungan publik dan privat yang berpengaruh kepada interaksi antar manusia. Hubungan manusia menjadi lebih singkat dan sementara. Toffler, futurolog pun menyatakan hal yang sama. Dalam bukunya, Kejutan Masa Depan, menurunnya rentang waktu hubungan antar manusia adalah akibat wajar dari meningkatkan jumlah hubungan itu.
Jumlah peningkatan hubungan yang sementara terjadi akibat adanya mobilitas yang tinggi. Sehingga yang terjadi adalah banyak bertemu orang, namun dengan tidak lama dan tidak mendalam. Bisa dikatakan, hubungan-hubungan ini menjadi terfragmentasi. Manusia menjadi terpecah dalam berbagai wajah.
Kedua adalah faktor psikologis. Alasan banyak orang menjomlo adalah permasalahan psikologis tentang dirinya yang mendasarinya. Di antaranya adalah ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pasangan, di sisi lain ada semacam hasrat terhadap kebebasan, trauma masa lalu, gaya kemelekatan (attachment style) yang berakar dari pengabaian dan keintiman.
Sehingga, ketika syarat semula menikah hanya berdasar kepada –setidaknya empat hal– kecantikan, kekayaan, keturunan, dan agamanya, kini bergeser kepada motif yang lebih beragam selain keamanan dan kenyamanan. Para jomlo ini berhadapan dengan berbagai ketidakpastian kerja, hubungan yang lebih beragam, dan mungkin meragukan dirinya apakah bisa lebih setia.
Rasionalitas yang berpadu dengan kesementaraan dan kebebasan ini, membuat individu-individu mudah cemas menghadapi masa depan. Karena ada sisi diri yang menginginkan kebebasan namun sebagai konsekuensi dari menggenap adalah ada sisi lain menjadi terikat. Satu pertanyaan saja, apakah dia adalah orang yang tepat untuk diajak hidup bersama selama sisa hidup?
Tak seperti orang tua zaman dahulu, menikah seperti berkomitmen menitipkan jiwa dan raga. Syaratnya ia bisa mencukupi berbagai kebutuhan dan memiliki kepribadian yang baik. Urusan cocok atau tidak, itu perkara belakangan. Konon, kecocokan itu hanya perlu diusahakan. Tapi, prinsip itu tidak diterima oleh generasi sekarang, anak-anaknya.
Perubahan Nilai dan Komodifikasi Cinta
Sebagai jomlo yang baik dan mengisi kejomloan agar bermanfaat, saya banyak belajar tentang manusia dan hasratnya akan cinta. Menurut para orang tua, cinta spesifik di antara orang dewasa itu menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Di sanalah saya berpikir, apakah benar seperti itu? Karena kebanyakan desain pencarian jodoh ini mirip seperti orang melamar pekerjaan. Tentu saja ini ditertawakan oleh orang tua zaman dahulu yang menikah.
Tepat ketika saya membaca buku Erich Fromm, barulah saya sadar ketika ia membahas tentang hancurnya cinta. Ia menulis begini “Peradaban kita menawarkan banyak obat pereda sakit yang membantu orang-orang agar sengaja tidak sadar dengan kesendirian ini : mula-mula rutinitas ketat pekerjaan birokratis dan mekanis, yang membantu orang untuk tetap tidak sadar akan hasrat manusia mereka paling dasar, yaitu kerinduan transendensi dan hasrat untuk menyatu.”
Setelah membaca kalimat itu, saya bercermin kepada diri sendiri, jangan-jangan saya memang tidak mengenal hasrat manusia yang paling dasar seperti apa yang disebutkan oleh Fromm. Fromm melanjutkan, manusia mengatasi rasa putus asa yang tak disadarinya dengan rutinitas hiburan, konsumsi pasif, kepuasan membeli barang baru, tapi tanpa diri. Dirinya hilang ditukar dengan kepalsuan-kepalsuan yang disangka pelebur lara.
Beberapa pakar pun menunjukkan kepada pembacaan yang demikian. Eva Illouz, seorang profesor Sosiologi, dalam bukunya Cold Intimacies menjelaskan mengenai bagaimana cinta dan hubungan intim sudah menjadi komoditas pasar. Seperti halnya rasionalitas yang merasuk kepada konsep homo economicus, di sini rasionalitas masuk ke dalam ranah percintaan dan emosi. Faktor rasionalitas yang berlebihan ini, kini mendominasi bagaimana seseorang memilih pasangan. Terlebih dengan terbukanya akses komunikasi dan informasi, disadari atau tidak, ada semacam tren untuk menjadi yang sempurna dan memilih yang sempurna.
Bisa kita lihat di aplikasi kencan yang menggunakan basis algoritma berdasarkan kecocokan jenis tertentu. Pemilihan pasangan bukan didasarkan kepada kelekatan tetapi lebih transaksional. Manusia lain diperlakukan seperti barang yang apabila disukai tinggal swipe right, tak suka tinggal delete. Kini, menikah tak ubahnya melamar pekerjaan atau membentuk sebuah organisasi bahkan berdagang. Faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus perceraian karena hasrat manusia dan kesementaraan.
Salah sangka ini diutarakan oleh Erich Fromm sebagai persekutuan berdua menghadapi dunia dan egoisme a deux disalahartikan sebagai cinta dan keintiman. Berbagai alat yang ditawarkan kepada para jomlo barangkali, bukan sesuatu yang dicari. Ia dihadirkan untuk melepas rasa kesendirian bukan sebagai alat penyatuan diri dan transendensi yang tinggi.
Masih banyak kesusahan lain yang menjadikan menjomlo menjadi kesusahan yang dipilih oleh manusia modern saat ini. Bahkan membuat sebuah identitas baru sebagai jomlo. Saya menyadari kesusahannya. Sudah disusahin negara, sulit mencapai memenuhi kebutuhan dasar manusia, perasaan kesepiannya dipalak menjadi komoditas industri. Habislah jomlo tak tersisa kecuali imannya kepada yang Mahakuasa. Itu pun kalau yang punya iman.
Namun sebagai jomlo, mesti tetap bernyali, menjaga diri, dan tentu saja menunggu yang mengetuk hati. Seperti lirik lagu Kunto Aji “Bukan tanpa nyali, sadar aku begini. Apa yang di depan mata, tak seperti yang engkau kira. Bahwa sesungguhnya pintu hati menunggu, terbuka.”
Kawan-kawan dapat membaca tulisan-tulisan menarik lainnya dari Laila Nursaliha, atau membaca artikel-artikel tentang pendidikan