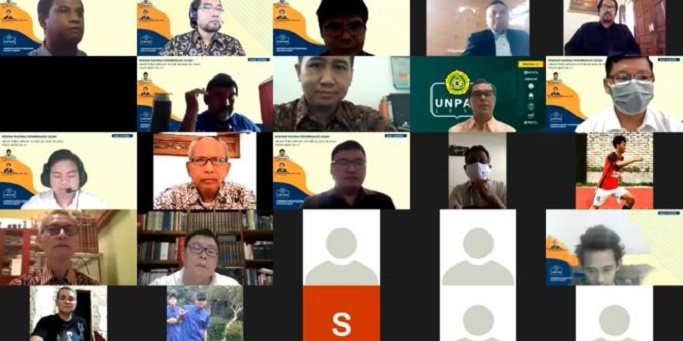Menilik Posisi Agama di Abad ke-21
Agama ditampilkan dalam paras ambiguitas antara fakta (historisitas) dan dogma (normativitas). Dogma terkait hal baik , namun fakta historisnya berbanding terbalik.
Penulis Iman Herdiana16 Juli 2021
BandungBergerak.id - Fakultas Filsafat Unpar (Universitas Katolik Parahyangan) menggelar webinar “Arah Perjumpaan Antar Agama-Agama Pada Abad ke-21”. Peserta webinar diajak melihat posisi agama pada abad ke-21. Di satu sisi, agama tampaknya sedang bangkit dan menawarkan harapan baru. Di sisi lain, ada potensi yang menyebabkan chaos.
Dibahas pula bagaimana model dan arah perjumpaan agama yang mesti diupayakan agar praksisnya semakin korelasional dan rasional. Diskusi juga berusaha menyodorkan hal-hal signifikan yang dapat digamit guna merancang peran agama ke depan.
Webinar ini menghadirkan cendekiawan muslim sekaligus Rektor IAILM Suryalaya Tasikmalaya, Asep Salahudin, dan dosen Fakultas Filsafat Unpar, Gerardette Philips.
Asep Salahudin mengatakan, ihwal arah perjumpaan antar-agama merupakan persoalan klasik namun akan selalu memiliki relevansi dan aktualisasi kehidupan dalam konteks keindonesiaan yang multikultural.
Hal lain yang perlu dikhawatirkan, lanjut dia, adanya kebangkitan paham populisme, sebuah paham yang mencoba mengglorifikasi sentimen yang berbasis pada identitas dalam pemaknaan yang sangat sempit. Baik identitas kesukuan maupun keagamaan.
Dalam konteks keindonesiaan, kata Asep Salahudin, seringkali publik dihadapkan pada konflik tak berkesudahan dan berulang, yaitu kekerasan fisik yang diawali dengan kekerasan simbolik.
“Hal ini dikarenakan adanya penafsiran agama yang dicabut dari akar sejarahnya dan dilakukan secara parsial serta semena-mena,” kata Asep, dikutip dari laman Unpar, Jumat (16/7/2021).
Menurutnya, agama seringkali ditampilkan dalam ‘paras’ yang penuh dengan ambiguitas antara fakta (historisitas) dan dogma (normativitas). Dogma seringkali digambarkan dengan hal baik dan menjanjikan kehidupan damai dan toleran, namun fakta historisnya justru berbanding terbalik.
“Karena ketegangan ini tidak bisa didamaikan, kemudian ada banyak orang yang meragukan keberadaan agama itu sendiri. Saya kira ini problem laten hari ini, ambiguitas agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman kita sehari-hari. Namun kenyataannya, agama selalu memiliki banyak ‘nyawa’, saat setiap orang menyangsikannya, agama selalu mengalami kebangkitan, mulai dari paling lunak hingga paling ekstrem. Tentu ini menjadi tantangan beragama memasuki awal abad 21 ini,” tutur dia.
Asep melihat, ada masalah besar tentang kebangkitan agama yang tidak sesuai dengan harapan. Respons terhadap keberagaman ini terbelah menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok bersifat inklusif dan eksklusif.
“Eksklusivisme ini menjadi awal muncul puritanisme, setelah puritan mereka menjadi fundamentalisme, setelahnya tentu selangkah lagi mereka menjadi terorisme. Ideologi kekerasan itu berakar dari fundamentalisme dan mereka memiliki basis legitimasinya dari sikap beragama yang eksklusif,” ujarnya.
Kendati demikian, kemajemukan yang menjadi fakta sosial di Indonesia mestinya menjadi alasan utama bagi setiap agama bisa melakukan deradikalisasi di ruang publik. Tiga langkah yang patut dilakukan, yaitu penalaran rasional, adanya pemahaman bersama melalui riset publik, dan seluruh proses pemahaman keagamaan ini sudah sewajarnya menjadi jalan bagi upaya munculnya kebaikan bersama.
Dalam situasi di Indonesia, Pancasila sebenarnya menjadi titik temu bagi keberagaman yang ditandai oleh pluralisme dan menyelesaikan persoalan lintas agama pada ruang publik. Oleh karena itu, dialog antar umat beragama mesti bermuara pada upaya menjawab serangkaian tantangan di masa depan.
“Saya kira dalam konteks keindonesiaan, kita sudah sangat memiliki pengalaman tentang itu. Ketika Pancasila dirumuskan dan menjadi satu hal yang hingga kini kita sepakati bersama, itu menjadi bagian ruang publik yang didialogkan untuk kebaikan bersama. Pancasila menyelesaikan persoalan lintas agama pada ruang publik. Pancasila menjadi titik temu, titik tumpu, dan titik tujunya,” katanya.
Dia pun menuturkan, agar agama tersebut produktif, maka ada 3 aspek yang tidak boleh diabaikan, yakni iman, logos (sisi intelektual), dan etos (agama menjadi pandu moral tindakan di ruang publik).
“Agama menjadi produktif ketika tiga lapisan itu kita tarik dalam satu helaan napas,” tutur tokoh NU tersebut.
Baca Juga: Kasus Penghilangan Paksa Menggema dalam Fiksi
Pancasila dari Rakyat (4): Ketika Petani Masih Dipandang Sebelah Mata
Pancasila dari Rakyat (3): Dialog dengan Sukarno dalam Lirik Lagu Koil
Pentingnya Membangun Budaya Harmonis dan Religius
Gerardette melihat nilai dan makna keberagaman pada agama itu sendiri. Salah satu nilai yang bisa dilakukan adalah membangun budaya harmonis dan religius. Serta sikap perspektif, baik secara implisit dan eksplisit yang dipegang orang tentang spiritualitas dan agama. Serta bagaimana mereka berhubungan dengan praktik kepedulian berdasarkan spiritual.
“Hormati perbedaan yang tidak dapat diprediksi tanpa mencari satu Tuhan. Fokus pada nilai yang dipraktik dan kepercayaan yang dijalani. Serta dialog dengan kesadaran penuh akan bias dan perbedaan yang tidak bisa dimungkiri,” ucapnya.
Agama-agama yang notabene berbeda-beda itu dapat membantu manusia untuk mengalami Tuhan dalam praksis. Praksis agama yang menjanjikan untuk masa kini dan ke depan, antara lain diwarnai dengan kemauan untuk terus menerus mengembangkan sikap terbuka, mengakui, menerima, dan menghormati perbedaan. Serta bertumbuh dalam sikap kritis dan berani berpikir rasional dalam merespon fenomena-fenomena agama.
Dia mengatakan, ada tiga hal yang perlu dipahami dalam beragama, yaitu pengetahuan, kepercayaan dan pengalaman. “Kalau ada pengetahuan, kepercayaan, dan pengalaman, pasti cara kita terhadap satu sama lain akan berbeda,” katanya.