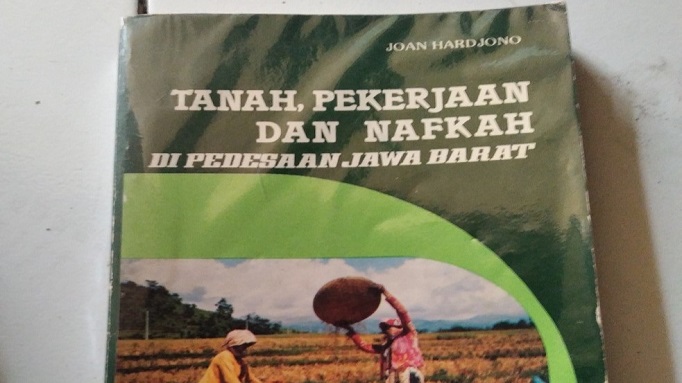BUKU BANDUNG #53: Menilik Pergeseran Pemilikan Tanah Era 70an
Kisah warga Desa Wangisagara di Majalaya menjalani proses transisi dari corak feodal menuju kapitalisme. Potret pergeseran politik kepemilikan tanah.
Penulis Yogi Esa Sukma Nugraha6 Desember 2022
BandungBergerak.id— Beberapa studi mengenai pembantaian massal 1965 menyimpulkan bahwa peristiwa kelam tersebut tidak lepas dari apa yang terjadi dalam konteks lokal. Misalnya saja, temuan Robert Cribb (2003, hal. 44-46) menyatakan tidak jauh dari kota Metro di Lampung, pembantaian massal dilakukan penduduk setempat yang mayoritas muslim, yang merasa terganggu atas kehadiran transmigran Jawa. Kemudian di Nusa Tenggara, gesekan menyeruak antara pemeluk Kristen dan agama-agama tradisional.
Selain itu di Nusa Tenggara, gesekan menyeruak antara pemeluk Kristen dan agama-agama tradisional. Di Timor, dipicu sikap Gereja Protestan yang sedang mendampingi petani miskin dalam sengketa agraria yang mengakibatkan terbunuhnya pendeta, guru, dan sejumlah staf universitas setempat. Lalu di Kalimantan Barat pembunuhan orang Tionghoa oleh suku Dayak.
Di sini kiranya menjadi penting untuk kemudian memahami apa dan bagaimana dampak lanjutan dari pembantaian massal 1965. Dalam konteks pedesaan, umumnya para petani tercerabut dari ikatan tanah yang sebelumnya dimiliki mereka. Hal ini selaras dengan pernyataan seorang filsuf yang hidup dua abad lalu, yang merumuskan gejala ini sebagai akumulasi asali atau akumulasi primitif. Bahkan ia menggambarkannya serupa dosa awal dalam teologi.
Ironisnya, akumulasi asali atau akumulasi primitif yang merupakan dampak lanjutan dari pembantaian massal 1965 ini termasuk yang jarang dipercakapkan publik. Padahal, itu dapat menunjukkan sebuah upaya awal bagaimana kelompok yang diuntungkan mempercepat proses akumulasi kapital. Dan pada saat yang sama, juga dapat menjelaskan mengapa kekuatan elemen yang memiliki komitmen sosial kemudian dihancurkan secara simultan.
Itu pula yang jauh setelah kejadian berakibat pada kemiskinan imajinasi sosial dan kultural. Dengan lain perkataan, relasi produksi kapital yang kini dominan, telah mengaburkan bahkan untuk sekadar orang membayangkan bentuk masyarakat ideal.
Yang terbilang langka, di salah satu wilayah Jawa Barat, kasus ini berjalan dengan proses yang sedikit berbeda. Tanpa ada pembantaian massal sebagaimana di wilayah lainnya, proses transisi corak produksi dari feodal ke kapitalisme berjalan tanpa hambatan berarti. Dalam upaya mengantar untuk kemudian mencari jawaban atas persoalan seperti itulah buku “Tanah, Pekerjaan, dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat” karya Joan Sardjono ini menjadi relevan.
Baca Juga: BUKU BANDUNG #52: Lawatan Sejarah yang Paling Sunyi
BUKU BANDUNG #51: Kisah Jin dalam Botol dan Pilgub Jabar Pascaruntuhnya Orde Baru
BUKU BANDUNG #50: Memotret Harapan Warga Pinggiran di Usia 200 Tahun Bandung
BUKU BANDUNG #49: Melacak Pengaruh Kopi dan Sistem Priangan pada Kebudayaan Sunda
Alkisah Sebuah Desa Bernama Wangisagara
Jauh di era sebelumnya –katakanlah, dalam corak produksi feodal— setiap petani umumnya memiliki sepetak tanah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun ada perubahan signifikan, terutama pasca pembantaian massal 1965. Pada era ini terjadi transisi dari corak feodal menuju kapitalis, ditandai dengan meningkatnya jumlah petani tunakisma: absolute landless dan landless tenant, atau yang di Indonesia disebut petani penyakap/bagi hasil dan penyewa.
Selain itu, masih sebagai penanda peralihan menuju corak produksi kapitalis, produk pertanian turut mengalami komodifikasi. Dari yang semula untuk subsistensi keluarga petani, atau paling tidak sekadar untuk upeti pada para tuan tanah, lalu kemudian berganti menjadi komoditas. Hal tersebut terjadi pula di Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.
Meski demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka bahwa apa yang terjadi di Wangisagara ini, proses awalnya sedikit berbeda dengan di wilayah lainnya. Sebab, lebih dulu digegerkan dengan huru-hara yang dipicu gerombolan DI/TII. Barangkali hal ini cukup menjelaskan mengapa seruan kelompok kiri untuk menghabisi “7 setan desa”, dan kampanye pendudukan lahan oleh petani miskin, yang oleh banyak kalangan disebut “aksi sepihak”, cenderung absen di wilayah ini.
Sebuah upaya penelitian yang dilakukan Joan Hardjono yang terbit pada tahun 1987 –untuk kemudian diterjemahkan 1990- berupaya menangkap proses transisi ini secara rinci. Sebagai langkah awal, Joan Hardjono melakukan sensus rumah tangga. Hal ini, menurutnya, agar data secara menyeluruh dapat dikumpulkan, terutama mengenai komposisi rumah tangga, pekerjaan anggota rumah tangga, luas tanah yang dimiliki dan digarap, dan jumlah hewan ternak yang dipelihara. Terbukti dalam waktu 15 bulan, Joan Hardjono mampu mempelajari perubahan musiman dalam penggunaan tanah, input tenaga kerja, sumber penghasilan, dan hal-hal penting lainnya.
Bersamaan dengan itu, data-data juga dikumpulkan mengenai hubungan keluarga (yang hijrah saat huru-hara) dan pemilikan tanah. "Jumlah penduduk Bandung meningkat pada 1957 dan 1958 ketika pemberontakan Darul Islam timbul, yang menyebabkan perpindahan penduduk yang tak seimbang di pedesaan Jawa Barat," tulis Hardjono (1990, hlm. 37).
Dengan demikian, selama tahun 1950an, perubahan pada pola pemilikan tanah tidak banyak terjadi akibat gerombolan DI/TII, yang kemudian memaksakan perpindahan penduduk Wangisagara ke tempat lain, terutama Bandung dan Jakarta.
Ada tiga alasan, beliau memilih desa Wangisagara untuk penelitiannya. Pertama, karena pola penggunaan tanahnya, sebagaimana Ester Boserup merumuskan konsep bahwa “di masa lampau pertumbuhan penduduk dalam sebuah masyarakat mengakibatkan intensifikasi penggunaan tanah”. Artinya, di Wangisagara, tanah dipanen tiga kali atau lebih per tahunnya, tanpa kekosongan. Kedua, adanya kepadatan penduduk yang tinggi dibanding luas tanahnya. Ketiga, lokasi dipilih harus cukup jauh dari perkotaan. Yang menarik, yang juga menjadi pembeda dengan apa yang terjadi di wilayah lainnya, adalah penjelasan mengenai program Land Reform pada tahun 1960an. Menurutnya, hal tersebut tidak berdampak signifikan pada "pola pemilikan tanah karena daerah ini dari segi politik tergolong tidak stabil untuk redistribusi tanah. Akan tetapi, sesudah tahun 1965, kecenderungan-kecenderungan baru muncul, yaitu menurunnya tingkat sosial pemilik-pemilik tanah yang luas dan mengecilnya ukuran usaha tani."
Penjelasan ini dipertegas lebih mendalam oleh pendapat Gunawan Wiradi, yang mengungkapkan bahwa syarat Land Reform bukan saja redistribusi tanah, melainkan juga (1) Organisasi Tani harus kuat di basis rakyat, (2) elit politik harus terpisah dari elit bisnis, (3) militer harus mendukung, (4) data keagrarian harus cermat dan akurat, (5) birokrasi tidak boleh korup, serta (6) kemauan politik dan aturan pelaksanaan yang tegas dari negara. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pada era Presiden Soekarno, yang merupakan tahapan awal, belum sepenuhnya berhasil mempersiapkan jalan bagi terwujudnya syarat-syarat reforma agraria tersebut. Dalam upaya awal pencatatan data keagrarian, misalnya, diwarnai oleh manipulasi counter-reform dari keluarga tuan tanah. Selain itu, juga minimnya dukungan dari militer.
Sebagai informasi pula bahwa jarak antara Wangisagara dari Kota Bandung kurang lebih sekitar 36 kilometer. Wangisagara merupakan satu dari dua belas desa-desa di Kecamatan Majalaya, yang lebih tepat berada di sebelah tenggara. Majalaya sendiri telah berdiri sebelum adanya Peraturan Konstitusionil yang dikeluarkan Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1854.
Pada permulaan tahun 1930-an penenunan tangan tradisional di Majalaya yang semula hampir lenyap akibat kebijakan impor pemerintah Belanda, mengalami kebangkitan kembali tatkala pemerintah kolonial mulai memperhatikan industri kecil sebagai upaya mengurangi kerugian di masa depresi. Kemudian dengan pemasangan listrik di awal tahun 1937, alat tenun mesin mulai digunakan, dan pada tahun 1960an, Majalaya menghasilkan 40 persen dari jumlah total produksi kain di Indonesia.
Yang menarik, sebagian besar dari jumlah tersebut merupakan hasil dari alat tenun bukan mesin (ATBM). Hal ini di afirmasi studi lain yang dilakukan Hiroshi Matsuo, yang menyebut bahwa pada tahun 1966, 23 persen dari semua rumah tangga di Kecamatan Majalaya ikut serta dalam industri tenun tangan. Namun, pada akhir 60an, sektor tenun tangan telah mengalami penyusutan. Hal tersebut, menurut Hardjono, salah satunya disebabkan oleh naiknya popularitas bergaya barat di Indonesia, yang menggantikan pakaian tradisional seperti sarung misalnya.
Seperti diketahui bahwa pada awal 70an, Orde Baru menerapkan politik pintu terbuka yang membuka akses seluas-luasnya pada Barat. Dalam Jurnal "Rambut Gondrong di Semarang Pada Tahun 1967-1973" yang ditulis Taufik Wijanarko dkk, disebut bahwa saat itu, musik rock yang pada masa Soekarno dianggap sebagai musik ngak-ngik-ngok, menjadi populer pada masa Orde Baru. Adalah The Beatles salah satu band yang populer di kalangan anak muda pada jaman itu.
Ironisnya, hal tersebut membuat Pangkopkamtib Jenderal Soemitro di layar TVRI geram, kemudian menyerukan operasi penertiban rambut gondrong. Tentu saja hal ini memicu tanggapan sejumlah kalangan. Salah satunya adalah kelompok mahasiswa dari Bandung, yang membalasnya dengan ejekan: melakukan razia orang gendut –mengacu pada perawakan Jenderal Soemitro. Singkatnya, bagi rezim Orde Baru, rambut cepak ala ABRI dianggap menjadi potongan rambut yang ideal. Sementara rambut gondrong, dinilai sebagai biang kerok segala persoalan sosial.
Yang terpenting, temuan Joan Hardjono menunjukkan bahwa merosotnya penghidupan petani dan industri tenun tangan yang diiringi kenaikan penduduk, disebabkan oleh masuknya investor besar. Suatu hal yang kemudian membuat petani mau tidak mau harus beralih mencari penghidupan di pabrik-pabrik tekstil mesin pada era 70an. Secara sederhana, seperti dinyatakan Joan Hardjono bahwa "perkembangan cepat di Industri Tekstil di Bandung pada masa 70-an kemudian terus-menerus menarik penduduk pedesaan untuk bekerja. Bahkan karena nilai tanah yang tidak sebanding dengan hasil pertanian, para pemilik sawah di daerah-daerah dekat Majalaya rela menjual sawah mereka kepada perusahaan tekstil sejak awal tahun 1970an.”
Proletarisasi Petani Wangisagara
Pada tahun 1967 terdapat 53,4 persen dari semua rumah tangga di Kecamatan Majalaya memiliki tanah pertanian, akan tetapi pada tahun 1980 hanya 20,3 persen. Dan antara tahun 1967 dan 1980, Kecamatan Majalaya dan Desa Wangisagara mengalami pertambahan penduduk yang cepat, dengan rata-rata per tahun 3,6 persen di kecamatan tersebut dan 4,5 persen di Wangisagara. (Hardjono, 1999, hlm. 43).
Artinya, terjadi pergeseran sebagian pemilikan tanah yang juga berarti transisi dari penyakapan menjadi buruh upahan. Sebetulnya, sebagian penyakap-penyakap sadar bahwa mereka dapat kehilangan pekerjaan karena perjanjian dapat dihentikan sesudah panen. Demikian pula penyakap-penyakap di tanah yang dulu mereka miliki lalu dijual, sadar akan ketidakpastian dalam relasi upahan. Namun, tentu mereka tak kuasa melawan sistem yang kian mencengkeram. Dan hal ini, tentu saja, tidak sesuai dengan jalan yang ditempuh Presiden Sukarno dalam Jalannya Revolusi Kita (Jarek), yang menandaskan bahwa “Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah. Tanah tidak untuk mereka yang dengan duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk- gendut karena menghisap keringatnya orang-orang yang disuruh menggarap tanah itu!”
Sejak tahun 1970, sedikitnya telah terjadi penjualan 59 bidang tanah dan sawah. “Alasan penjualan tanah yang paling sering diutarakan adalah demi pembayaran ongkos pengobatan dan keperluan pembelian bahan-bahan dasar untuk hidup,” tulis Hardjono (hlm. 88). Adapun seorang warga lainnya, yang dalam satu kesempatan berbincang dengan Joan Hardjono, mengatakan bahwa “lebih baik dia memiliki seekor kuda dan delman sebagai sumber penghidupan sehari-hari, daripada sawah yang diwariskan kepadanya, meskipun ia harus mengambil risiko kehilangan uang bila kuda itu sakit atau mati. Dua keluarga lainnya memiliki pengalaman berbeda. Mereka terpaksa menjual tanah lebih banyak lagi untuk mengongkosi anak-anak mereka yang telah dewasa yang kini menganggur di Kota Bandung”.
Mengenai sumber penghasilan pada awal 70an, penyakap yang masih tersisa di sawah beririgasi di Desa Wangisagara masuk dalam kategori maro, yang artinya pemilik tanah dan penggarap membagi rata hasil panen. Pada sistem maro tradisional, kedua pihak juga membagi rata ongkos-ongkos penggarapan. Hardjono (hlm. 127) menyebut bahwa konsep maro itu sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil Tahun 1960, dimana “penggarap harus mendapat sedikitnya setengah jumlah panen sesudah ongkos-ongkos bibit, pupuk, binatang pembajak, penanaman, panen, dan zakat dibagi rata; semua tenaga kerja (keluarga maupun buruh) ditanggung penyakap, sedangkan pemilik tanah membayar pajak IPEDA”. Namun, persoalan lainnya kemudian adalah harga gabah yang ditentukan rezim Soeharto, yang mana harganya terlalu minim bagi para petani Wangisagara.
"Banyak dari mereka ingin agar UUPBH 1960 diterapkan secara lebih konsisten, terutama pada masalah penanggungan beban biaya produksi, akan tetapi mereka tidak mau mengambil risiko dengan posisi mereka sekarang ini. Mereka tidak akan bersedia membentuk suatu perhimpunan atau organisasi untuk meningkatkan kekuatan kedudukan mereka sebagai penyakap, karena mereka sadar bahwa para pemilik tanah bisa dengan mudah membatalkan perjanjian penyakapan dan menggunakan tenaga buruh," tulis Hardjono (Hlm. 142). Ini pula yang kemudian membuat surplusnya tenaga kerja, bahkan umumnya terjadi di seluruh Jawa. Dan oleh karena perubahan teknologi yang kian beragam, sistem maro ini pun pada akhirnya hilang akibat inovasi dan penemuan terbarukan.
Bagi petani Wangisagara yang tersisa, alternatif lain yang memungkinkan adalah melakukan intensifikasi. Terutama bagi orang-orang yang tidak memiliki tanah, yang hanya dapat hidup dari pertanian. Namun kesemuanya ini terhalang oleh aktivitas tekstil yang nantinya menghasilkan limbah. Sebagaimana Hardjono mengungkapkan bahwa "peternak itik ikut merasakan akibat dari perkembangan teknologi. Meskipun penggunaan padi unggul memberikan kesempatan tiga kali setahun untuk mendapatkan makanan itik, penggunaan insektisida untuk membunuh tikus sering meracuni itik. Dekat Majalaya, pembuangan limbah dari pabrik tekstil ke saluran irigasi telah merugikan usaha peternakan itik maupun ikan" (Hlm. 154).
Intensifikasi pertanian lainnya mewujud pada penanaman sayuran secara komersial yang dimulai pada tahun 1979. Hal ini didorong oleh kerugian-kerugian padi unggul yang diserang hama wereng selama tahun 1978. Sementara hasil-hasil usaha non-pertanian pasca merosotnya sumber penghidupan dari penggunaan tanah dan sawah di Wangisagara adalah kain dan batu bata. Sejumlah warga yang menghasilkan kain belacu membeli benang dari seorang leveransir di wilayah Majalaya lainnya, yang juga membantu memasarkan kain produksi mereka. Namun mereka jadi harus bergantung sepenuhnya pada penilaian leveransir ini, dan harus menerima harga berapa pun yang ditawarkan. Usaha untuk memasarkan kain sendiri terbilang sulit sebab industri tekstil Majalaya besar sekali, dan persediaan benang dikuasai oleh usahawan-usahawan tekstil.
Hal ini mengingatkan pada konsep akumulasi primitif dan proletarisasi, yang dirumuskan seorang filsuf abad 19. Dia menyebut bahwa "akumulasi primitif tidak hanya terkait dengan masa lalu kelam kapitalis. Ia bukanlah proses yang sudah selesai, tetapi termasuk cara yang terus digunakan kapitalis modern untuk menciptakan proletariat di mana pun kapitalis ingin mengeruk laba". Meski demikian, penulis buku cenderung lebih memilih menggunakan pendekatan Malthusian, yang mana, agak kurang memadai, dan inilah yang sekaligus menjadi kelemahan buku ini. Tentu, wajar saja karena buku ini ditulis ketika rezim orde baru kian mengganas. Tapi, bagaimana menjelaskan pergeseran moda produksi sosial yang cukup determinan dalam perkembangan masyarakat Wangisagara, yang kemudian mengondisikan fenomena populasi-lebih?
Yang paling penting dalam pembahasan buku ini, saya kira, adalah bagaimana publik dapat melihat kerangka lebih luas gejala proletarisasi di Wangisagara ini, yang mana, dipicu kondisi struktural. Saat itu, kekurangan kas di awal Orde Baru mendorong Soeharto menjual kawasan hutan dan menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Tokoh reforma agraria Gunawan Wiradi menyebut bahwa melalui payung hukum ini Indonesia bukan lagi open door policy, tapi ibarat rumah tanpa dinding; pemodal bebas hilir mudik dalam rangka mengakumulasi kapital lewat eksploitasi sumber daya alam, aproriasi tanah, dan penggusuran rakyat.
Selain UU PMA, ada pula kebijakan rezim orba yang secara signifikan mengubah struktur sosio-ekologis rakyat Indonesia pada umumnya. Revolusi Hijau (RH) adalah salah satunya, yang dimulai ketika International Rice Research Institute (IRRI) didirikan di Los Banos, Filipina, di bawah bimbingan dan sponsor Rockefeller Foundation, dan Ford Foundation.
Bahkan implikasi dari proletarisasi ini juga turut terasa pada persoalan kultural. Hardjono (hlm. 73) menyebut bahwa “perasaan kerja sama masyarakat yang dulu pernah ada telah menurun”. Barangkali hal ini memang tidak dapat dielakkan, terutama saat kuasa atas kapital produktif seperti tanah dan air tidak diimbangi dengan peningkatan pada sumber penghidupan lainnya.
Sebagai refleksi, penting kiranya menutup uraian ini dengan sebuah kutipan dari Prof. Iman Soetikno, yang menyatakan bahwa “manusia membutuhkan tanah dan hasilnya untuk kelangsungan hidup, membutuhkan tanah untuk tempat hidup dan usaha, bahkan sesudah meninggal pun masih membutuhkan sejengkal tanah. Bagi suatu negara agraria, tanah mempunyai peran yang amat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.”
Informasi Buku
Judul: Tanah, Pekerjaan, dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat
Penulis: Joan Hardjono
Penerbit: UGM Press
Cetakan: 1, 1990
Halaman: 328 hlm.
ISBN: 9794201650