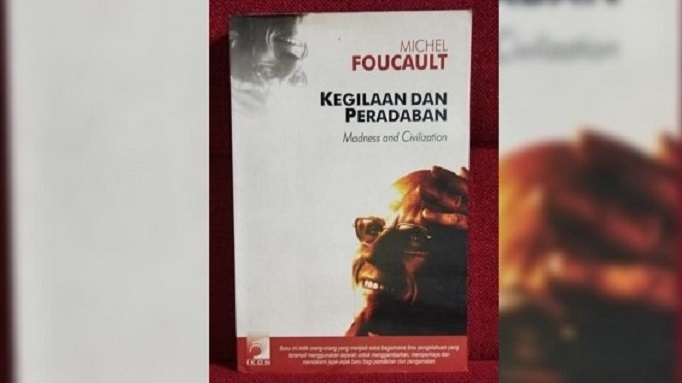SAWALA DARI CIBIRU #6: Wacana Parrhesia
Foucault mencatat sejarah kegilaan dengan sudut pandang yang berbeda. Narasinya atas sejarah peradaban manusia.

Hafidz Azhar
Penulis esai, sejak September 2023 pengajar di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan (Unpas), Bandung
14 Desember 2022
BandungBergerak.id—Saban Kamis, pukul lima subuh, saya sudah duduk di pelataran Stasiun Cimekar untuk menunggu ke berangkatan kereta menuju Cimahi. Meski fajar belum terlihat, beberapa kursi peron telah terisi penuh oleh calon penumpang. Deretan kursi itu disoroti lampu-lampu yang masih menyala terang. Bahkan tampak di depan saya, satu per satu orang memasuki antrean pembelian tiket. Saya pun mencuri perhatian. Kebanyakan dari mereka memasang muka yang bermacam-macam. Ada yang menampakkan wajah-wajah suntuk, ada pula yang terus melihat gawainya dengan sangat khusyuk.
Di tengah-tengah kesunyian itu terdengar obrolan yang berbisik-bisik. Segelintir remaja berseragam putih abu asyik bercakap-cakap, tetapi sebagian lain dari remaja yang berseragam itu hanya berdiri tanpa kata. Sebagaimana calon penumpang lain, ibu-ibu muda dan bapak-bapak berpakaian dinas ikut duduk bersamaan pada deretan kursi yang telah disediakan. Masing-masing dari mereka tertahan oleh kondisi yang cukup sunyi itu; menunggu aba-aba dari petugas mengabarkan kereta telah tiba.
Kedatangan kereta kurang dari setengah jam. Sebelum petugas memberikan aba-aba, saya membuka kembali lembaran buku yang sedang dibaca. Sejak dari rumah saya berniat untuk menamatkan buku bacaan di perjalanan. Sebab jarak yang ditempuh lumayan jauh. Kalau dihitung bisa menghabiskan waktu sekitar satu jam. Cukup bosan juga bila hanya digunakan untuk berdiam diri.
Dari Cimekar saya baca buku itu tipis-tipis. Buku yang saya baca, yakni Kegilaan dan Peradaban karya Michel Foucault. Sebetulnya sulit untuk memahami isi buku ini, karena penulisnya mencatat ihwal sejarah kegilaan dengan sudut pandang yang berbeda. Tahun 2002 buku itu terbit berdasarkan terjemahan dari versi Inggrisnya berjudul Madness and Civilization. Kendati sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karya Foucault ini masih sukar untuk dipahami. Ia tidak memuat sejarah berdasarkan rentetan alurnya yang umum ditulis. Justru dalam buku itu Foucault ingin mengangkat narasi lain dari sejarah peradaban manusia.
Memang belakangan ini saya sedang menggarap penelitian tentang wacana (discourse) Covid-19. Sejak penelitian tersebut saya harus berupaya keras memahami satu per satu karya-karya yang telah ditulis oleh Foucault. Seketika memori kolektif mengingatkan saya kembali pada masa dua belas tahun yang lalu, saat istilah wacana berkembang di lingkungan LPIK, di sela-sela diskusi rutin yang digelar setiap satu minggu dua kali. Saya ingat betul, kala itu kawan saya, Rifki, ikut mengemukakan pendapatnya tentang wacana keislaman. Di sana ia menyebut bahwa wacana keislaman tidak terikat oleh ruang dan waktu.
Apa itu wacana? Saya sendiri belum tahu. Di masa-masa berikutnya saya menangkap bila istilah wacana melingkupi semua aspek pengetahuan yang sedang diperbincangkan.
Jika merujuk pada definisi umum, kata wacana sendiri mengandung makna yang terikat dengan bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wacana bisa diartikan sebagai “komunikasi verbal”. Bisa juga berarti “kemampuan atau prosedur berpikir secara sistematis”, dan bahkan bermakna “pertukaran ide secara verbal”.
Baca Juga: SAWALA DARI CIBIRU #5: Berkubu dalam Filsafat
SAWALA DARI CIBIRU #4: Jalan Filsafat untuk Membaca Kritis
SAWALA DARI CIBIRU #3: Belajar Filsafat dari Keberagaman
SAWALA DARI CIBIRU #2: Merawat Tradisi, Menyemai Selebrasi
Parrhesia
Kaitannya dengan gagasan Foucault merujuk berdasarkan fungsinya dalam berfilsafat. Hal ini seperti tergambarkan pada Discourse and Truth: Problematization of Parrhesia (Wacana dan Kebenaran: Problem Parreshia), yang merupakan enam materi kuliah Foucault di Berkeley tahun 1983. Dalam materi kuliahnya itu, Foucault menguraikan berbagai hubungan parrhesia; baik yang berhubungan dengan kebenaran (truth), keterusterangan (frankness), kewajiban (duty), dan kritik (critics), atau juga yang berhubungan dengan bahaya (danger).
Bagi Foucault sendiri parrhesia menunjukkan arti umum yang tidak terpisah dari konteks lisan. Di situ ia mengartikan to say everything. Foucault juga menjelaskan bahwa parrhesia digunakan untuk mengatakan semua hal yang ada dalam pikirannya. Dalam parrhesia seseorang tidak menyembunyikan apa pun. Bahkan ia membuka sepenuhnya isi hati maupun benak pikirannya untuk didistribusikan kepada orang lain melalui wacananya (Foucault, 1983).
Bukan hanya itu. Dalam parrhesia seorang pembicara mesti memberikan penjelasan yang lengkap dan tepat terkait apa yang ada dalam pikirannya. Hal ini dilakukan agar si pendengar bisa memahami secara tepat pikiran yang ingin disampaikan oleh si pembicara. Dari sini kemudian parrhesia mengacu pada hubungan di antara pembicara dengan apa yang dikatakannya. Sebab, dalam parrhesia, pembicara membuat kejelasan dari pendapatnya sendiri, dan justru menghindari segala bentuk retorika yang akan menutupi apa yang dia pikirkan (Foucault, 1983).
Pada materi kuliah itu Foucault juga menjelaskan bahwa dalam parrhesia pembicara menekankan dirinya sebagai subjek pengucapan. Dengan kata lain, subjek pengucapan mengacu pada dirinya sendiri sebagai pendapat yang ia rujuk. Karena, menurut Foucault, aktivitas berbicara (speech activity) berkaitan dengan apa yang dipikirkan oleh subjek pengucapan (Foucault, 1983).
Dengan demikian, parrhesia, istilah yang dihadirkan Foucault ini memiliki maksud agar seorang pembicara mengatakan semua hal berdasarkan kebenaran, kendatipun dalam prosesnya memiliki risiko. Lantas dari mana istilah parrhesia itu muncul?
Menurut asal-usulnya, Foucault mengambil kata parrhesia dari khazanah sastra Yunani yang hadir pertama kali pada abad 400-an Sebelum Masehi. Dalam penelusurannya Foucault memperoleh tiga bentuk kata parrhesia: pertama, parrhesia sebagai bentuk nomina; kedua, parrhesiazomai sebagai bentuk kata kerja; dan ketiga, parrhestiastes kata yang tidak banyak ditemukan dalam teks-teks klasik (Foucault, 1983).
Selain itu, dalam bahasa Inggris parreshia juga biasa diartikan dengan free speech (kebebasan berbicara), dalam bahasa Perancis francparler (berbicara langsung), dan dalam bahasa Jerman freimuthigkeit (keterusterangan); sedangkan orang yang menggunakan parrhesia disebut parrhesiastes, yakni orang yang mengatakan kebenaran (Foucault, 1983), sehinggga kita bisa menangkap kata kunci bahwa parreshia berkaitan dengan segala macam wacana lisan. Itulah salah satu penjelasan Foucault mengenai wacana. Dalam konteks ini tentu saja Foucault memberikan konsep yang khas mengenai speech activity, meskipun uraian ini hanya bagian terkecil dari kategori wacana yang ia suguhkan. Sekali lagi, tidak mudah untuk memahami pemikiran Foucault. Sebab, ia ingin menampilkan narasi-narasi di luar perkiraan banyak orang.
*Tulisan Sawala dari Cibiru merupakan bagian dari kolaborasi antara BandungBergerak.id dan UKM Lembaga Pengkajian Ilmu Keislaman (LPIK)