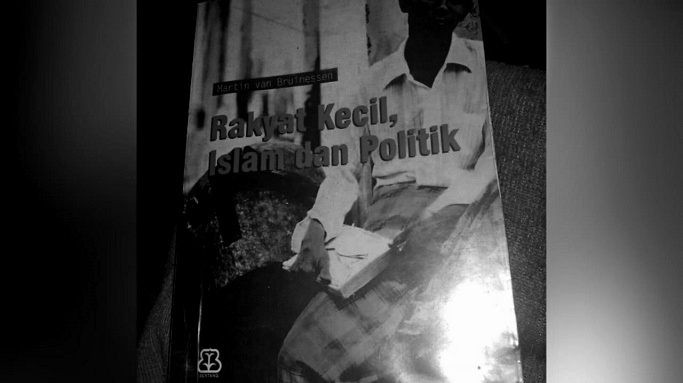BUKU BANDUNG (29): Melihat Muramnya Kota Kembang Era 80-an dari Kacamata Martin Van Bruinessen
Jika pada buku dan tulisan peneliti lain kita kerap menemui Bandung dalam bingkai romantik, maka Martin Van Bruinessen memampang sisi muram kota kembang.
Penulis Yogi Esa Sukma Nugraha16 Januari 2022
BandungBergerak.id - Banyak peristiwa sosial dan politik yang membuat gaduh publik era 80-an. Harmoko melarang lagu "Hati yang Luka" yang dinyanyikan oleh Betharia Sonata. Rhoma Irama dicekal tampil di TVRI, lagunya disingkirkan dari "tangga lagu" RRI, peredaran kasetnya dihambat, dan izin konsernya dipersulit. Persib sukses menjuarai Perserikatan musim 1986 usai mengalahkan Perseman Manokwari di babak final. Nista, Maja, Utama.
Dua tahun sebelumnya, tepatnya 12 September 1984, ratusan umat Islam tewas akibat bentrok dengan tentara. Sebulan kemudian, 27 Oktober 1984, pascabeberapa wilayah termasuk Bandung dilanda demam dikarungan —alias petrus, majalah Tempo memuat sebuah artikel yang merupakan hasil penelitan lapangan di sebuah kampung perkotaan di Bandung. Artikel inilah yang menjadi titik tolak pembahasan kita nantinya. Isinya mengisahkan ragam persoalan kehidupan sehari-hari warga biasa yang, seperti halnya warga kota lain saat itu, sedikit banyak terdampak rencana modernisasi besar-besaran. Bandung sendiri pada saat itu mengusung program Bandung Atlas: aman, tertib, lancar, sehat. Artikel ini nantinya menjadi bagian pertama buku yang diterbitkan penulisnya, Martin van Bruinessen, yang diberi judul Rakyat Kecil, Islam dan Politik.
Di dalam bukunya, Bruinessen memaparkan seluruh hasil kajiannya ketika melakukan riset di area sekitar Pagarsih, Jamika, salah satu sudut kota kembang, selama kurun waktu 1980-1990. Selama melakukan penelitian itu, Bruinessen tinggal dan menjadi bagian dari penduduk sebuah kampung kumuh bernama Sukapakir. Dia menjalani kehidupan dengan keluarga-keluarga kelas menengah-bawah yang —dalam penggambarannya— seakan tidak pernah dapat keluar dari kemiskinan kecuali memenangi undian Porkas.
Semua narasumber dalam kajian Bruinessen ditulis dengan nama bukan sebenarnya, tetapi kisah yang diceritakan merupakan kisah nyata, berdasar pengamatan langsung dan wawancara dengan pendudukan Sukapakir dalam waktu yang tidak singkat. Hasil kajiannya di Bandung inilah kemudian yang mengantarnya untuk terlibat dalam penelitian-penelitian selanjutnya mengenai ulama dan pesantren di Indonesia. Di bab awal bukunya, kita serasa dituntun kembali ke suasana pemukiman di tengah Kota Bandung era 80-an, lengkap dengan cerita-cerita getir kehidupan warganya.
Berteman dengan Kegagalan
Gelombang migrasi tahun 50-an menjadi titik awal kajian dalam buku Rakyat Kecil, Islam dan Politik Martin van Bruinessen. Zaman ketika DI merajalela di kawasan selatan. Melalui proses yang panjang, Martin van Bruinessen menunjukkan sisi lain dari kebijakan "penertiban". Dalam amatannya, hal itu merupakan suatu proses pemiskinan dari lapisan masyarakat yang pendapatannya tergantung pada sektor informal. Tentu ada sejumlah faktor lain, di antaranya, kedatangan ataupun perpindahan penduduk ke wilayah tersebut. Perpindahan tersebut diikuti dengan sempitnya lapangan pekerjaan. Alhasil, penduduk terpaksa menjalankan pekerjaan informal, seperti membuka warung, berdagang makanan kecil, atau buruh panggilan.
Sukapakir termasuk daerah terpadat di Bandung. Penghuninya pada saat itu, sebagaimana dijelaskan di muka, adalah pekerja informal: tukang-tukang bakso, tukang bubur, pengupas bawang, pedagang kaki lima, tukang becak, pelacur, dukun. Menurut sensus penduduk 1980 —sebagaimana dicatat Bruinessen dalam bukunya —tingkat kepadatan Sukapakir 900 orang lebih per hektar. Satu bangunan rumah kebanyakan dihuni oleh dua, tiga, bahkan empat keluarga. Bukan hal aneh apabila dua keluarga —masing-masing ayah, ibu, dan beberapa anak— menempati satu kamar (bukan rumah!) yang sama. Dengan sendirinya, kondisi sanitasi dan kesehatan runyam. Penyakit menular cepat membiak. Lebih lagi, belum tahu pencegahannya. Memang ada dua MCK saat itu, tapi tersedia hanya untuk 335 keluarga.
Selain itu, penduduk harus pula membayar guna mendapat setetes air bersih. Pada musim kemarau, selalu saja ada yang kena muntaber. Tingkat kematian anak tinggi. Dan jangan tanya mengapa mereka tidak pergi ke dokter —atau bahkan puskesmas. Karena, ya, dukun mereka asumsikan lebih berguna. Tentu saja kenyataan seperti ini layak dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan kiwari untuk dapat mengetahui informasi tentang tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan dalam menentukan alokasi sumber daya program.
Dalam catatan lainnya, Bruinessen menyimpulkan bahwa kemiskinan dan kepadatan Sukapakir sebenarnya bukan keunikan —di seantero Bandung, sangat mudah ditemukan daerah semacam ini. Keadaan mereka bahkan kadang lebih parah. Diperkirakan 10 persen penduduk Bandung tinggal dalam kondisi serupa. Ciri khasnya, penduduknya kebanyakan pendatang —dari desa— yang biasanya memilih tempat ini untuk mencari kontrakan murah. Ada juga orang yang pindah dari kawasan tengah Bandung ke sukapakir ini, dan biasanya karena keadaan ekonomi yang mendesak. Jadi hampir setiap bulan, ada yang pindah, ada yang datang.
Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan nasional. Misal, salah satunya, dampak revolusi hijau. Pertanian kian mahal, beberapa orang kaya membeli tanah petani. Dan akibatnya, jumlah petani tanpa tanah alias petani gurem meningkat. Ini membuat kehidupan di kota menarik perhatian. Persoalan utama "Revolusi Hijau", upaya pemuliaan tanaman padi dalam pertanian modern, menuntut investasi besar —antara lain jumlah pupuk, penyemprotan hama, dan pengairan. Ini juga mempercepat proses polarisasi pertanian perdesaan. Bisa dimengerti mengapa antara tahun 60-70-an banyak pendatang baru di Sukapakir, terutama yang dari daerah "Revolusi Hijau" dilaksanakan: Cirebon, Tegal, dan Indramayu. Rombongan 60-70-an itu sebagian besar bekerja sebagai sopir, kenek, dan centeng. Wanitanya menjadi pembantu. Yang unik, mayoritas pendatang dari Brebes dan Tegal menjadi tukang bakso. Sedikit yang memilih bidang lain (Hlm. 14-15).
Namun seiring perkembangan, pedagang kecil lekas bertambah, dan otomatis persaingan menjadi tajam. Ketika harga bahan-bahan di pasar naik, harga komoditas yang bakal dijual sudah sulit sekali ikut naik. Akibatnya, keuntungan sulit diraih. Semuanya tercatat dengan detil dalam buku Bruinessen ini. Kita menemukan kedalaman, juga pergulatan dalam menjalani kerasnya hidup. Meski seringnya berjalan sia-sia.
Kisah muram sebelumnya itu bukanlah kasus-kasus yang paling menarik dibanding banyak kasus lain di Sukapakir. Dalam bukunya ini, Bruinessen sepertinya tidak hanya minat menjadikan kemelaratan sebagai bahan penguras air mata. Artinya, tentu banyak pula yang sukses. Tapi —sebagaimana Bruinessen menuliskan— mereka "hijrah" dan tinggal di lingkungan lebih layak. Karenanya, cerita tentang mereka yang menetap di Sukapakir adalah kisah orang-orang yang senantiasa berikhtiar, tetapi terus-menerus gagal.
Baca Juga: BUKU BANDUNG (26): Tjiumbuleuit, antara Romantisme dan Realitas
BUKU BANDUNG (27): Rekam Jejak Bosscha dari Komunitas Sahabat Bosscha
BUKU BANDUNG (28): Terusir, Kisah Orang-orang Tergusur di Kota Bandung
Kemiskinan Struktural
Martin van Bruinessen melakukan komparasi kajiannya dengan antropolog lain, Oscar Lewis, yang banyak melakukan pengamatan tentang orang-orang miskin di kawasan slum Meksiko dan Puerto Rico. Lewis merumuskan konsepsi "budaya kemiskinan" untuk sikap dan pandangan hidup yang ditemukannya di sana. Dalam rumusannya, dijelaskan bahwa kemalasan dan ketidakpercayaan pada diri dan orang lain sebenarnya bukan penyakit yang sudah menjadi watak. Melainkan justru adaptasi terhadap situasi yang dihadapi, selain merupakan jalan satu-satunya untuk bertahan dalam penderitaan. Bruinessen sampai pada kesimpulan yang lebih kurang serupa. Pasalnya, sikap demikian banyak dijumpai di Sukapakir.
Situasinya memang tidak separah yang digambarakan Lewis di Meksiko dan Puerto Rico, tetapi sedikitnya gambaran ke arah sana lambat laun tampak semakin terang. Sudah terlihat banyak orang memberi reaksi sama: apatis. Partisipasi mereka dalam kegiatan sosial rendah. Seperti juga di Amerika tengah, gotong-royong dalam praktiknya sedikit sekali. Orang cenderung menjadi egoistis dan selalu curiga. Sikap saling tidak mempercayai itu tergambar dari cara meyakini guna-guna: semua musibah —sakit, atau usaha yang gagal— dihubungkan dengan guna-guna dari mereka yang iri. Jarang sekali memikirkan masa depan, perhatiannya melulu pada hari ini. Dan dengan sadar meyakini bahwa rencana masa depan tak ada artinya. Dengan demikian, itu juga berarti mereka tidak mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di hari esok. Dan karena itu, bersikap spontan, alias gampang nekat. Ada pun hal lainnya, yakni, langsung bereaksi terhadap apa yang terjadi tanpa menimbang konsekuensi. Dan cukup girang dengan menikmati hal-hal yang amat sepele, yang tidak ada artinya bagi orang lain. Bisa juga sangat tidak sabaran. Bila melihat sesuatu yang disukai, dengan segera ingin memiliki. (Hlm. 22-23)
Cara memandang yang tidak jauh ke depan ini cukup mengondisikan perkara pinjam-meminjam uang. Sebagaimana di daerah slum lainnya, nyaris semua orang berutang tanpa khawatir apakah bisa membayar. Ada himpitan yang diledakkan lewat sifat-sifat semacam itu. Umumnya, dulu orang di Sukapakir memang selalu berharap akan tibanya hari baik buat perekonomian mereka. Hal ini sulit, sebab, ada kenyataan pahit lain. Untuk menopang sekolah anak, misal, beberapa keluarga sering berhubungan dengan rentenir. Jarang ada yang berpikir untung ruginya.
Dengan bunga selangit, 20-30 persen, sungguh sulit untuk dapat mengembalikan pinjaman. Jika dibanding bunga bank resmi atau pegadaian milik pemerintah, bunga lintah darat itu sungguh mengerikan. Tapi bagi penduduk Sukapakir, mustahil meminjam uang lewat bank. Diperlukan macam-macam persyaratan yang membuat mereka putus asa sebelum mencoba. Yang layak digarisbawahi, sedikit sekali yang menyadarinya sebagai proses alamiah yang wajar. Sebagian besar —bahkan yang mengenyam bangku sekolahan— beranggapan bahwa kemerosotan ekonomi mereka disebabkan oleh ilmu hitam dan seterusnya itu, selain oleh tibum.
Belakangan, hal ini dipertegas penelitian terbaru lembaga riset Smeru Institute yang menunjukkan bahwa anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung berpenghasilan lebih rendah ketika mereka dewasa. Penelitian yang telah dipublikasikan di makalah internasional Asian Development Bank (ADB) menunjukkan pendapatan anak-anak miskin setelah dewasa 87 persen lebih rendah dibanding mereka yang sejak anak-anak tidak tinggal di keluarga miskin.
Penelitian itu juga menunjukkan bahwa keluar dari jerat kemiskinan tidak semudah yang banyak orang kira karena kemiskinan yang terjadi pada anak-anak berkaitan dengan kondisi kemiskinan keluarganya. Kemiskinan keluarga akan membatasi akses anak-anak mereka terhadap berbagai kesempatan (misalnya untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan) yang sebenarnya diperlukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Perbedaan kesejahteraan orang tua menyebabkan kondisi ekonomi anak-anak mereka tidak berada pada garis awal yang sejajar.
Suatu hal yang juga diafirmasi David Harvey dalam The Culture of Poverty: An Ideological Analysis. First Publisheb (December 1, 1996) menyatakan bahwa konsep Oscar Lewis sering disalahartikan sebagai teori yang cenderung menyalahkan para korban kemiskinan atas kemiskinan mereka. Dalam esainya, The Culture of Poverty: An Ideological Analysis, dia mengoreksi kesalahpahaman ini. Menggunakan pendekatan sosiologis, ia mengeksplorasi asal-usul kesalahan pembacaan Lewis ini, dan secara kokoh didasarkan pada kritik Marx terhadap kapital dan kontradiksi-kontradiksi produktifnya.
Hasilnya, tentu saja ini bukan sekadar perkara malas atau kurang inisiatif saja. Ada prakondisi lebih luas yang sifatnya struktural. Dengan demikian, meluasnya pemiskinan di kota tidak bisa dilihat memakai perkakas moral. Lebih dari itu, tidak pula hanya terjadi di ruang manufaktur, melainkan telah menyebar pada semua pekerja informal lainnya di kota-kota yang memproduksi “nilai”.
Radikalisme dan Kemiskinan
Di buku Rakyat Kecil, Islam dan Politik Martin van Bruinessen, terselip pula cerita-cerita menarik yang menceritakan awal mula kuliner dan jajanan pasar yang sekarang dikenal luas seperti siomay dan bakso tahu. Kemudian tersaji juga cerita bagaimana sebuah profesi biasanya identik dengan latar belakang asal si pelaku usaha, seperti perajin emas yang berasal dari kampung Kamasan Rajapolah, Tasikmalaya. Atau penjelasan yang menguraikan mengapa Indramayu sering diasumsikan sebagai penyuplai terbesar tenaga kerja untuk red light district di Kota Bandung. Jika pada buku dan tulisan peneliti lain kita kerap menemui Bandung dalam bingkai romantika keindahan atau keningratan, justru dalam buku Bruinessen, terpampang sisi muram kota kembang.
Setelah bercerita tentang Sukapakir dan liku hidup warganya, buku ini melaju ke bagian kedua yang terdiri dari beberapa esai mengenai politik Islam di Indonesia yang pernah terbit tahun 90-an. Bruinessen melihat bagaimana peran ulama dan cendekiawan muslim saat itu turut membentuk wajah politik di Indonesia. Hanya saja, terdapat beberapa hal yang, sulit sekali kiranya saya untuk sependapat dengannya. Oleh karenanya, biar pembaca sendiri sajalah yang menafsirkannya nanti.
Tulisan-tulisan Bruinessen dalam bab ini sulit untuk dapat dilepaskan dari konteks politik Orde Baru terhadap umat Islam, tapi menjadi menarik karena di satu sisi kegiatan umat Islam diawasi dan dikontrol agar tetap jinak, di satu sisi represivitas Orde Baru juga telah memancing dinamika pergulatan intelektualitas yang luar biasa di kalangan para cendekiawan muslim Indonesia.
Wacana radikalisme dibahas pula di salah satu tulisan di bagian ini. Bruinessen memulainya dengan upaya meredefinisi fundamentalisme dari berbagai narasi politik dan perspektif. Pemaknaan fundamentalisme berpengaruh pada analisa bagaimana gerakan fundamentalis tersebut dijelaskan. Dari penelitian lapangan langsung, Bruinessen sampai pada penjelasannya sendiri mengenai kelompok garis keras. Menurutnya, radikalisme sukar ditemui dari lingkungan miskin, namun tumbuh menyemai di kalangan orang-orang yang lebih berada, lebih berpendidikan, dan mempunyai ambisi yang lebih besar. Dengan kata lain, radikalisme justru digerakkan oleh orang-orang yang terkategori kelas menengah-atas, mereka yang mempunyai waktu luang, dan kebutuhan dasarnya sudah tercukupi.
Informasi Buku
Judul: Rakyat Kecil, Islam dan Politik
Penulis: Martin Van Bruinessen
Penerbit: Yayasan Bentang Budaya
Cetakan kedua, April 1999
Tebal: 367 halaman